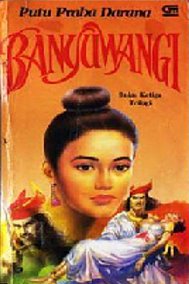Bab 6 : Sri Tanjung
Tahun seribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Masehi belum habis. Kemarau panjang kembali datang. Seolah hujan enggan datang. Debu merajai suasana. Dentam martil pemecah batu terdengar di setiap sudut kota Banyuwangi, yang beberapa hari lalu masih disebut orang sebagai kota Sumberwangi.
Dahulu orang mengenal Tumenggung Singamaya sebagai pahlawan perkasa, maka sekarang nama itu tak boleh lagi disebut pahlawan. Semua orang diharuskan mengakui si Tumenggung Wiraguna-lah pahlawan pembangunannya. Secara pelan-pelan kawula diharuskan menghilangkan ingatannya terhadap Wong Agung Wilis. Harus dikuburkan nama itu. Karena orang itu cuma pandai ngomong, dan menimbulkan peperangan, tidak memberikan kedamaian, tidak memberikan kesejahteraan. Wong Agung Wilis selama menjadi kepala pemerintahan di Blambangan cuma membawa kemiskinan dan peperangan.
Terus saja itu ditiupkan. Dari mulut para punggawa. Para hulubalang. Para bekel, para jagatirta (pengatur pengairan) para jagabaya (kepala keamanan atau pengatur keamanan desa). Pendek kata semua orang yang memegang jabatan, harus membicarakan seperti itu. Mau atau tidak. Setuju atau tidak! Jika mereka tidak ingin kehilangan jabatannya harus membicarakan itu. Sehingga orang Blambangan tahu, bahwa Wiraguna benar-benar pembawa kesejahteraan bagi seluruh kawula Blambangan. Di bawah payung kekuatan Kompeni, Wiraguna membuat semua orang tidak berkutik.
Di bawah pengawalan Kompeni, ia sendiri mengadakan peninjauan ke desa-desa yang sekarang dihuni oleh pendatang baru. Umumnya orang yang berasal dari Mataram. Sering ia mengadakan percakapan langsung dengan para petani. Juga dengan para pekerja gotong-royong yang membangun kota Banyuwangi itu. Ia memamerkan senyumnya di mana-mana. Dengan ramah dan terampil Wiraguna memberikan petunjuk-petunjuk, bagaimana melaksanakan pembangunan Blambangan secepatnya. Terutama Banyuwangi.
Para pembantunya tahu bahwa kawula Blambangan yang pribumi seperti diri mereka sendiri-kebanyakan mulai memberi penilaian. Membanding-bandingkan. Memang sudah jarang terdengar kidung pujian untuk mengagungkan dan fnemuja Wong Agung Wilis. Tapi sering terlontar nada sumbang jika orang berbicara tentang Wiraguna. Apa sih bisanya orang macam itu? Seorang penguasa Blambangan tapi tidak pernah terdengar ia bicara Sanskerta, tidak juga bisa berbahasa Bali. Apa yang dia bisa?
Namun di tengah suara sumbang yang terdengar di hampir setiap telinga, pembangunan ibukota Blambangan berjalan terus. Ia tidak pernah mau mendengar semua itu. Ia harus mewujudkan impiannya, Banyuwangi! Bukan cuma itu. Sri Tanjung sebagai garwa padmi! Mengapa baik Singa Manjuruh maupun Juru Kunci tak berhasil memboyong Sri Tanjung? Ah, mungkin saja setelah mereka memandang wajah Sri Tanjung hati mereka rontok. Dan ada keinginan mengambil wanita itu menjadi istrinya? Jika demikian, aku harus menindak mereka. Satu per satu harus ditindak. Sebab jika tidak, mereka akan menghalangi kehadiran Sri Tanjung. Apa kata para tamu pada waktu wisudaku nanti? Apa kata mereka? Aku tidak akan dapat menjawab jika mereka bertanya, mana garwa...? Oh, Sri Tanjung, Sri Tanjung! Betapa sulitnya memetik sekuntum mawar yang tumbuh di tengah belantara itu!
Tapi aku harus bijak. Harus. Karenanya ia panggil Juru Kunci. Ia perhatikan wajah bopeng patihnya itu tajam-tajam. Arinten, kakaknya yang' tinggal di Pakis, mengatakan bahwa Juru Kuncilah yang berjasa membuatnya naik tahta di "Blambangan. Dia yang semula ditunjuk menjadi adipati. Dan masih banyak lagi pujian tentang orang ini dari kakaknya.
Termasuk jasanya meruntuhkan kepercayaan VOC pada Jaksanegara. Ahai, jika ia mampu berbuat itu pada Jaksanegara, maka ia akan sanggup pula berbuat semacam itu padanya. Ah, sialnya lagi rumahnya di Pangpang. Tentu ia selalu berhubungan dengan Tuan Residen. Baik kepada Schophoff maupun Pieter Luzac Juru Kunci memang amat dekat. Dan yang wajib diperhatikannya, Juru Kunci sering mempersembahkan padanya wanita-wanita cantik. Tentu itu juga dilakukannya pada Schophoff dan Pieter Luzac. Aku perlu hati-hati menghadapi seorang macam dia.
"Yang Mulia, hamba sangat prihatin dengan kegagalan Yang Mulia membawa calon garwa padrni," ia memulai setelah Juru Kunci duduk di depannya.
"Ampunkan hamba, Yang Mulia. Sudah hamba laporkan beberapa hari lalu. Sebaiknya Yang Mulia berpikir yang lain."
"Kenapa?"
"Ampun, apakah yang dimaksud itu Mas Ayu Tunjung, putri..."
"Aku telah mengubah namanya menjadi Sri Tanjung. Tak perlu lagi memanggilnya dengan nama Ayu Tunjung.
Bukankah ia patut jadi seorang garwa padmi?"
"Tentu sepatut-patutnya. Bahkan lebih dari itu, andaikata beliau menjadi Sri Ratu, tentu lebih gilang-gemilang dari Sri Maha Ratu Suhita, Rani Majapahit itu." Tertawa. Wiraguna juga.
"Tapi sayang..." Juru Kunci mengejutkan. "Kenapa? Apanya yang sayang? Dia masih Hindu?"
Wiraguna menarik alis sebelah kirinya ke atas sambil memandang tajam.
"Ampunkan hamba jika berkata terus-terang." "Ya. Katakan!" "Beliau sendiri yang berkata, bahwa tidak akan duduk di samping Yang Mulia!"
"Apa katamu?" Wiraguna melompat dari tempat duduknya.
Sembahyang tahajud tiap malam tanpa mengenal kantuk masih gagal mengais hati gadis itu.
"Ampunkan hamba, Yang Mulia." Juru Kunci gelisah. "Apa alasannya? Apa alasannya?" Suara Wiraguna keras.
"Ampun, Yang Mulia! Tapi sepenglihatan hamba beliau saat ini ada di pangkuan Rsi Ropo."
"Ya, Aliahku! Ya, Tuhanku!" Wiraguna menyebut seperti ada petir yang mengejutkannya. Tiba-tiba tubuhnya seperti kehabisan tenaga. Seperti daun bambu kering rontok dari dahannya Wiraguna terkulai, dan kembali duduk di kursinya. Beberapa jenak mereka berdiam. Desah napas Wiraguna terdengar satu-satu.
"Sri Tanjung, Sri Tanjung! Mengapa kau perlakukan aku seperti ini, Wong manis...," Wiraguna mengiba. "Kau runtuhkan semua impianku! Hua-duuh..."
"Sabar, Yang Mulia!"
"Waktu aku bersua pertama, Rsi Ropo tidak muncul. Tidak!
Pasti ia bohong!"
"Tidak, Yang Mulia. Ia tidak bohong. Hamba bersua dengan Rsi Ropo. Dan masih seperti dulu waktu Yang Mulia Jaksanegara memerintah, ia mengajar pada seluruh orang Songgon."
"Seluruh orang Songgon? Di sana tidak banyak kawula berhimpun."
"Justru kita melakukan pagar betis, kini Songgon menjelma menjadi satu negeri yang subur makmur!" "Tidak mungkin! Mana ada kejadian seperti itu!" kembali ia mengangkat alis kirinya.
"Hamba menyaksikan mereka sedang panen. Padi mereka bertumpuk di halaman. Bukankah suatu pertanda bahwa lumbung mereka penuh? Dan bukankah itu suatu pertanda bahwa mereka tak kekurangan?"
"Setan! Seperti itu mereka tidak punya kesadaran sama sekali membayar upeti! Dianggapnya Songgon milik moyang mereka? Aku akan lapor pada Residen! Tentu si setan Ropo itu penghasut-nya. Kita perlu mengirimkan pasukan ke sana."
"Sabar, Yang Mulia. Apakah itu menguntungkan?
Pengerahan pasukan berarti penambahan biaya. Sedang untuk pembangunan ibukota ini saja kita sudah berutang pada VOC begitu banyak."
"Jadi? Aku gagal mempersunting Sri Tanjung?" Entah apa yang dirasakan oleh Raden Tumenggung Wiraguna itu, mendadak dadanya sesak, kepalanya berdenyut-denyut, matanya sembab. Tak terasa, air matanya meleleh perlahan.
"Sri Tanjung, Sri Tanjung...," keluhnya perlahan. Ia tahan agar tidak menangis. Tapi justru menahan itu Juru Kunci yang sejak tadi menunduk itu jadi terkejut. Isak lelaki muda itu menarik dagunya untuk mendongak. Selintas Juru Kunci jadi teringat pada Ayu Tunjung. Benar-benar awas mata perempuan cantik itu. Mas Ngalit cuma pandai berlindung di balik pinggul wanita! Tak layak memakai gelar Wiraguna! Dan kini tampak Wiraguna bersandar sambil memalingkan wajahnya. Sebelah tangan bertopang pada tangan kursi. Dan pada tangan itu dagunya bertumpu. Sedang sebelah lagi tangannya dipergunakan menghapus air mata itu. Pilar-pilar perkasa pendapa itu menjadi saksi bisu atas keringkihan hati sang Adipati. Juga Juru Kunci membisu.
"Kenapa Singa Manjuruh tak melapor sejak awal?" "Itulah, Yang Mulia," Juru Kunci kembali berani berkata. "Ya! Aku heran."
"Mungkin suatu persekongkolan untuk mempermalukan kita."
"Jika demikian, perangkap perlu kita pasang. Kita panggil Singa Manjuruh, kemudian kita masukkan penjara. Jika perlu digantung."
"Tidak, Yang Mulia. Singa Manjuruh kita jadikan umpan untuk bisa memancing Sri Tanjung. Bukankah cuma beliau kita butuhkan?"
"Tapi bagaimana dengan suaminya?"
"Serahkan pada hamba. Dia memang perlu kita serahkan pada Kompeni. Tapi tidak kita serbu ke Songgon. Itu akan memulai perang baru yang akan memakan biaya besar."
"Aku dengar ayahmu mati juga karena ulah orang itu. Lari dari bilik penahanan di Pangpang dan ayahmu sebagai gantinya."
"Tidak salah, Yang Mulia. Karena itu utang darah akan dibayarnya di tiang gantungan."
"Baiklah, Yang Mulia. Aku cuma ingin Sri Tanjung sebagai Garwa Padmi. Lain tidak!"
"Hamba, Yang Mulia."
Juru Kunci meninggalkan Wiraguna sendiri. Tak seorang selir pun diperkenankan menghadap. Kegundahan hati mengundang tangis. Memang tidak lazim bagi lelaki.
Barangkali memang tidak pernah ada lelaki Blambangan menangis karena menghadapi beban yang gunung-gemunung sekalipun. Tapi kenyataan ini terlalu, ya, terlalu berat bagi Wiraguna. Seorang muda, tampan, kaya, ditolak oleh seorang gadis. Dan Sri Tanjung itu... memilih seorang Rsi. Apa sih bahagianya menjadi istri seorang berpengetahuan tinggi tapi miskin seperti itu? Tidak punya kekuasaan? Sungguh tak masuk akal. Ini tentu terkena guna-guna. Atau Rsi Ropo itu amat tampan? Tiba-tiba saja ia ingin tahu wajah sang Rsi. Maka segera ia memerintahkan Su Lie Hwa, selirnya, untuk menjumpai Juru Kunci. Dengan pesan menghadapkan Rsi Ropo sebelum digantung.
Sementara itu Juru Kunci telah memasukkan Singa Manjuruh ke dalam bilik penahanan di Banyuwangi. Diawali dengan memanggilnya. Kemudian ia didakwa mempermalukan Adipati karena telah melaporkan kepalsuan. Singa Manjuruh tidak dapat mengelak. Untung ia sudah memberikan petunjuk pada istrinya apa yang harus dilakukannya bila ia kemudian hari ditangkap. Karena memang ia memberikan keterangan palsu tentang Songgon.
"Kenapa harus menipu, Kakang?" Istrinya gelisah. "Aku tak sampai hati mereka diserbu oleh pasukan
Kompeni. Ah, mereka sudah damai "
"Tapi bukankah jika Raden Tumenggung sendiri ke sana, akan menimbulkan masalah buat Kakang? Buat kita, Kang? Lihatlah perut ini!" istrinya menunjuk perutnya. Makin membengkak. Janin makin besar saja. Sekalipun tidak diberi makan, ia dengan tiada sesadar ibunya terus saja makan dari jatah yang dimakan oleh ibunya.
"Masalah akan selalu timbul. Cepat atau lambat. Sebab Mas Ayu Tunjung pasti menolak. Karena ia sudah punya suami.
Wiraguna tidak akan mau melihat kenyataan ini. Jika kukatakan itu terus-terang, maka saat itu juga kepalaku akan dipenggal. Nah, apakah tidak lebih baik jika aku mengulurnya sampai sekarang?"
"Lalu?"
"Kau pimpin Singa Juruh ini sampai anak kita ini dewasa." "Ah..." "Inilah kenyataan. Barangsiapa tidak mau menerima kenyataan maka ia akan menelan semua yang ada dalam kehidupan ini dengan rasa pahit. Tidak apa, Sayangku!
Mantrolot, temanku itu, akan membantumu."
Pembicaraan itu terjadi dua hari lalu. Dan perempuan yang sedang hamil itu menunggu. Menunggu. Tapi suaminya tak kunjung kembali.. Naluri keperajuritan yang diajarkan suaminya selama ini muncul kembali. Tidak! tiba-tiba kata hatinya. Suaminya tidak boleh mati dengan tanpa pembelaan. Setelah itu ia segera memanggil semua pembantu suaminya. Blegok yang diserahi jabatan jagatirta, Mantiri si jagabaya, Manaragil sebagai wakil bekel. Semua heran mendengar kentongan yang dipukul tiga kali sebagai isyarat bagi panggilan buat mereka. Namun dengan tanpa berpikir lebih jauh mereka menghadap ke rumah Singa Manjuruh.
Tapi lelaki itu tidak ada. Cuma seorang wanita muda yang sedang hamil. Nyi Singa Manjuruh, begitu sebutan wanita itu sekarang, duduk dengan wajah bermendung. Mereka datang satu-satu. Nyi Singa Manjuruh tidak berkata sesuatu sebelum semua berkumpul. Dan Manaragil yang datang terdahulu, tidak berani bertanya apa-apa. Ia tahu perasaan Nyi Manjuruh sedang gundah. Tak terlalu lama memang mereka menunggu yang lain. Tapi rasanya seperti setahun. Angin bebas berkeliaran di pendapa itu. Membuat suasana siang itu tidak begitu gerah. Sekalipun begitu Nyi Singa Manjuruh merasakannya sebagai neraka. Kegerahan yang ditimbulkan oleh janin dalam perutnya sudah merupakan aniaya tersendiri. Sekalipun saat pertama ia tahu bahwa sudah berbadan dua, itu merupakan saat yang paling bahagia dalam hidupnya.
Demikian pula untuk suaminya. Ble-gok orang terakhir yang memenuhi panggilannya kini telah naik ke pendapa rumahnya.
"Sudah dua hari Kakang Singa Manjuruh tidak pulang," kata Nyi Singa mengejutkan semua orang. "Dipanggil oleh sang Adipati tetapi tidak ada keterangan sampai sekarang. Oleh karenanya aku akan pergi ke Banyuwangi. Akan tanyakan langsung pada Adipati Wiraguna."
"Apakah itu tidak berbahaya, Nyi."
"Ketakutan telah membuat aku kehilangan suamiku. Kami telah mengalah. Artinya ada yang kita takutkan. Dan kita mau bekerja demi kepentingan VOC. Bukankah itu berarti ketakutan? Dan sekarang aku kehilangan suamiku. Tak ada manusia dapat hidup dari ketakutan!"
"Apa kita harus kembali angkat senjata?" Mantiri berapi-api. Sejak dulu ia memang tidak setuju, berdamai dengan Adipati Blambangan yang dianggapnya memihak VOC. Padahal mereka lari dari Malang untuk menghindarkan diri dari VOC.
"Tidak! Kita tidak mampu lagi berperang melawan mereka," Nyi Singa Manjuruh menegaskan. "Karena kita sudah terjebak oleh keenakan makan dan minum dari masa damai ini. Dan kita memburu keenakan itu. Aku perintahkan pada kalian sekarang menarik semua tenaga kerja yang kita kirimkan untuk bekerja di loji-loji dan semua tempat di mana mereka dipekerjakan dalam pembangunan ibukota Blambangan itu.
Kita tidak berkepentingan dengan selesai atau L tidaknya pembangunan ibukota. Urusan kita sekarang adalah kembalinya Singa Manjuruh dengan jalan damai."
"Baik, Nyi."
Semua meninggalkan tempat dan langsung mengerjakan perintah Nyi Singa Manjuruh, kecuali Jagabaya Mantiri. Sebab ia dan tiga orang pemuda diperintahkan mengawal Nyi Siriga Manjuruh ke rumah Mantrolot di Banyuwangi. Dan tentu saja Mantrolot segera menarik semua orang yang menjadi pengikutnya dari tempat mereka L bekerja. Ia bahkan merencanakan mengerahkan semua pengikutnya ikut mengawal Nyi Singa Manjuruh menghadap Adipati.
Juru Kunci yang menerima teguran dari Pieter Luzac karena di kandang-kadang kuda VOC tidak ada rumput, loji-loji kosong dari para pekerja, wanita ataupun lelaki. Demikian pula yang bekerja pada para pengusaha Arab, saudagar Cina dan India, serta bangsa asing lainnya, semua tidak masuk bekerja dengan tanpa keterangan. Buru-buru ia mencari Wiraguna yang sedang melihat keadaan Banyuwangi yang tiba-tiba menjadi sepi. Kuli-kuli pelabuhan tinggal sedikit. Itu pun bukan orang-orang Jawa. Bahkan kedai-kedai yang milik orang Jawa tutup. Sampai-sampai pekatik*) pun tidak masuk bekerja. Tentu akan menimbulkan kerugian besar karena kuda-kuda itu akan mati. Bahkan juru masak yang sebahagian besar juga penduduk yang datang dari Jawa itu banyak yang meninggalkan dapur mereka. Schophoff, residen Blambangan, segera memerintahkan Pieter Luzac turun ke Banyuwangi.
Persoalan kecil yang dimulai keadaan semacam ini akan berkembang menjadi pemberontakan. Karenanya Kompeni yang ada harus disiapkan.
Tetapi yang terjadi bukan pemberontakan. Ternyata hari keempat dari hilangnya Singa Manjuruh dari tengah anak buah dan istrinya, Juru Kunci dan Wiraguna dikejutkan oleh suara ramai di alun-alun. Keduanya segera berdiri. Dari pendapa itu keduanya melihat seorang wanita keluar dari kerumunan banyak orang yang sedang berhimpun di alun-alun. Kemudian wanita berjalan perlahan-lahan menuju regol kadipaten.
Beberapa waktu kemudian ia menoleh pada rombongan pengiringnya untuk tenang. Tidak mengeluarkan suara gaduh maupun kekerasan. Para pengiringnya itu, lelaki dan perempuan, semua orang yang biasa bekerja di pembabatan hutan, pembangunan loji, juru masak, kuli pelabuhan, dan masih banyak lagi. Jumlah mereka ternyata belum genap, karena masih ada yang di perjalanan. Semua di bawah pimpinan Mantrolot. pemelihara kuda atau tukang rumput untuk kandang milik para pembesar negeri dan VOC
Mereka masih berjalan keliling jalan-jalan Banyuwangi.
Apakah jalan raya utama ataupun lorong-lorong. Mereka lewat sambil bersorak-sorai. Juga mengeluarkan teriakan-teriakan yang mempertanyakan keberadaan Singa Manjuruh. Penjaga- penjaga gardu keamanan tidak bisa mencegah mereka, karena jumlah mereka begitu banyak. Bahkan ada sedikit kengerian dalam diri pengawal kota.
"Wiraguna! Kau keturunan kuda! Maka kau tak mengerti balas budi! Hiduplah Singa Manjuruh!" Demikian sayup-sayup teriak anak buah Nyi Singa Manjuruh yang berbaris di alun- alun. Wiraguna berdesir mendengar itu. Marah tapi gentar.
Berulang teriakan mereka mengguruh. Berulang Nyi Singa Manjuruh menghentikan langkahnya untuk menenangkan anak buahnya.
Teriakan kembali mengguruh kala Nyi Singa Manjuruh ditahan oleh penjaga. Bahkan mereka bergerak maju sambil bergandengan tangan satu dengan lainnya. Deretan demi deretan. Lapis demi lapis, seolah menyatu. Satu tujuan.
Sebaya mati, sebaya mukti. Melihat itu Juru Kunci segera memerintahkan penjaga membiarkan Nyi Singa Manjuruh masuk.
"Siapa ini Yang Mulia?" tanya Juru Kunci.
Wiraguna segera teringat. Ini istri si bekel Singa Juruh. Nyi Singa Manjuruh. Hamil. Perutnya besar. Langkahnya lamban karena dibebani oleh janin dalam perutnya. Kakinya berselimut debu. Pipinya merona karena terik matahari. Keringat mengalir dari tiap lubang pori di dahinya. Turun ke bawah membasahi kain penutup tubuhnya.
"Istri Singa Manjuruh!" desis Wiraguna. Ingatannya kembali pada sorot mata kala wanita itu menodongkan laras bedil padanya. Sorot yang itu pula kini menatapnya. Membuat ia takut menatap mata itu. Kini wanita itu naik ke titian pendapa. Pelan karena lelah. Tapi sorot matanya tetap tenang.
Menunjukkan ketegaran hati.
"Bicaralah pada dia, Yang Mulia," Wiraguna menyerahkan. Kendati pelan namun sampai pula di hadapan Wiraguna. Tapi perempuan itu tidak ngelesot dan menyembah. Ia tetap berdiri. Sementara itu pengiringnya merangsek maju mendekati pagar istana. Para pengawal mencegah. Mereka berhenti 9 sambil berteriak-teriak. Wiraguna tampak bingung.
"Apa maksudmu, Nyi Singa Manjuruh?" Juru Kunci segera memulai.
"Aku datang hendak menanyakan di mana suamiku berada."
"Bukan begitu kebiasaan wanita Jawa berlaku. Kau tak menyembah? Kau meniru orang Blambangan? Bahkan tidak berhamba?"
"Aku bukan orang Jawa! Aku orang Blambangan." Nyi Singa Manjuruh berbahasa Jawa dengan logat Madura. Maka tahulah Juru Kunci bahwa perempuan ini asli Madura.
"Kau tidak bisa berbahasa Blambangan."
"Setiap orang yang sadar bahwa ia makan dan minum serta hidup di bumi Blambangan ini, maka seharusnya ia mencintai dan berbakti pada negeri ini. Apa salahnya jika aku merasa jadi orang Blambangan? Bukankah sangat mengherankan jika ada orang Blambangan sendiri yang tidak mencintai negerinya?"
"Apakah ada yang demikian?
"Setiap orang Blambangan yang risi menggunakan budaya negerinya sendiri dan lebih suka pada budaya Belanda maka sebenarnya ia telah menjadi sampar bagi negerinya sendiri!" Nyi Singa Manjuruh menegaskan. Itu mengejutkan Juru Kunci dan Wiraguna. Betapa sangat beda dengan suaminya.
Perempuan ini lebih berani menyatakan pendapatnya.
"Apalagi aku mempersembahkan upeti. Mengirimkan tenaga untuk ikut bergotong-royong membantu membangun Blambangan. Karena itu kami berhak tinggal di negeri ini dengan damai. Ya, dengan damai."
"Kau ingin damai?" Juru Kunci tertawa sambil bangkit dari tempat duduknya. Wiraguna masih belum mampu menemukan dirinya. Barisan di luar pagar makin bertambah banyak. Rupanya anak buah Mantrolot sudah tiba dan bergabung. Teriakan-teriakan makin membahana.
Menyakitkan telinga. "Bagaimana mungkin, Nyi Singa Manjuruh? Kau datang bersama ribuan orang yang berteriak tanpa memperhatikan kesantunan? Bukankah itu menimbulkan keresahan?"
"Yang menimbulkan keresahan tentu bukan kami. Kawula tak pernah ingin keresahan. Tapi mereka menyatakan pendapat. Menyatakan kerinduan, kejengkelan sekaligus. Dan itulah kawula! Aku saat ini menjadi duta mereka untuk menanyakan di mana pemimpin mereka berada. Ya, suamiku! Di mana suamiku berada?"
Juru Kunci diam. Berpikir.
"Jika tak diberitahu tentulah ini merupakan penculikan..."
"Singa Manjuruh ditangkap...," Juru Kunci memotong. "Tidak! Ia dipanggil oleh Adipati. Namun tidak
diperkenankan pulang. Tanpa memberitahu keluarga yang ditinggalkan, maka itu sama dengan penculikan! Kalian tidak merasa itu? Kami yang kehilangan. Kami yang mencari!
Bukankah kewajiban kami mencari suami yang hilang? Dan mereka adalah anak buah suamiku. Tak dapat disalahkan jika mereka juga ikut mencari. Nah, jika kalian risi, berikan jawaban. Supaya kami segera menentukan sikap kami selanjutnya."
"Jadi... kau yang memerintahkan semua peka-tik, semua juru masak, semua pengangkat barang di pelabuhan, semua pembabat... ya, semua orang untuk tidak masuk kerja?" Wiraguna kini seperti tersadar dari sebuah impian. "Bukan! Tapi rasa kesetiakawanan. Jika..."
"Bagaimana jika ternyata Singa Manjuruh dihukum mati?" "Apa salahnya?" Nyi Singa agak berdesir.
"Menghina Adipati!" Juru Kunci menyahut lagi.
"Baik! Kebenaran memang selalu ada di tangan orang yang berkuasa. Kawula memang tidak kuasa memiliki kebenaran itu. Baik, semua orang akan meninggalkan Blambangan.
Karena ternyata Blambangan tidak dapat memberikan kedamaian pada kawulanya. Jangankan kami. Pribumi pun kalian aniaya! Bunuhlah dia, karena pada dasarnya kalian memang pembunuh." Nyi Singa, Manjuruh membalikkan tubuh, membelakangi mereka untuk kemudian melangkah.
Serta-merta teriakan makin keras. Bahkan lebih menggetarkan hati.
"Sundel Bolong! Bunuh dia! Wiraguna kunyuk!!!" '
Hati Wiraguna mendadak kecil. Wajahnya pucat. Ancaman bunuh baginya akan bisa terjadi kapan saja jika kebencian orang-orang itu tak teratasi.
"Awas kau! Setan alas! Dasar anak kuda! Ha... ha... hah..." Kasar dan merupakan penghinaan yang lebih tidak santun.
Ia dikatakan sebagai anak kuda. Rasanya Wiraguna tak
pernah menerima yang sekasar itu. Dengan kata lain mereka mengejek bahwa ibunya berzinah dengan kuda. Keterlaluan itu. Dalam kekalutan ia panggil kembali Nyi Singa Manjuruh yang hampir menuruni titian pendapa. Wanita itu berhenti.
Menoleh dengan mata sayu, Hampir boleh dikatakan tatapan kosong.
"Apalagi yang akan kudengar? Ketahuilah! Bukan suamiku menghina kau! Tapi justru ia tidak ingin mengatakan apa yang didengarnya dari Mas Ayu Tunjung tentang dirimu. Ia bermaksud supaya kau sendiri mendengar penampikan Ayu Tunjung padamu. Ia sangat menghormatimu. Aku memang tidak! Sebab hilanglah sudah rasa hormatku pada tiap perampas kebebasan, kebahagiaan, bahkan hak orang lain. Ternyata kekuasaan yang kausandang saat ini tak kaugunakan untuk membangun kesejahteraan kawulamu. Tapi sekadar untuk dirimu sendiri dan Kompeni serta VOC atau kekuatan modal lainnya."
"Cukup!" Wiraguna tak sanggup mendengar lagi. Ingin rasanya menyumpal mulut perempuan hamil itu. Tapi ia tak berani. Di belakang perempuan itu berbaris ribuan orang, lelaki dan perempuan. Baik pekerja maupun sundal. Kuli maupun rampok.
"Singa Manjuruh tak akan dijatuhi hukuman mati," tegasnya. "Tapi katakan pada mereka, supaya berhenti mengucapkan kata-kata yang kotor seperti itu. Dan kedua..."
"Mereka tidak bicara kotor! Mereka menumpahkan perasaan," jawab Nyi Singa Manjuruh.
"Ternyata kau tak pernah memahami perasaan seseorang." "Alangkah indahnya, Yang Mulia. Bagaimana jika
pertanyaan itu berpulang padamu sendiri? Mengertikah kau
perasaan seorang wanita hamil tua yang suaminya sedang diculik? Juga kawula kehilangan tanahnya? Kehilangan anaknya yang dijual oleh pengusaha negeri sebagai budak? Wajarlah jika mereka menumpah-ruahkan semua kejenuhannya dengan kata-kata itu. Cuma kata-kata. Tapi mereka dirampok, dipaksa dengan kekuatan serta todongan bedil. Sebenarnyalah belum cukup adil atas semua kebijakan yang pernah kaukerjakan untuk memperkaya dirimu sendiri itu."
Kembali Wiraguna terhenyak. Wanita dengan kaki berdebu, peluh selalu membasahi kainnya yang setengah kumal itu mampu mengembalikan pertanyaannya. Bibirnya bergetar tanpa kata-kata. "Apa lagi yang harus kudengar? Tapi ingat-ingat!
Keputusanmu hari ini, akan menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan Banyuwangi! Lihat! Semua mereka berang karena penculikan ini!" Nyi Singa Manjuruh menuding para pengiringnya. Dan mereka menjawab dengan sorakan seperti suara bata yang roboh.
Sambil menarik napas panjang Juru Kunci kemudian memberikan keputusan karena Wiraguna tidak mampu lagi berkata-kata.
"Singa Manjuruh akan dibebaskan. Pasti! Tapi kau harus mampu menghadapkan Sri Tanjung dari Songgon. Dan memaksa suami wanita itu menyerah."
"Sungguh suatu lelucon. Jika kekuatan senjata tidak mampu memaksa mereka maka sekarang seorang wanita yang sedang hamil, dipaksa mengambil dua orang perkasa itu. Habiskah pahlawan VOC dan begundalnya?"
"Karena kau telah mampu memaksa kami. Dengan kata lain, kau dianggap bukan orang lemah. Dan karena itu, jika kau gagal maka leher suamimu akan terempas ke bumi."
Sesaat mata istri Singa Manjuruh tersentak. Matanya memancarkan kemarahan. Tapi ia segera A membalikkan tubuh. Ia mengerti bahwa Juru Kunci tidak main-main.
Sekalipun mereka pergi VOC akan tetap meminta para adipati untuk mengirimkan orang-orang yang dianggap sampah di negerinya ke Blambangan.
"Lebih cepat kau mengirim mereka lebih baik. -Sebab jika putus sabar kami karena pembangkangan kalian ini, maka habis juga nyawa suamimu!" Juru Kunci masih sempat mengeluarkan ancaman. Dan pengiring Nyi Singa Manjuruh makin marah mendengarnya. Namun wanita m muda itu memberi isyarat agar mereka tenang. Dan mengajak mereka bubar. "Kita sudah cukup menyatakan pendapat kita. Ini sudah sangat baik. Daripada sama sekali tidak! Kita bubar dulu. Setelah di rumah nanti kita akan berunding. Mereka akan membebaskan Kakang Singa Manjuruh dengan syarat."
Mantrolot tidak terima. Tapi demi Singa Manjuruh sahabatnya itu maka ia mengalah. Pelan-pelan mereka meninggalkan alun-alun. Omelan dan cetusan kekecewaan lewat makian terdengar ^ lagi seirama dengan langkah mereka yang pelan-pelan meninggalkan tempat mereka berhimpun. Wiraguna tak dapat menenangkan debar jantungnya sendiri. Bayangan mata-mata nyalang seolah mengincarnya terus sambil memaki: ibunya berzina dengan kuda! Ha... ha... ha... dilogoknjar-rf«!!.*) Bergidik ia tanpa sesadarnya. Seperti melihat hantu. Ribuan hantu yang kasar dan kotor. Keringat dingin keluar di dahinya? Dan lebih celaka lagi kala ia sedang sendirian, ribuan mata itu berulang muncul. Umpatan busuk itu juga berkali terngiang-ngiang di telinganya. Keser pian menimbulkan ketakutan yang tak teratasi. Terutama malam hari ini. Kejadian siang tadi tak mau pergi dari ingatannya.
Bayangan ribuan orang berselang-seling dengan bayangan Ayu Tunjung mengganggunya. Ah, Sri Tanjung? Mengapa kemudian ia menjelma jadi ribuan mata pengumpat? Makin mendekat, beramai-ramai ribuan tangan hendak mencekiknya. Rasanya ia berlari. Di padang rumput. Luas sekali. Tidak ada orang. Ia menoleh kiri-kanan. Tiada seorang pun. Tiba-tiba saja Sri Tanjung muncul.
Tersenyum. Menggoda dengan lambaian tangan agar Wiraguna mendekat. Wanita itu kini menjauh. Ia kejar. Makin jauh. Gumpalan awan mendadak turun. Pelan-pelan menutup tubuh Sri Tanjung. Tidak!!! ia berteriak. Dan tiba-tiba muncul pelangi di celah awan dan sinar mentari yang remang-remang. Tampak olehnya Sri Tanjung meniti pelangi itu. Pelan-pelan.
Naik ke atas. Ke atas sambil tersenyum. Ia kejar. Napasnya terengah-engah. Sri Tanjung!!! Jangan tinggalkan aku, Istriku!!! Tapi wanita itu naik terus. Terus.
Wiraguna menerobos awan gelap dan mencoba meniti pelangi. Tapi entah bagaimana mulainya," pelangi itu lenyap. Dan di depannya muncul ribuan orang lelaki dan perempuan. Semua memandangnya dengan wajah kalap. Mereka mengacung-acungkan tinju. Ia berhenti melangkah. Berbalik. Tapi kini ia juga berhadapan dengan keadaan yang sama. Ia terkepung. Ketakutan datang lagi. Ai, kini mereka mendekat. Wiraguna berteriak-teriak minta ampun. Ia pejamkan mata. Terserah akan diapakan. Sambil berteriak-teriak ampun, ia tutup mukanya.
Sebuah tangan menyentuhnya. Ia berteriak makin keras. "Ampun, Yang Mulia. Ada apa?" Suara merdu menyapanya. "Jangan bunuh! Jangan! Ampun!" Napas Wiraguna
terengah-engah. Bahkan badannya gemetar.
"Tidak, Yang Mulia. Mimpi apa? Kenapa tidur di kursi?" Kembali suara itu menanya. Dan Wiraguna menggeragap. Ia membuka matanya. Ternyata ia masih di pendapa. Ah, mimpi rupanya.
"Oh, kau, Su Lie Hwa?".
"Hamba, Yang Mulia," wanita itu menyembah. "Astaghfirullaahal'azhiim!" Wiraguna menyebut. "Laa ilaaha
illallaahu Muhammadur Rasuulullah..." Kemudian Wiraguna mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Seolah mengusap noda di wajah itu. Setelah menarik napas panjang ia bangkit.
"Mari, Lie, temani aku malam ini. Aku tak ingin sendiri." "Yang Mulia terlalu lelah " Wanita itu membimbingnya.
Perlahan mereka masuk bilik. Perlahan. Seolah meniti duri. Kegelapan makin mencekam. Dan Lie Hwa menutup rapat- rapat pintu bilik peraduan Wiraguna. Setelah semua jendela juga sudah tertutup rapat, barulah keduanya membaringkan diri.
***
Empat hari empat malam Nyi Singa Manjuruh dengan ditemani Mantrolot serta lima orang pengawalnya berjalan. Melintas belantara, menuruni jurang dan mendaki bukit, serta menerjang semak dan onak. Menapaki jalan mendaki kini.
Sudah memasuki Hutan Songgon. Kelelahan hampir tak tertahankan. Janin yang di perutnya sering kali menendang- nendang. Ingin segera keluar meringankan beban ibunya.
Berkali rombongan itu berhenti. Minum dari tabung bumbung yang mereka bawa sejak dari rumah mereka. Peluh dan debu menyatu di kulit mereka. Bahkan rasa pegal linu dan kelelahan hampir membuat Nyi Singa Manjuruh putus harapan. Apakah ia mampu sampai di hadapan Ayu Tunjung? Jika tidak tentu suaminya tercinta itu akan dipancung. Lebih baik aku sendiri mati daripada suamiku. Maka aku harus sampai di hadapan Mas Ayu Tunjung.
Tapi apakah aku bisa mendapat kasihnya? Sehingga ia merelakan suaminya diserahkan pada penguasa? Ia sendiri tak rela Singa Manjuruh dipancung. Haruskah aku kehilangan cintaku? Cinta telah membuat Nyi Singa Manjuruh menempuh perjalanan jauh. Berkali ia pegangi perutnya. Rasa sakit dan rasa-rasa lain menyatu tak menentu. Kadang sakit itu hilang. Mantrolot ikut panik. Bagaimana jika bayi ini lahir di perjalanan. Di hutan tanpa dukun bayi? Ah, jangan-jangan aku jadi dukun bayi? Mantrolot bergidik. Demikian pula pengawal lainnya.
Makin dekat dengan perbatasan Songgon, makin semangat mereka melangkah. Namun makin sering pula Nyi Singa Manjuruh berhenti. Terik mentari memberikan aniaya tersendiri. Kepalanya sering pening dan pandangan matanya menjadi gelap dengan tiba-tiba. Ah, apakah tiap perempuan hamil mengalami seperti aku? Ya, Tuhan beri aku kekuatan, ia menyebut dalam hati. Tentu para pengawalnya itu tak tahu apa yang ia rasakan. Ia malu menceritakan pada mereka.
Apalagi pada Mantrolot. Sebab orang itu sering-sering bicara kotor. Rupanya pergaulan telah membiasakan orang itu bicara seenak perutnya. Diam-diam ia kembali mengumpulkan tenaga untuk berangkat. Tinggal selangkah lagi, katanya pada diri sendiri. Ah, cinta telah melahirkan kesetiaan. Dan kesetiaan itu tetap digenggam oleh Nyi Singa Manjuruh.
Hingga ia rela mengerjakan semua ini, karena ia terikat oleh kesetiaan itu. Kesetiaan bagi perempuan Madura harus dibawa mati. Penyelewengan berarti hukuman mati. Kesetiaan itu pula menyulut semangatnya untuk bertahan dan berjalan. Kepada janin dalam perut ia berkata, jangan lahir di sini, Nak. Ini masih di tengah hutan. Nanti, di depan Ayu Tunjung
Orang-orang Songgon tidak mencegah. Bahkan mereka segera memberi pertolongan waktu melihat rombongan yang memapah wanita hamil itu. Barangkali saja sudah tiba waktunya melahirkan., Namun Nyi Singa Manjuruh menolak untuk berhenti di sebuah rumah di ujung desa. Ia harus menghadap Ayu Tunjung sekarang juga. Maka kawula Songgon segera menyiapkan pedati kecil dengan dua ekor kerbau penariknya.
"Tidak perlu "
"Tidak apa-apa, Nyi. Keharusan kami menolong tiap orang yang membutuhkan," kata mereka ramai-ramai. Laki- perempuan.
Mantrolot melihat itu dengan terharu. Demikian pula Nyi Singa Manjuruh. Betapa jauh bedanya dengan berita yang didengarnya di luar Songgon. Di luar tertiup berita bahwa pribumi Blambangan adalah orang-orang jahat. Pembunuh dengan tenung atau teluh. Juga pandai memikat hati wanita atau lelaki dengan menggunakan ilmu pelet. Semua tak terlihat di sini. Semua baik dan ramah. Melihat kenyataan itu, air mata Nyi Singa Manjuruh runtuh kala itu sudah duduk dalam pedati, berlampin jerami. Pengawalnya berjalan cepat di samping kiri-kanan pedati bersama beberapa orang Songgon yang ramai menanyakan dari mana asal mereka dan berbagai pertanyaan lagi. Menyodorkan minuman air gula kelapa dan kinang, merupakan selingan dalam perjalanan ke pertapaan.
Pohon kelapa yang begitu banyak berjajar di kebun-kebun, diselingi pisang atau tanaman palawija lainnya, menunjukkan kesuburan tanah Songgon ini. Bekas panen sudah mulai dibersihkan karena mereka mulai membajak sawah kembali. Persemaian tampak menghijau di sudut-sudut petak sawah.
Anak-anak kecil berlarian pulang sambil membawa rentengan belut di tangan kanan mereka, menggambarkan betapa damainya desa terpencil ini. Dalam kalbu Nyi Singa Manjuruh iri, mengapa ini bisa terjadi di sini? Tidak di desanya Singa Juruh? Apakah di sini tak terusik pajak? Bukankah saat ini tak seorang pun bisa menghindarkan diri dari upeti? Barangkali zaman Wong Agung Wilis kawula Blambangan dapat diam dengan tenteram tanpa terusik membayar upeti. Tapi sekarang? Zaman Wiraguna ini? Kiranya tak ada lagi tempat damai. Pembayaran upeti telah mengusik siapa saja yang diam di bumi Semenanjung Blambangan. Apakah ia petani, penjual makanan, pemilik kedai atau warung-warung. Bahkan anak-anak kecil pun dijatah untuk membayar upeti. Jangankan manusia. Hewan pun harus membayar upeti. Pemilikan kerbau, sapi, kambing, itik dan ayam sekalipun mengharuskan orang siap bayar upeti. Tapi tampaknya Songgon adalah desa perkecualian.
Jalan yang bersih dan rata menunjukkan betapa rajinnya orang Songgon merawat sarana yang mereka gunakan bagi lancarnya pengangkutan hasil panen di sawah ke lumbung- lumbung, Rupanya orang Songgon tidak membiarkan ternak a melewati jalan ini setiap kali akan berangkat ke sawah. Ada jalan tersendiri bagi mereka. Bahkan rombongan itik pun tak diperbolehkan lewat di sini. Namun pengamatannya pada alam seputarnya itu cuma sekilas. Sebab Nyi Singa Manjuruh segera teringat kembali pada suaminya yang sedang berhadapan dengan algojo yang haus darah. Kembali ia menutup wajahnya. Jangan! teriaknya dalam hati. Jangan bunuh dia!
Dan algojo terbahak-bahak. Ia tersentak oleh derak gerobak. Ah, pedati itu berhenti. Beberapa orang perempuan buru-buru keluar gerbang, dan menolongnya turun dari pedati.
Hati Nyi Singa Manjuruh terkejut luar biasa. Tentu Mas Ayu Tunjung sudah tahu bahwa ada seorang datang menghadapnya. Lebih dari itu tentu sudah mendengar bahwa yang datang seorang perempuan hamil. Luar biasa, dari mana mereka tahu? Benarkah Rsi Ropo seorang yang mampu melihat sesuatu yang belum terjadi atau yang akan terjadi?
Perlahan sekali ia melangkah. Rasa sakit hampir tiada tertahankan. Kembali si janin mendepak-depak. Memaksanya berhenti sejenak sambil memegangi perutnya. ,
"Hyang Dewa Ratu... Jagat Pramudita!" Ayu Tunjung segera turun dari titian pendapa. Nyi Singa Manjuruh mendongak mendengar suara itu. Merdu. Dan betapa terkejut demi ia memandang wajah yang gilang-gemilang itu. Lebih mulia dari waktu perawan dulu. Atau barangkali karena perhiasan yang dikenakannya, atau karena kainnya yang sutera kuning itu. Atau kutang emas dengan gambar bunga mawar sebagai penutup putik susunya itu? Sungguh tidak mengherankan jika iman lelaki mana pun akan runtuh berhadapan dengannya. Kakinya yang mulus itu kini menginjak hamparan kerikil untuk mendekati Nyi Singa Manjuruh. Matanya. Aduh, betapa agungnya wanita ini.
Apakah ia juga tahu maksud kedatanganku? Debar jantung Nyi Singa mengencang. Ayu Tunjung tersenyum tulus.
"Selamat, selamat datang, Kawan. Apa kabar?
Dirgahayu...," kembali suara merdu penuh kasih itu menyentuh hatinya. "Tentu ada yang amat penting maka seorang hamil tua begini tertatih-tatih naik ke Songgon. Mari, barangkali ada yang dapat aku bantu."
Ah, wanita ini barangkali tak sadar bahwa aku datang untuk merusak kebahagiaannya? Aku tak bisa! Ia tidak sanggup berkata-kata. Matanya sembab memandang Ayu Tunjung yang begitu ramah. Memang wanita itu berkata dalam Blambangan. Tapi ia mengerti semua makna kata-kata Ayu Tunjung. Tidak ada tersirat kecurigaan yang memancar. Semua orang, baik pengawalnya maupun pengawal Ayu Tunjung, memandangnya. Kepalanya kian pening. Ayu Tunjung kian mendekat. Dan ketika ia hendak melangkah, kekuatannya punah. Maka ia terhuyung ke depan. Untung Ayu Tunjung segera melompat menangkapnya. Demikian pula orang lain. Namun ia tidak pingsan. Ia masih sadar. Dan kemudian Nyi Singa Manjuruh merangkul sambil mencium kaki Ayu Tunjung. Bahkan sedu-sedannya meledak. Tak ayal lagi kaki Mas Ayu Tunjung tercuci oleh air mata Nyi Singa Manjuruh.
Inilah pengalaman pertama bagi Mas Ayu Tunjung. Hatinya menjadi berdesir. Teringat pada berita yang baru saja disampaikan oleh suaminya semalam. Singa Manjuruh akan dibunuh jika Ayu Tunjung dan Rsi Ropo tidak menyerahkan diri ke Banyuwangi. Semalam suaminya dalam pergumulan.
Membuat ia juga tidak bisa tidur. Keduanya tahu demi Singa Manjuruh, nyawa mereka harus diserahkan. Kini suaminya sedang menjumpai Harya Lindu Segara di Bandar Banyuwangi. Tentu orang itu sedang memperun-dingkan cara yang terbaik untuk menolong Singa Manjuruh. Sejak pagi orang itu berangkat. Melintas rimba dengan kuda hitam yang perkasa.
"Berdirilah, Nyi Singa Manjuruh. Tak pantas wanita yang pernah mengangkat senjata melawan VOC menangis semacam ini." Ayu Tunjung meraba punggung wanita hamil itu. Kemudian memberi isyarat pada Parti, pengawalnya, untuk mengangkat wanita itu masuk pendapa. Namun Nyi Singa Manjuruh memeluk kaki Ayu Tunjung makin erat. Tak mau dipisahkan lagi. Rasa bersalah dan berdosa tak tertanggungkan, sekalipun ia belum menyatakan permohonannya.
"Ampunkan hamba, Yang Mulia," rintihnya dalam Blambangan yang berlogat Madura. "Ampuni hamba "
Kini semua pengawal Nyi Singa Manjuruh memandang Ayu Tunjung. Mereka ingin tahu jawaban yang keluar dari bibir itu.
"Sudah kukatakan. Berdirilah. Katakan dengan tenang. Apa yang harus kukerjakan untuk membantumu?" Ayu Tunjung tegar.
"Cuma Yang Mulia bisa menolong hamba "
"Luar biasa kau. Barangkali belum pernah aku melihat kisah cinta yang seperti kaumiliki ini, Nyi. Kesetiaanmu telah melahirkan pembelaan atas nyawa suamimu. Sungguh, siapa yang tak menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, tak akan pernah percaya, seorang wanita hamil tua, tertatih-tatih membela cintanya. Cinta telah membuatmu enggan tinggal di puri bangkalan. Mengagumkan." Mas Ayu tersenyum.
Kemudian menatap tempat yang kosong. Senyum Rsi Ropo suaminya seolah tampak di kejauhan. Tapi sedan Nyi Singa Manjuruh telah menyentakkannya.
"Kuatkanlah hatimu! Janganlah patah semangatmu, Nyi Singa Manjuruh. Janganlah khawatir. Sebab akan ada upah untuk usahamu ini."
"Yang Mulia " Pelan-pelan Nyi Singa Manjuruh
mendongak. Air matanya masih mengalir deras. Seperti dua sungai kembar menelusuri sebuah bukit di tengahnya.
"Benarkah yang hamba dengar ini? Atau karena Yang Mulia " Ia tak berani melanjutkan. Menangis makin keras.
Meraung. "Aku akan membicarakan kepulangan suamimu! Jangan sedih," Ayu Tunjung menegaskan. "Mari, naiklah ke pendapa!"
Ayu Tunjung kemudian dibantu <5leh para pengawalnya memapah Nyi Singa Manjuruh naik ke. pendapa. Rasa haru menyesaki dadanya. Kaki berselimut debu itu dicucinya dengan air kendi yang memang tersedia di depan titian pendapa. Setelahnya dengan sangat susah mereka naik.
Rupanya itu tenaga penghabisan bagi Nyi Singa Manjuruh.
Dan betul. Begitu masuk pendapa ia terjatuh lagi. Bukan cuma karena tenaganya yang habis. Tapi ia tak tahan melihat wanita yang tergolong pasangan baru ini direnggut kebahagiaannya demi kepentingan pribadinya. Betapa kejam diriku ini. Kini Ayu memerintahkan orang untuk membaringkan Nyi Singa Manjuruh di amben yang biasa dipakainya duduk bersama suaminya. Setelahnya ia membasuh wajah Nyi Singa yang berdebu itu dengan air.
"Panggil dukun bayi, Mbok Mukti, kernari," katanya pada pengawalnya. Dan tanpa banyak cakap perempuan muda itu berangkat.
"Belum tentu melahirkan sekarang. Tapi lebih baik jika di tangan seorang dukun daripada di tanganku yang belum pernah melahirkan seorang pun anak." Ia tersenyum pada Mantrolot. Juga pada seluruh pengawal Nyi Singa Manjuruh. Mantrolot tertunduk oleh sorot matanya. Hati semua orang itu jadi berdebar. Nyatalah bahwa perempuan ini bukan cuma seorang cantik. Namun juga berpengetahuan tinggi.
Mendengar nada bicaranya pasti ia sudah tahu tujuan kedatangan mereka. Dari mana wanita ini bisa tahu? Padahal ia dan suaminya tentu tidak banyak keluar rumah. Bukankah mereka lebih banyak menggunakan waktu di dalam pura?
Berdoa dan membaca lontar saja?
"Memang bukan pekerjaanku menolong seorang yang melahirkan. Karena memang aku bukan dukun bayi." Ayu Tunjung tersenyum lagi. Seolah tak habis-habisnya senyum itu. Senyum yang menyejukkan hati semua orang. Mantrolot bersama teman-temannya tetap membisu. Tak tahu apa yang harus dikatakan. Kemudian Ayu Tunjung mendekati Nyi Singa Manjuruh yang terlentang di amben itu dan mengelus perutnya.
"Akan lahir di sini dengan damai, Anak manis. Bapakmu akan menjemputmu di tempat ini setelah aku dan suamiku diserahkan."
"Yang mulia..." Nyi Singa terisak lagi. Hatinya benar-benar lumat.
"Kalian adalah sahabat Mas Dalem Puger yang dicintai oleh kawula Blambangan. Sama seperti Wong Agung Wilis. Maka kalian juga sahabat kami "
"Yang Mulia, doakan kami, ampunkan kami " Nyi Singa
Manjuruh terbata-bata di antara sedu-sedan. Ayu Tunjung mengelus rambutnya dengan kasih. Ia sendiri ingin meneteskan air mata. Tapi ia tahan sekuat tenaga. Meski ia tahu air mata adalah senjata bagi wanita untuk melepas kesesakan yang menghimpit dada. Tapi ia tidak akan melakukan itu. Ia sadar bahwa ia adalah satria Blambangan. Ia bukan wanita semata wayang. Maka katanya,
"Kau memerlukan suamimu. Kebebasan suamimu! Dan tak akan ada kebebasan itu turun cuma karena doa. Kebebasan perlu diperjuangkan. Dan tiap perjuangan membutuhkan pengorbanan. Dan aku adalah manusia yang dikehendaki untuk dikorbankan "
"Ja "
"Tenanglah, Nyi Singa! Sahabat yang baik adalah sahabat di dalam suka dan duka. Dan sahabat sejati adalah seorang yang rela menyerahkan nyawa bagi sahabatnya itu."
Tak tertahan lagi suara tangis Nyi Singa Manjuruh. Makin meraung-raung. Tidak hanya itu. Mantrolot dan para sahabatnya pun ikut menangis. Belum pernah mereka menjumpai orang yang semacam ini. Apakah itu cuma kata- kata? Atau barangkali saja Ayu Tunjung sengaja mau menyerahkan diri pada Mas Ngalit karena ingin kehidupan yang lebih baik? Kaya dan enak? Di istana? Tak dikejar oleh nyamuk karena tidak tahan lagi di tengah hutan? Ia belum dapat dipercaya. Tapi paling tidak kata-katanya amat merogoh hati semua yang mendengarnya saat ini.
Beberapa bentar kemudian Mbok Mukti, si dukun bayi, datang dan menyembah. Pada seorang pengawal ia memerintahkan agar disediakan kamar. Kemudian pada seorang lagi diperintahkan mempersiapkan tempat istirahat bagi Mantrolot dan sahabatnya. Lalu seorang lagi diperintahkan memukul kentongan sebagai isyarat agar para cantrik atau siswa terkemuka berkumpul di balai pracabaan.
Namun sebelum mereka bubar, Rsi Ropo bersama Lindu Segara memasuki pendapa. Ayu Tunjung tergopoh-gopoh berlari menjemput suaminya. Mencuci kaki lelaki itu dengan air bunga di titian pendapa lalu menciumnya. Setelah itu keduanya bergandengan menuju ke tengah pendapa. Semua orang melihatnya jadi iri. Sepasang muda-mudi dalam pakaian kebrahmanaan. Seperti sepasang dewa-dewi yang turun dari kahyangan.
Semua menyembah. Mantrolot dan teman-temannya juga terkena wibawa keduanya dan ikut menyembah.
"Dirgahayu semuanya!" sapa Rsi Ropo.
"Dirgahayu!" jawab semua orang. Nyi Singa Manjuruh berusaha bangkit. Tapi dicegah oleh Ayu Tunjung.
"Kami sudah berkeputusan untuk menolong suamimu," Rsi Ropo menjelaskan. Setelah itu ia memandang sekelilingnya.
"Adinda... sudahkah kau siap?" "Kanda..." Ayu Tunjung memeluk suaminya. Direbahkannya kepalanya ke atas dada suaminya. Mengundang keharuan semua orang. "Tiada seorang pun suka keberakhiran "
"Ha... ha... ha..." Suara tawa Rsi memotong kata-kata istrinya. Ia tak ingin mendengar kelemahan semacam itu. "Seorang bijak tentu telah menimbang semua langkahnya. Mati pun dipertimbangkan. Bukankah kita telah memilih kemati-an yang paling mulia? Nah, Mantrolot, kau akan menyertai Lindu Segara menyerahkan lontar pada Wiraguna. Katakan aku dan istriku akan berangkat ke Banyuwangi, jika Singa Manjuruh sudah dikirim ke Songgon. Sebab aku tak mau kita ditipu. Kami rela berkorban. Tapi bukan untuk ditipu."
"Yang Tersuci...," Mantrolot kaget.
"Tak apa. Berangkatlah. Kuda telah disiapkan untukmu. Tapi jangan kembali tanpa Singa Manjuruh. Sebab mereka adalah drubiksa keji. Penipu dan pembinasa. Dan tidak pernah mendengar jerit tangis kawulanya."
Kemudian kedua orang brahmana itu masuk. Semua tetap menanti. Tanpa bisik. Cuma angin yang bebas berdesir.
Semua bersila tanpa gerak. Tertunduk tanpa melirik. Debar jantung mereka yang seperti berpacu. Sejenak. Dua jenak. Sampai ratusan... Ya, ratusan jenak. Mereka tetap menanti. Tanpa tahu apa yang sedang dikerjakan Rsi dan istrinya di balik dinding batu itu. Burung gagak memamerkan suaranya di halaman. Mengalahkan suara burung-burung lainnya.
Kala suara langkah kaki Rsi terdengar, semua makin tertunduk. Perlahan langkah itu. Tapi mantap.
"Mantrolot. Ini lontar yang kami tulis sendiri untuk Wiraguna. Katakan aku akan menunggu di sini. Jika mereka akan menjemput kami, jangan boleh masuk ke desa Songgon. Tapi dipersilakan menunggu di luar tapal batas desa. Jika ini dilanggar, maka semua janji yang aku tulis dalam lontar itu aku nyatakan batal. Dan kau bertugas memeriksa pesanggrahan Sri Tanjung. Itu harus kaukerjakan bersama Lindu Segara. Ingat-ingat. Jangan mau ditipu. Perlu sekali pemeriksaan tempat Sri Tanjung itu. Jika dia menolak, katakan Sri Tanjung tidak akan berangkat ke Banyuwangi."
"Hamba, Yang Tersuci," Mantrolot menirukan orang Blambangan menyebut sang Rsi.
"Jangan lupakan. Bukan kau yang seharusnya memeriksa pasanggrahan itu, tapi Lindu Segara. Kau tak perlu tahu apa maksudnya. Setelah itu kau boleh berpisah dengan Lindu Segara. Ingat! Kau harus menyertai Singa Manjuruh kemari."
"Yang Tersuci..." Nyi Singa Manjuruh tak dapat melanjutkan kata-katanya. Tertahan oleh rasa haru.
"Pikirkanlah kebebasan suamimu. Jangan pikirkan kami!"
Selesai memberikan perintah Rsi masuk lagi. Dan semua melaksanakan apa yang diperintahkannya. Lindu Segara mengawal orang yang Belum pernah dikenalnya secara dekat. Tapi Mantrplot nampaknya segan melihat otot-otot kekar di hampir seluruh tubuh Lindu Segara. Dalam hati bertanya siapa orang ini. Kumis tebal serasi dengan alisnya yang teduh membuat matanya seolah bercahaya. Pendiam orang ini, pikir Mantrolot. Karena memang Lindu Segara bicara cuma seperlunya saja. Pikirannya sedang sibuk mengatur siasat selanjutnya. Kendati ia sudah memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi semua bajak laut yang tunduk padanya untuk bergerak ke Banyuwangi.