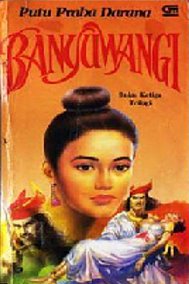Bab 4 : Pagar Betis
Kedatangan Sratdadi alias Rsi Ropo memberikan angin baru bagi seluruh orang Songgon. Mereka begitu kagum dan menganggap bahwa Rsi Ropo memiliki seribu nyawa yang tak mungkin dapat mati. Maka kehidupan di Songgon dengan amat tiba-tiba menjelma menjadi lebih semarak dari semula.
Semangat mereka yang hampir padam, kembali membara. Sebab dengan hadirnya Rsi Ropo, kawula berharap bahwa Wong Agung Wilis akan kembali hadir di tengah mereka.
Penjagaan di malam hari juga mulai diadakan. Karena Ropo mulai mengajar bahwa mereka perlu menjaga hak mereka.
Songgon, kata Ropo, adalah tanah suci, yang harus tidak terjamah oleh tangan si bule. Maka penjagaan sandi kembali dilakukan seperti dulu kala sebelum perang.
Bunga-bunga kembali ditanam orang. Kenanga, kantil, mawar dan melati, kembali bermunculan. Seolah mereka ikut berbahagia menyambut hadirnya sang Rsi. Apalagi terdengar berita bahwa satu minggu lagi Rsi akan melangsungkan upacara pernikahan. Semua orang bersukacita. Songgon yang kecil segera menjelma jadi bintang di tengah hutan belantara. Anak-anak gadis dan orang-orang tua yang dulu berharap bahwa anak-anak mereka akan diperistri sang Rsi, tidak perlu menjadi kecewa. Sebab tidak mungkin mereka membandingi wanita itu. Bukan cuma manis tanpa tandingan, tapi juga memiliki pengetahuan yang tinggi. Semua orang menilai bahwa keduanya adalah pasangan yang serasi.
Kuntum bunga telah mekar di sana-sini. Seolah ikut mempersiapkan diri bagi upacara pernikahan kedua orang itu. Demikian pula halnya desa Songgon. Semua jalan-jalan dibersihkan. Tidak sehelai rumput pun boleh tumbuh di jalan- jalan. Tak ada yang memerintah. Tapi tiap orang membersihkan jalan-jalan yang melintas di depan rumahnya. Mereka kerjakan dengan kesadaran mereka sendiri. Mas Ayu Tunjung terharu melihat itu. Mas Ayu Tunjung jadi tidak bebas keluar rumah. Ia selalu dikerumuni wanita-wanita tua, yang sudah berpengalaman. Tiap pagi dan sore ia dilulur dengan mangir. Tanpa ada yang meminta mereka bertandang ke dalam puri pertapaan itu. Mas Ayu jadi rikuh. Apalagi pagi dan sore mereka juga yang memandikannya dengan air bunga setelah dilulur. (diborehi, diolesi dengan mangir) Geli rasanya.
Ia memang belum pernah mendapat perlakuan seperti itu.
Rasanya semua orang mengasihinya. Hatinya menjadi berbunga-bunga. Betapa tidak?.
Wanita-wanita yang sudah peot itu, ternyata mempunyai banyak cerita. Sambil melulur tubuh-nya, mereka memijit dan bercerita. Macam-macam cerita mereka itu. Ada dongeng "Timun Mas dengan Raksasa Hijau", ada dongeng mengenai "Kelana Gandrung", "Panji Asmara Bangun" dan macam- macam lagi. Rasanya ia kembali meriup jadi bayi. Semua orang memperhatikan. Semua menumpahkan kasih sayang.
Harya Lindu Segara pun ikut sibuk. Ia mengirim berita ke Mengwi, melalui para nelayan. Maka Wong Agung Wilis segera menulis surat pada anaknya itu. Dikirimkannya lewat caraka sandi (utusan rahasia) yang menjadi kepercayaannya.
Demikian pula, secara diam-diam ia mengirimkan hadiah berupa emas dan pakaian, baik untuk menantunya maupun untuk anaknya sendiri. Mas Ayu Tunjung menerima kiriman itu dengan air mata yang berlinang. Bertiga mereka membaca surat Agung Wilis.
"Sratdadi, Anakku
Dirgahayu! Jayalah kau, jayalah negerimu! Sungguh gembira hati ini, kau akan menikahi anak kakakku sendiri, Prabu Mangkuningrat anumerta Setidaknya kau telah menyambung kembali pertalian darah yang hampir putus karena perbedaan pandangan dan kepentingan. Aku dapat membayangkan betapa Tunjung telah tumbuh menjadi seorang gadis manis dan cerdas. Mungkin saja lebih dari ibunya. Aku berharap kalian bisa hidup serasi. Terlebih dalam menanggungkan tugas berat di masa kini dan mendatang.
Lebih dari itu tugas mulia.
Sewajarnyalah jika aku memberikan sesuatu pada menantuku. Tentu ini tidak sepadan dengan milik paramesywari Blambangan. Tapi barangkali saat ini, itulah yang terbaik, yang dapat aku berikan buat menantuku.
Maafkan aku, karena aku bukan bandit yang mampu- menggunakan uang orang lain demi kepentingan sendiri."
....
Sampai di sini Mas Ayu berhenti sebentar. Air matanya berlinang. Bahagia bersatu dengan haru. Buru-buru ia menghapusnya karena malu. Seorang yang telah menua itu masih memperhatikannya. Masih ingin menyumbangkan sesuatu demi kebahagiaan anaknya. Atau memang itulah naluri seorang bapa? Ingin melihat anaknya bahagia? Ah, tidak semua! Bukankah Amangku-rat dari Mataram pernah bertengkar dengan anaknya demi memperebutkan wanita?
Sama-sama orang tua. Sama-sama lelaki. Tapi berbeda jatidirinya. Yang seorang penuh pengabdian buat kemanusiaan, yang seorang penuh dengan persundalan. Beberapa bentar kemudian ia melanjutkan pembacaannya, sementara Sratdadi dan Lindu Segara mendengar sambil memperhatikan. Tiap kali Mas Ayu Tunjung memberikan bubukan kapur pada lontar yang dibacanya.
"Lepas dari semua kegembiraan dan kebahagiaan yang kaualami itu, aku berharap bahwa kau tidak akan pernah lupa pada kewajiban yang dibebankan oleh zaman kepadamu!
Beban yang gunung-gemunung, memang. Tapi mulia. Tiada manusia yang lebih mulia dari pada orang yang mempersembahkan karya dan darmanya bagi kemanusiaan. Bagi kehidupan! Bagi kebebasan umat manusia! Apa sebab? Sebab meniadakan kebebasan adalah perampasan hak yang paling hakiki. Memang kebebasan adalah hak yang paling hakiki. Meniadakan kebebasan berarti kejahatan yang tak bertara! Karena itu berjuanglah, Anakku!"
Lagi. Ketiga orang itu saling pandang. Hati mereka serasa dijamah oleh jari-jari Wong Agung Wilis. Kemudian diremas- remas agar tidak terbuai oleh mimpi di bulan madu. Beberapa bentar kemudian mereka sampai pada bagian akhir dari surat Wong Agung Wilis:
"Kawula Blambangan sengaja dipunahkan. Seperti orang- orang Banda yang dipunahkan oleh Yan Pieter Zoen Coen.
Itulah sebabnya aku berkata beban yang tersampir di pundak kalian, amat berat. Bagaimanapun juga kawula harus diselamatkan. Jangan dibiarkan mereka dibantai! Jika kita hendak memerangi VOC, maka kita tidak boleh berperang sendiri. Kemenangan hanya akan tercapai jika seluruh Nusantara bangkit bersama-sama! Ingat-ingat ini, Anakku!
Kebijakan jauh lebih penting demi keselamatan kawula yang tinggal sendikit itu. Mempertahankan hidup serta kehidupan mereka adalah juga semulia-mulianya pekerjaan "
Ketiga orang itu menyebut. Rupanya Wong Agung amat sedih mendengar berita kerusakan kawula Blahnbangan.
"Apa akal kita sekarang?" Lindu Segara bertanya setelah beberapa saat mereka terdiam. Masing-masing merenung. Berbincang dengan pendapatnya sendiri.
"Yah, kita harus berpikir. Memang benar pendapat Ayahanda itu. Rupanya beliau belajar dari kekalahan demi kekalahan semua kerajaan di Nusantara ini," Sratdadi menjawab sambil menarik napas dalam-dalam. Setelah itu menopangkan siku di atas pahanya yang sedang bersila itu, sementara telapak tangannya menyangga dagunya. Sedang Mas Ayu Tunjung memandang ke halaman. Ayam-ayam sedang bercengkerama dengan sesamanya. Bebek-bebek juga sibuk mencari makanan di parit yang menuju ke sawah. "Mungkin saja kita harus berbagi tugas. Kita tidak boleh memancing peperangan di Blambangan," Lindu Segara mengutarakan pendapatnya.
"Kita menempuh cara seperti Singa Manjuruh? Karena jera kita berlaku seperti dia?" Sratdadi bangkit dari duduknya. Lalu mendekati jendela sambil bersedekap ia pandang gunung- gunung biru yang jauh. Pikirannya mencoba menerawang jauh. Jauh sekali ke masa depan.
Mas Ayu Tunjung menarik napas panjang. Susunya naik- turun seirama tarikan napasnya. Kemudian pelan-pelan ia berkata,
"Tidak! Kita bukan Singa Manjuruh. Kita tidak pernah akan jera. Tapi sebelum menentukan, marilah kita menengok masa lalu bangsa kita. Pengalaman leluhur kita. Sebagai cermin untuk menentukan sikap dan langkah." Berhenti sebentar. Ia bersirih. Memerah bibirnya yang tipis itu. Warna kulit manggis yang merekah. Sratdadi dan Lindu Segara menoleh padanya.
"Kita dulu bangsa besar," Ayu Tunjung memulai lagi. "Tapi sekarang menjadi bangsa kerdil. Apa sebabnya? Dulunya kita adalah bangsa laut. Bangsa yang menguasai laut. Dengan kata lain menguasai perniagaan. Kemudian dikalahkan oleh bangsa lain, dan kita digiring ke pantai. Tidak lama kemudian dikalahkan lagi dan digiring ke pedalaman. Pegunungan dan hutan-hutan. Akibatnya kita makin jauh dari kemajuan. Sebab semua kemajuan dikuasai oleh bangsa yang memiliki alat perhubungan. Nah, kita dikecohkan sedemikian rupa, sehingga lautan yang dulunya adalah alat perhubungan bagi kita, telah menjadi semacam pembatas yang amat sulit dilintasi. Kanda, mari kita menyadari hal ini."
"Jagat Pramudita! Jagat Bathara!" Sratdadi menyebut. "Di mana-mana, di bumi Nusantara ini tidak akan ada
kebebasan. Barangkali di samudra luas sana kita akan menemukannya. Salahkah pendapat hamba ini, Kanda?" Ayu Tunjung mendekati calon suaminya.
"Tidak, Adinda!" Sratdadi menghela napas dalam-dalam. Ia pandang tajam-tajam Ayu Tunjung. "Aku baru mendengarnya sekarang. Andaikata itu sudah kita ketahui sejak Ayahanda masih menjadi patih amangkubhumi Blambangan dulu, maka pendapat itu akan sangat banyak gunanya. Kita masih memiliki armada untuk menjadikan Blambangan bangsa pelaut.
Mas Ayu mengelus dada Sratdadi. Kemudian dengan ekor matanya ia memandang Lindu Segara dengan sekilas. Sambil tersenyum ia melanjutkan,
"Tak ada gunanya berandai-andai dengan masa lalu. Apa saja yang kita punya harini itulah modal kita. Jika harini kita cuma punya Harya Lindu Segara, maka dengannyalah kita akan membangun jiwa pelaut dalam bangsa kita. Sekali lagi, Kanda jangan mengandai-andai. Kita harus pandai-pandai mengukur kemampuan. Barangsiapa yang tak mampu mengukur kemampuannya sendiri, ia sedang melangkah pada kehancuran."
"Hyang Bathara!" kedua pemuda itu menyebut berbareng. Sesaat, dua saat, lima saat, sepuluh saat, mereka membisu. Tercekam lamunan masing-masing.
"Baiklah. Jika demikian hamba akan segera turun kelaut begitu selesai upacara pernikahan suci. Itu sesuai dengan rencana. Tapi kali ini dengan tujuan membangun kembali armada Blambangan. Bukan sekadar membuat kerepotan kecil bagi VOC," Lindu Segara berjanji.
"Barangkali ada gunanya jika daku pun turun ke laut.
Pekerjaanku sebagai seorang Rsi sebaiknya diambil alih oleh Mas Ayu..."
"Kehadiran Rsi Ropo masih diperlukan bagi kawula Blambangan. Lihat! Dengan tiadanya Kanda di tengah-tengah mereka, mereka tak ubahnya anak-anak ayam yang kehilangan induknya." Mas Ayu Tunjung keberatan. "Hamba cuma mampu memberikan pengetahuan sedikit buat mereka. Tapi yang mereka butuhkan sekarang bukan cuma pengetahuan. Mereka butuh keterampilan, sikap hati, dan setelah itu baru pengetahuan."
"Betul, Yang Mulia," Lindu Segara mendukung.
Kembali ruangan dilanda keheningan. Sampai beberapa jenak. Tiba-tiba saja, Sratdadi melihat Tunjek berlari menuju pendapa. Mencari-cari. Kemudian cepat ke bale pracabaan. Kosong. Masuk ruangan di mana ketiganya sedang berbincang. Napas pemuda itu terengah-engah.
"Ada apa, Tunjek? Tampaknya tergopoh-gopoh."
"Oh, Ampunkan hamba, Yang Tersuci, menghadap tanpa dipanggil."
"Tak apa, Tunjek. Apa ada sesuatu yang penting?" "Barangkali amat penting. Serombongan besar Kompeni
mengepung Songgon "
"Jagat Dewa Pramudita!" Rsi Ropo tersenyum. dengan sabar ia berkata pada Tunjek, "Baiklah. Mereka mencari aku terus-menerus. Suruh teman-temanmu menyingkir. Aku akan hadapi mereka."
"Hutan-hutan juga sudah dikepung."
"Mereka tidak akan usik kalian. Mereka ingin bersua denganku! Jika demikian bersiaplah! Panggil Cantrik Anggada! Aku mau bicara padanya."
Tunjek segera memunggunginya. Setelah Tunjek pergi, Tunjung segera mengutarakan pendapatnya,
"Biarkan mereka masuk, Kanda. Hamba akan hadapi mereka." "Lalu aku? Sembunyi?"
"Kanda bersama Lindu Segara bersiap-siap. Bukan bersembunyi. Satria Blambangan pantang bersembunyi. Apalagi seorang..." Mas Ayu Tunjung tidak melanjutkan tapi mengerling.
Beberapa bentar kemudian Anggada naik. Tapi kemudian pergi lagi bersama Rsi Ropo dan Harya Lindu Segara.
Sementara Ayu Tunjung menyiapkan diri. Memang tak ada waktu untuk menyiapkan diri dengan baik bagi Sratdadi.
Namun dia adalah bekas menteri mukha pada pemerintah pengasingan Blambangan. Nalurinya terbiasa me-| nyiapkan suatu gelar peperangan. Apalagi sebenarnya kawula Songgon adalah orang-orang terlatih. Dengan cepat mereka menyelinap ke dalam gerumbul penyimpanan senjata.
Laporan Tunjek bahwa Kompeni telah mengepung Songgon tentu tidak masuk akal bagi Sratdadi. Sebelum pergi ke Bengkulu, Sratdadi telah memasang berbagai jebakan di seputar hutan desa itu. Maka ia tak terlalu gelisah. Malah Tunjek yang ternganga, waktu masuk ke semak-semak yang dipimpin oleh Anggada, mereka menerima pembagian senjata api laras panjang. Tak ada yang karatan. Berarti senjata- senjata itu setiap waktu dirawat dengan baik.
"Jangan ada yang menembak sebelum ada perintahku!" setiap kali memberikan senjata Anggada memperingatkan.
Laporan Tunjek tidak sepenuhnya salah. Karena memang saat itu telah datang pasukan berkuda menuju ke Songgon. Semua jadi tegang dalam persembunyian masing-masing.
Semut merah merupakan barisan pengganggu yang menjengkelkan di persembunyian seperti itu. Tapi mereka adalah orang-orang terlatih. Baik menyembunyikan senjata maupun diri. Jadi semut dan nyamuk hutan, seolah telah menjadi sahabat mereka. Walau sebenarnyalah merupakan aniaya bagi lainnya. DaR persembunyian semacam itu mereka akan leluasa melihat siapa saja yang datang. Wanita yang tua serta mereka yang telah renta tidak ikut sembunyi. Akibatnya waktu barisan Kompeni masuk mereka cuma mendapatkan wanita-wanita renta dan lelaki yang sudah gemetar waktu bicara. Itu sebabnya rombongan kedua segera diberi isyarat untuk masuk. Rombongan pertama terdiri dari tiga puluh orang. Semua mengenakan topi yang terbuat dari anyaman mendong (sebangsa rumput yang bisa dipakai bahan pembuat tikar) Barangkali buatan Sidayu atau Gresik, para pengintip tidak tahu. Yang mereka tahu tak seorang pun kulit putih di antara mereka. Tapi Sratdadi memerintahkan agar mereka tetap waspada di persembunyian masing-masing.
Justru yang berkulit sawo matang macam itu, lebih galak dari yang kulit putih.
Semua pengintip menjadi amat terkejut. Ternyata rombongan kedua memikul sebuah tandu. Tentu seorang pembesar, pikir Mas Sratdadi dan Lindu Segara. Siapa ya? Mata tajam Sratdadi serta Lindu Segara segera tahu bahwa yang di dalam tandu itu ternyata seorang wanita. Masih muda. Memang lebih tua jika dibanding Ayu Tunjung. Mengenakan kemben. Pertanda bahwa ia bukan wanita Ciwa. Berkali wanita dalam tandu itu melongok ke kiri dan kanan. Seperti agak gelisah. Tak ada penyambutan. Padahal saat ini ia adalah wanita tertinggi di Blambangan. Sratdadi kenal benar. Arinten dari Pakis. Di belakang tandu itu ada sebuah jodang (Sebuah tempat bentuknya seperti pandosa (alat pemikul mayat), tapi ini biasanya dipakai memikul makanan. 0,5x2 m panjangnya) yang juga dipikul oleh empat orang seperti halnya tandu di depannya. Di belakangnya lagi baru sepuluh orang berkuda dan bersenjata lengkap. Kompeni. Tentu semua pengintai bertanya-tanya. Apa maksud mereka kemari?
Ternyata mereka terus berjalan menuju ke pertapaan. Apa mereka sudah mendengar rencana perkawinan Rsi Ropo dengan Mas Ayu Tunjung sehingga datang membawa berbagai macam hadiah? Apalagi waktu Arinten benar-benar turun di depan pendapa, dan masuk diiringi para pemikul jodang, rasanya dugaan itu makin kuat. Pasukan pun berhenti dengan aba-aba dari pemimpinnya. Cepat membentuk jajar mengepung pertapaan.
Mas Ayu Tunjung menjemput dengan mengenakan kain sutera putih. Juga selendang sutra melilit lehernya, sedang kedua ujung selendang itu berkibar di belakang tubuhnya karena angin. Gelang emas serta kalung permata pemberian Wong Agung Wilis menjadi pelengkap keanggunannya siang itu. Binggalnya jelas gaya Bali terbaru, membuat Mas Ayu Arinten tersentak. Ia hitung-hitung, berapa harga permata dan perhiasan lain yang menempel di tubuh montok Mas Ayu Tunjung ini. Belum kutang emas yang menghias putik susu serta pending yang terlilit di bawah pusar.
Sekalipun pernah bersua ketika gadis itu masih dalam istana Lateng (ibukota Blambangan zaman Wong Agung Wilis, (baca: Tanah Semenanjung)) dulu, mau tak mau Arinten iri melihat wajah Mas Ayu Tunjung. Tidak heran jika adiknya tergila-gila. Barangkali tidak berlebihan jika di seluruh bumi Blambangan saat ini, tak ada wajah sesempurna wajahnya.
Senyum nya... Aduh! Bagaimana iman adikku tidak rontok? Bibir tipis diwarnai merah samar oleh tak ada wajah sesempurna wajahnya. Senyumnya... Aduh! Bagaimana iman adikku tidak rontok? Bibir tipis diwarnai merah samar oleh kinang. Caranya berdiri di atas titian pendapa itu, oh, anggunnya...
"Dirgahayu, Yang Mulia," Ayu Tunjung menyapa sebelum tamunya mengucapkan salam. "Jika tidak salah, maka yang datang saat ini adalah tamu agung dari Pakis. Yang Mulia Arinten?"
"Betul, Yang Mulia. Eh... Dirgahayu," terpaksa membalas dengan terbata-bata. Aduh, sorot mata gadis ini, seperti bintang fajar Pelan-pelan ia mendekati titian. Sungguh makin jelas. Kulitnya benar-benar halus tanpa cela, kendati sawo matang. Malah cenderung hitam manis. Kemudian ia mengikuti langkah sang gadis menuju tengah pendapa. Cukup besar pendapa ini jika dibanding pendapa Pakis. Pilar-pilarnya terbuat dari kayu hitam. Diukir-ukir. Kendati atapnya terbuat dari ijuk.
Di tengah pendapa itu terdapat sebuah amben besar. "Kita duduk di sini, Yang Mulia."
Mas Ayu Arinten sekali lagi memandang sekelilingnya. Tak ada kisi-kisi yang menutup tempat mereka duduk. Sungguh Tunjung tak menerima pengaruh dari kebudayaan baru yang sedang berkembang di kota-kota Blambangan lainnya.
"Tentu, Yang Mulia. Yang Hamba kerjakan ini seperti janur di puncak gunung. Karena memang tak pernah dilakukan oleh siapa pun sebelum ini. Karena didorong oleh keinginan hati mengumpulkan semua tulang yang terpisah. Tulang darah Tawang Alun!"
"Luar biasa kebudayaan baru di Blambangan sekarang!" Ayu Tunjung tertawa ramah. Sementara itu para pengawalnya datang mempersembahkan kinangan. Kemudian menjauh ke sudut pendapa. Ada lima orang dara yang berjaga di seputar mereka. Pengawal Ayu Arinten tak diperkenankan masuk.
Kendati mereka adalah kompeni. "Yang Mulia sudah pandai memperhalus kata-kata." Tertawa lagi. Arinten menjadi salah tingkah. Pandangannya berlarian ke segala arah untuk mencari pegangan.
"Tapi Yang Mulia sendiri berkias-kias," (menggunakan kiasan) ia membalas.
Kembali terdengar suara tawa Ayu Tunjung. Arinten pun ikut tertawa. "Menyesuaikan diri
dengan adat keraton baru " Ayu makin ramah saja. "Hamba pikir memang ini tak pernah dikerjakan oleh Wong
Agung Wilis sekalipun," Arinten mencoba menjajagi. Ayu Tunjung diam sejenak. Terdengar lagi suara Arinten, "Juga tidak oleh Mas Rempek anumerta.
"Barangkali saja Wong Agung Wilis tidak melihat keuntungan yang bisa diambil dari berkerumunnya keluarga dalam satu atap. Sebagai seorang yang bijak tentu beliau melihat banyak kesulitan yang akan kita temui dalam mengumpulkan tulang yang..." "Banyak kesulitan?"
"Ya. Banyak kesulitan," tegas Ayu Tunjung. "Apa sebabnya?"
"Tiap orang punya kepentingan dan pandangan hidup yang tidak sama. Dan karena itu sukar dipersatukan."
"Ya, Tuhan... Ya, Allah...!" Arinten menyebut. Namun Ayu Tunjung segera menyodorkan sirih. Kemudian Arinten menuturkan bahwa ia membawa oleh-oleh dari Mas Ngalit. Kemudian Arinten memerintahkan agar jodang-nya dibawa masuk. Setelannya dibuka dihadapan Tunjung. Ternyata bukan makanan. Tapi bermacam-macam perhiasan, kemban, kain batik dari Madura juga barang pecah-belah.
"Jagat Bathara! Apakah manfaatnya benda semacam ini?
Dan bukankah hamba tak memerlukannya? Kain cita, kemban, dan pakaian macam begini, tidak seharusnya dianugerahkan pada hamba."
Arinten tersenyum. Kini ia merasa menang. Walau ia tahu harga perhiasan di tubuh Ayu juga amat mahal. Dengan rasa lebih unggul ia kembali duduk. Tapi ia segera mencari jalan untuk menerobos hati Ayu Tunjung.
"Itu adalah sekadar persembahan. Karena kami amat mengagumi Yang Mulia. Betapa tidak? Di tengah desa yang dikelilingi bukit dan gunung, tinggal bersama kawula miskin seperti ini, Yang Mulia masih dapat menyambut kami dengan hati gembira. Senyum Yang Mulia membuat wajah manis Yang Mulia kian berseri. Ah, barangkali benar kata orang, bahwa kepedihan hati akan mematahkan semangat. Dan jika semangat telah musnah maka ketuaan menyerbu dengan cepatnya."
"Ada-ada saja Yang Mulia ini." Ayu Tunjung tersenyum lagi sambil berjalan ke amben. Suara binggalnya berdetingan memenuhi ruangan. Sementara burung-burung bercanda dengan teman-temannya di halaman. Nyiur tampak melambai, bergantian dengan daun pisang, karena ditiup angin pegunungan. Tidak ada kegerahan di sini. Beberapa bentar Ayu Tunjung menyambung lagi,
"Tentu bukan tanpa kepedihan. Namun hamba senang berdamai dengan alam seputar hamba. Selebihnya adalah pengertian yang menyebabkannya. Sebab hati orang yang berpengertian tidak pernah memburu kebodohan."
"Apa yang bisa diburu di lingkungan yang jauh dari istana begini? Jauh dari tatakrama pergaulan seperti laiknya satria? Sebenarnyalah kedatangan hamba untuk mencabut Yang Mulia dari kepapaan di tengah rimba seperti ini."
Mas Ayu Tunjung tertawa ramah untuk keseki-an kalinya.
Lalu menjawab,
"Suatu pertanyaan sekaligus pernyataan yang amat bagus." Berhenti sebentar. "Cuma sayang, tidak sepatutnya itu ditujukan pada hamba. Tentu Yang Mulia belum lupa bahwa hamba berasal dari istana. Istana yang berdaulat! Yang tidak dipengaruhi oleh bangsa asing. Maka kalau boleh hamba bertanya, apa yang dapat diburu dalam istana? Tak lebih dari pemanjaan nafsu yang tanpa batas."
"Ya Allah..."
"Hamba melihat sekarang istana adalah tempat berkumpul para pemalas yang menyebarkan jalan berduri. Lebih dari itu, pagar maut." "Ya, ampun! Ya, Aliahku... dengan kata lain Yang Mulia tidak berniat lagi tinggal di istana?"
Mas Ayu Tunjung diam sebentar. Kembali meracik Tdnang. "Padahal... niat kami mengumpulkan kembali keluarga
Tawang Alun sudah bulat. Niat mulia kami itu ditandai dengan kedatangan kami ke sini dengan harapan agar Yang Mulia berkenan menerima sekapur sirih yang kami persembahkan ini dan sudi meninggalkan Songgon. Sepatutnyalah Yang Mulia berada di istana Blambangan, karena Yang Mulia-lah yang lebih berhak. Sebenarnya apa yang telah kami lakukan semua selama ini, tak lain untuk membangunkan kembali cakrawarti (kejayaan, kewibawaan) wangsa Tawang Alun."
"Yang Mulia memaksudkan agar kami bersatu, seatap dengan Mas Ngalit? Menjadi istrinya?" Ayu Tunjung masih saja tersenyum.
"Bukankah itu lebih baik? Demi cakrawarti..." "Bagaimana mungkin cakrawarti bisa dibangun di atas
persundalan?"
"Ya, Allah..." Arinten tersentak. Kini hatinya seperti digores sembilu. Mendadak lemas. Seolah tulang-tulangnya copot dari persendiannya. Satu pertanyaan yang tak pernah diduganya. Namun ia berusaha menahan hati.
"Memperoleh kesenangan atau harta dengan lidah dusta adalah kesia-siaan. Karena ia telah mewarnai hidup dengan kekejian. Kedurhakaan!" Ayu Tunjung bergumam seperti pada diri sendiri. Lagi Arinten mengernyitkan keningnya.
"Apakah ini berarti Yang Mulia menuduh kami sundal?" "Yang memburu kesenangan pribadi dengan
mempersembahkan kepuasan bagi orang lain, dan tidak
memperhatikan jatidirinya, atau lebih jika hamba sebut kehilangan jatidirinya, sebenarnya ia telah bersundal. Para Yang Mulia dapat menilai diri sendiri. Bukan hamba." "Masya Allah... apa yang kami kerjakan selama ini demi tanah semenanjung Blambangan yang suci, demi bumi kelahiran tercinta. Ya, demi Allah."
Untuk kesekian kalinya Mas Ayu Tunjung memperdengarkan suara tawanya yang lirih. Semua pengawalnya pun nampak tersenyum melihat Arinten seolah meriup kecil. Apalagi setelah Mas Ayu Tunjung menjawab,
"Barangsiapa tak berpengalaman akan percaya pada tiap perkataan. Tapi orang bijak akan mempertimbangkan langkahnya." Diam sebentar. Bangkit dan dengan perlahan ia menunjuk pada jodang yang tergeletak di lantai seraya katanya,
"Sebaiknyalah benda ini dikembalikan pada pemiliknya.
Hamba tidak memerlukannya lagi." "Tak memerlukan?"
"Wanita memerlukan perhiasan untuk memperindah diri. Sebab keindahan itu menawan. Tapi seperti yang Yang Mulia lihat, apakah hamba kurang perhiasan? Permata? Tapi hamba tidak pernah mendapatkannya dengan jalan merampas milik orang lain."
"Ya, Tuhan. Kami tak pernah melakukan seperti itu "
"Yang Mulia memang tak melakukannya sendiri. Tapi yang dijual oleh Mas Ngalit untuk mencukupkan membayar pajak tahunan itu tanah siapa? Hutan siapa? Moyangnya? Bukan! Itu milik negara. Tapi bukankah ia menjualnya dengan semena- mena? Belum lagi ladang dan sawah kawula? Berapa banyak yang harus direlakan? Satria seharusnya menjadi pelindung.
Tapi Mas Ngalit tak lebih dari momok. Balikan sampar bagi kawula Blambangan sendiri. Ya, sampar!"
"Yang Mulia menuduh? Itu akan segera berubah jika Yang Mulia tinggal bersama kami. Yang Mulia akan melihat bahwa tuduhan Yang Mulia itu salah." "Ampunkan hamba. Biarlah hamba tetap tinggal di tempat ini bersama seluruh kawula. Kiranya lebih tenteram makan sepiring sayur dengan kasih, dari pada segumpal daging dengan kebencian dari seluruh kawula."
"Kawula membenci kami? Lihat, Belanda saja menghargai kami."
"Jika Yang Mulia mengerti, maka Yang Mulia akan memiliki hikmat untuk melihat semua ini. Sebab hikmat tinggal di dalam hati orang berpengertian. Tapi tak dikenal oleh orang bebal. Bukankah cuma bandit yang dapat memuji bandit lainnya?"
“Astaghfirullaah!" kembali Arinten tersentak. "Yang Mulia tidak menyadari bahwa zaman telah berubah. Mercu suar Wong Agung Wilis telah ambruk!" Kini Arinten berdiri.
Suaranya bergetar menahan getaran jiwa. "Pada zaman baru kita harus membentuk tatanan baru, yang lebih baik, yang lebih beradab. Kendati itu datangnya dari orang asing! Hamba ingin menasihatkan, berhati-hatilah dengan ucapan Yang Mulia itu. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran."
"Terima kasih, Yang Mulia!" Tunjung tetap memamerkan senyum "Berbahagialah tiap orang yang mengerti jalannya sendiri. Karena disebut berkhidmat dan cerdik. Tapi orang bebal ditipu oleh kesemuan. Sebab ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dalam tertawa hati bisa merana. Kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Karena demikianlah kehidupan."
"Yang Mulia menolak lamaran kami?"
"Sepatutnyalah bandit berkumpul dengan sundal! Bukan dengan hamba!" Mas Ayu Tunjung mengucapkan selamat jalan sekalipun Arinten belum berpamitan. Dan mau tak mau, di bawah pandang Ayu Tunjung yang ..berwibawa itu, pengawalnya mengangkut kembali jodang itu. Ia mengerti betul, setiap paksaan akan dijawab dengan perlawanan oleh Tunjung. Kecut hatinya. Meriup. Ah, tak berani ia pandang wajah gadis itu lagi.
***
Kegembiraan kawula Songgon kala menyambut dan merayakan perkawinan Rsi Ropo dan Mas Ayu Tunjung tiba- tiba saja agak terganggu. Laporan peronda kampung menyebutkan bahwa Songgon dikepung oleh Kompeni. Semua orang yang masuk desa itu ditahan, demikian pula orang songgon dilarang keluar. Para pedagang juga dilarang memasuki wilayah Songgon.
Sementara itu Lindu Segara meloloskan diri melewati jalur rahasia, Songgon ke Sempu, yang dulu sering digunakan oleh Mas Ayu Prabu atau Sratdadi.*) Ia harus siap kembali ke kapal. Supaya anak buahnya tidak terlalu risau menunggu.
Tapi cita-citanya sudah mantap. Ia ingin membangun armada yang kuat. Seperti yang dianjurkan oleh Ayu Tunjung. Diam- diam ia mengagumi kecerdasan wanita itu. Ah, betapa bahagianya punya istri semacam itu. Baik wajahnya, otaknya, dan hatinya. Bukan main bahagia Sratdadi.
Tapi tahan berapa lamakah kebahagiaan pemuda itu? Saat ini Songgon mulai dikepung. Ia harus menolongnya.
Menyelamatkan dua orang muda 2 yang amat serasi itu. Ah, jika orang pernah mendengar cerita tentang Dewa Kamajaya dan Kamaratih, tentulah itu gambaran tentang dua muda-mudi yang saat ini sedang memadu kasih di Songgon itu. Apa upayaku? Tapi harus! 'Harus!
Perjalanannya kian jauh meninggalkan desa yang dikepung dengan pagar betis itu. Tentu maksudnya agar desa itu kelaparan dan kemudian menyerah terhadap kemauan Mas Ngalit. Mas Ngalit! Awas, kau. Ingat-ingat ini. Di daratan kau berkuasa. Tapi jika saja kau turun ke laut, maka nyawamu akan punah di dasar laut! ancam Lindu Segara dalam hati.
Orang Songgon akan dibunuh secara pelan-pelan dan satu- satu. Atau mereka mau membayar upeti dan mengirimkan tenaga buat bergotong-royong di Sumberwangi. Lebih dari itu yang dituntut Mas Ngalit supaya Tunjung...
Namun setelah Lindu Segara sampai di Sumberwangi, berita yang diterima jauh lebih banyak dari apa yang ia lihat sendiri di Songgon. Ternyata bukan cuma Songgon yang sedang dikepung. Tapi juga beberapa hutan yang dicurigai ada sisa-sisa 4 laskar Bayu. Bahkan ada juga yang dibakar.
Nasib buruk juga diterima oleh Sentolo bersama seratus delapan puluh dua orang pengikutnya, terdiri dari lelaki, wanita, dan anak-anak. Semua terkepung dalam Hutan Sentul, sebelah selatan kota Sumberwangi. Sentolo dan kawan- kawannya menolak dirumahkan kembali. Menolak bersemu-ka dengan para punggawa. Itu sebabnya Mas Ngalit kehabisan sabar dan memerintahkan supaya Hutan Sentul dikepung. Tak seorang pun diperbolehkan masuk atau keluar dari hutan itu. Kompeni memasang pagar betis atas permintaan Mas Ngalit.
Persoalan bermula dari dijualnya Hutan Sentul pada Babah Koh A Jie, teman Baba Song. Ngalit berusaha agar pembangunan kota yang direncanakan menjadi ibukota Blambangan itu cepat selesai. Untuk itu tentu saja ia ingin melibatkan semua pihak. Termasuk para. pedagang yang biasanya mempunyai banyak budak. Setiap penghambatan akan ditindak. Kendati ia tidak akan menggunakan sebutir peluru pun. Karena itu berarti biaya yang harus dipikul.
Sentolo yang memang sejak Bayu kalah meninggalkan rumah dan sawah-ladangnya berusaha menghalangi pembabatan hutan yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka. Para budak pembabat takut melihat munculnya mereka. Kurus-kurus. Telanjang dada.
Laki-perempuan, besar-kecil, tua-muda, semua tinggal tulang terbungkus kulit. Wajah mereka pucat. Berjalan seolah terhuyung, mereka bersama-sama mendekati para pembabat hutan. Kesan yang mereka lihat saat itu seolah ratusan hantu datang menyerang. Tentu saja itu membuat semua budak pembabat terbirit-birit sambil berteriak-teriak.
Mas Ngalit marah luar biasa kala Juru Kunci melaporkan apa yang terjadi.
"Cobalah, Yang Mulia... bicara pada Sentolo. Daripada berkelana di hutan begitu, kan lebih baik mereka kembali ke Lateng atau Sumberwangi. Begitu banyak rumah dan ladang serta sawah yang merana."
"Mereka menolak bersemuka dengan kita. Hamba sudah mencoba. Bahkan hamba sendiri masuk ke tengah perkemahan mereka."
"Perkemahan?"
"Ya-, dalam hutan mereka membuat semacam rumah- rumah kecil berdindingkan dedaunan. Ada juga yang terbuat dari ilalang seperti atapnya. Tapi umumnya lebih pendek dari jika kita berdiri. Jadi mereka merunduk jika memasuki tempat perlindungan atau perkemahan mereka itu."
"Ya, Allah! Hidup macam begitu lebih suka?"
"Seorang anak kecil berkata pada kami, lebih baik makan batu daripada harus bersujud pada kita!"
"Astaghfirullaah aPazhiim! Siapa yang mengajar mereka semacam itu? Masih kecil?" "Anak-anak."
"Itu meracuni jiwa anak! Seharusnya mereka disadarkan agar mendapatkan masa yang cemerlang. Mengapa mereka tidak sadar akan pentingnya pembangunan? Jika demikian, tutup jalan keluar ataupun masuk hutan itu! Aku ingin tahu, bagaimana mereka makan cuma dengan semboyan! Mereka bertahan karena mendapat bantuan dari Songgon."
Terjadilah perintah Mas Ngalit. Hari pertama, kedua, keenam, Sentolo dan kawan-kawannya, masih makan sisa perbekalan. Hari ketujuh, sampai hari kelima belas mereka mengisi perut dengan mencari uwi (tumbuhan menjalar, daunnya hampir seperti sirih, akarnya seperti ubi jalar tapi sebesar kepala manusia) hutan, gembili, dan minum dari air yang menetes dari mata air. Satu bulan tidak menggoyahkan Sentolo.
Bulan kedua Sentolo masih bertahan dengan makan ontong (kuncup dari kumpulan bunga pisang) pisang hutan. Tapi kemudian semua habis. Musim kering pun tiba. Jerit tangis anak-anak yang kelaparan mulai terdengar oleh para pengepungnya. Satu demi satu anak-anak berguguran. Bau badeg mulai menyebar ke luar hutan. Pertanda bahwa anak- anak tidak lagi bisa dikuburkan. Tak ada lagi kekuatan untuk menggali tanah. Sentolo juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Sedih hatinya. Demikiankah nasib junjungannya Wong Agung Wilis waktu dikepung di kota Lateng dulu? (baca: Tanah Semenanjung)
Ayam hutan, malio, musang, ular, kadal, dan semua binatang yang dulu memenuhi Hutan Sentul semua punah dimakan oleh anak buah Sentolo. Sekali lagi ada suara berseru-seru, agar Sentolo dan kawan-kawannya menyerah. Akan diberi pengampunan dan rumah serta makanan yang layak. Mereka akan diperlakukan baik-baik. Kebimbangan menggoda hati Sentolo. Maka ia berkata pada sisa anak buahnya. Kepalanya mulai pening. Pandangannya pun mulai kabur. Kendati matanya tampak kian lebar.
"Jika kalian ingin menyerah, menyerahlah!" suaranya parau.
Semua diam.
Ia ulangi berkata. Tapi tetap tiada berjawab.
"Wong Agung tidak pernah kalah, Sentolo. Mengapa kita kalah oleh karena kelaparan. Mati lebih suka daripada jadi budak si bule!" seorang yang telah amat tua berkata.
Suaranya dalam. Hampir tiada terdengar. "Bukankah itu suara Mas Ngalit?" Sentolo mencoba. "Ah, penipu! Mengapa kita mau dengar suara penipu.
Orang yang menerima pujian dari musuh, tidak pernah baik
bagi kita."
Umur Sentolo serasa disambung lagi mendengar kata-kata itu. Walau kemudian sore harinya orang tua itu menghembuskan napas terakhir. Istrinya tetap setia di sampingnya. Kurus wanita itu sekarang. Matanya tampak cekung dan pucat.
"Kau menyerah, istriku?" Wanita itu merangkul suaminya. Ia cium pipi yang kempong itu. Belum tua sebenarnya usia
Sentolo. Seperti halnya dia sendiri. Kelaparan membuat ia nampak amat tua. Dingin pipi itu.
"Kakang...," bisik wanita itu, "kau rela aku dipersundalkan?" Suatu pertanyaan yang amat menggores hati. Diam-diam air mata Sentolo meleleh. Terharu. Begitu setia wanita ini. "Walau lapar seperti ini?"
"Walau maut menjemput, aku pantang bersundal!"
Bau badeg makin merajalela. Lalat berdatangan tanpa diundang. Merubung semua-mua! Yang hidup maupun yang mati. Mas Ngalit tetap pada pendiriannya. Sentolo sudah tidak mampu lagi menengok siapa yang mati harini. Istrinya kaku dalam pelukannya. Ia tak kuasa melepas pelukan itu. Ia tak punya tenaga. Ah, istrinya telah mati entah kapan. Barangkali tadi malam waktu ia tertidur setelah ia menjawab pertanyaan istrinya. Kakang, apakah kau mencintai aku? Dan ia menjawab di kegelapan malam...
"Istriku, bukankah aku tak pernah memperduakan cinta?" "Ah...," desah bahagia keluar dari bibir istrinya. Kembali
wanita itu mempererat rangkulan-nya. Sampai sekarang. Sampai ia mati. Kini ia sendiri juga akan mati. Pelan-pelan ia membaringkan diri. Pikirannya melayang pada masa lalu. Indah. Tapi musnah. Kini bibirnya berkomat-kamit. Pelukan istrinya tidak juga bisa lepas. Sentolo berserah dalam doa. Doa! Beberapa bentar kemudian Sentolo terkejut. Matanya mengerjap. Telinganya menajam. Ia dengar suara gemertak. Jagat Dewa! Hutan ini dibakar!