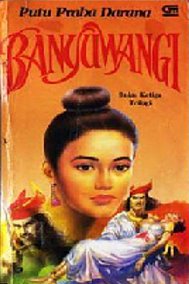Bab 3 : Rindu
Hati Sratdadi dan Harya Lindu Segara sama-sama berdebar.
Pantai sudah nampak jelas. Sebentar lagi mereka akan mendarat. Tekad mereka bulat. Mereka akan mendarat di Sumberwangiv Sayup-sayup mereka telah mendengar bahwa Sumberwangi sedang dirombak untuk menjadi ibukota baru. Mereka juga sudah mendengar bahwa Mas Ngalit, dari Pakis, diangkat menjadi penguasa tertinggi Blambangan.
Kedua orang muda yang telah saling berjanji sebaya mukti sebaya pati itu kemudian menukar pakaian mereka dengan pakaian saudagar. Dan memang keduanya akan mendarat dengan membawa kain mori buatan India, sutera Cina, tembikar, cengkeh, pala, dan lada. Sebelum itu mereka telah merapat di Buleleng untuk mendaratkan senjata-senjata yang seharusnya diperuntukkan laskar Bayu. Tapi karena keduanya mendengar bahwa Bayu sudah tumpas-tapis, maka mereka mendaratkan senjata-senjata itu di Bali. Di samping itu mereka memerlukan diri menghadap Wong
Agung Wilis, untuk memohon petunjuk dan berita tentang keadaan di Blambangan.
Sepercik harapan memuncrat di sudut hati Mas Sratdadi ketika ayahnya, Wong Agung Wilis, berkata dengan suara berat,
"Bayu memang punah, Nak. Tapi kawula Blambangan tak pernah kalah. Mereka sekarang meninggalkan huma dan rumah untuk menyatakan sikapnya. Tidak mudah mencari penampilan semacam itu, Nak. Mereka sudah diremukkan tapi masih berani menyatakan sikap. Lebih baik makan batu daripada harus menjadi budak! Bukankah itu sikap yang baik?"
"Hamba, Yang Mulia," ia menyembah pada ayahnya.
"Ada lagi yang masih membesarkan hatiku. Mas Ayu Tunjung, anak Kanda Mangkuningrat, ternyata mampu mengambil sikap perwira. Ia sekarang tinggal di Songgon. Dan memimpin pembangkangan. Mereka tidak membayar pajak. Mereka tidak mau kerja paksa."
"Jagat Bathara!"
"Aku dengar ia setia menantimu, Nak?"
Pertanyaan yang membuat Sratdadi tersipu. Memerah. Ia menunduk di bawah sorot mata ayah serta ibu tirinya. Namun mata cekung dan bersinar tajam itu seolah mengikutinya. Ah, Wong Agung Wilis yang perkasa dulu itu, kini telah menjadi tua dan kurus. Cuma kumisnya saja yang gemuk. Untung ibu tiriku begitu baik. Dia pula barangkali yang menyambung umur ayahku, gumam Sratdadi kala meninggalkan puri ayahnya. Kembali suara ayahnya bergema,
"Cuma kalian berdua yang tersisa. Blambangan telah kehilangan semua satria sejatinya. Karena itu cuma pada pundak kalian berdua aku menitipkan cita dan cintaku. Citra darah Agung Wilis, yang tidak pernah menyerah pada siapa dan apa pun."
"Hamba, Yang Mulia," kedua orang itu menjawab. Bagaimanapun kekaguman mereka kian bertambah pada
Agung Wilis. Walau berbaring di pangkuan istrinya, ia mampu
melihat negerinya dengan mata batin. Juga mampu mendengar semua kejadian bahkan keluhan kawula Blambangan. Padahal Mas Ngalit, yang duduk di singgasana Blambangan tidak pernah mendengar rintih kawulanya sendiri.
"Bagaimana bisa mendengar, karena memang telinganya telah disumpal harta dan keenakan pribadi," Sratdadi menjawab kata-kata Lindu Segara.
"Hamba akan membuat perhitungan kelak. Jika mungkin dengan tangan sendiri ini hamba akan membunuh tiap penjual bangsa. Penjual negeri!" Serapah keluar dari mulut sambil menunjukkan kedua lengannya. "Mari kita menundukkan kepala untuk mohon kekuatan Hyang Maha Durga, juga tuntunannya, sebelum menginjakkan kaki kembali ke tanah kelahiran yang tercinta ini."
"Hamba, Yang Mulia." Seluruh awak kapal diperintahkan ikut berdoa. Keduanya akan turun terlebih dahulu. Semua anak buah kapal diperintahkan melakukan penyamaran.
Dermaga jauh lebih luas dari semula. Bakau-bakau pelindung pantai telah sama sekali punah. Dibabat dan dijual sebagai kayu bakar. Atau dijadikan arang. Ini adalah gejala yang buruk dari pembangunan. Apalagi tenaga pembangunan itu umumnya bukan tenaga pribumi. Rupanya perpisahan yang lama dengan anak-istri telah membuat mereka jadi liar.
Hampir di tiap sudut jalan sekarang ada kedai makanan dan minuman. Bahkan semalam-malaman mereka tidak tutup. Di bagian belakang kedai itu biasanya terdapat sebuah rumah besar. Dalam rumah besar itu ada bilik-bilik kecil. Antara satu bilik dengan bilik lain dipisahkan oleh dinding yang terbuat kulit bambu. Ternyata kedai-kedai itu merangkap jadi rumah penginapan bagi para pelaut asing yang singgah. Dalam kedai besar itu banyak pelayan wanita muda yang juga bertugas sebagai penghibur bagi para pelaut.
"Jagat Bathara!" Sratdadi menyebut dalam hati. "Sejak kapan Blambangan mengenal kebudayaan macam begini?" ia mencoba berbisik pada Harya Lindu Segara.
Yang ditanya cuma mengangkat bahu. Mereka perhatikan kuli-kuli pelabuhan yang hilir-mudik. Umumnya orang Madura dan Jawa. Betul Wong Agung Wilis, jika demikian. Mereka tidak sudi jadi kuli. Karenanya menyingkir ke pedalaman.
Mereka berjalan terus sambil mencari penginapan yang lebih besar dan agak bersih. Bangunan mesjid hampir selesai. Tidak satu pun pura atau candi. Kedua orang itu mengerti apa artinya. * Perang paregreg(perang perontokan) kedua telah usai. Maka nilai-nilai peradaban Blambangan asli pun di punahkan. Mau tak mau Blambangan harus menerima peradaban baru. Suka atau tidak. Arti dari suatu kekalahan menelan apa saja yang dijejalkan oleh pemenang.
Mereka masuk ke sebuah penginapan yang ternyata milik orang Arab. Mengenakan topi putih, baju putih lengan panjang, terbuat dari mori India. Bersarung tenun buatan Gresik.
"Ahai, Tuan orang baru? Dari Melayu?" Orang Arab yang menyebut dirinya Makdun itu menanya. Orang ini juga mengangkat diri sebagai raja kecil. Para wanita di sekelilingnya. Ada yang memijit, ada yang mengipas. Orang- orang dari mana mereka ini? Yang jelas tentulah bukan orang Blambangan. Ah, banyak sekali pendatang baru. Rupanya untuk mengisi rumah dan huma yang ditinggal pergi oleh penghuninya.
"Ya. Ya. Kami dari Melayu," Lindu Segara menjawab cepat.
Ia memang mahir berbahasa Melayu.
Makdun melambaikan tangan pada seorang wanita. Dan orang itu mendapat tugas mengantar keduanya ke kamar. Muda dan ramah.
"Tuan-tuan membutuhkan teman tidur malam ini?" tanya wanita itu tanpa malu-malu. Bahasa Melayunya kurang baik. Menunjukkan bahwa ia baru belajar. "Jika iya, hamba akan panggilkan seorang teman hamba yang baru datang dari Jawa."
"Dari Jawa? Jawa mana? Bukankah Blambangan juga Jawa?" Harya Lindu Segara masih terus mengajukan pertanyaan.
Sratdadi mendapatkan kamar lebih dahulu. Dan ia mengatakan bahwa tidak perlu dicarikan teman tidur.
"Musim dingin begini?"
"Nantilah aku pikirkan. Hari masih siang." "Baik, Tuan." Wanita itu kemudian menunjukkan satu kamar lagi untuk Harya. Dan melanjutkan keterangannya, bahwa orang Blambangan tidak suka dipanggil Jawa. Bahkan mereka menjuluki para pendatang Jawa ini sebagai kaum ora (dari bahasa Jawa, artinya 'tidak'). Sebaliknya orang Jawa menjuluki mereka sebagai kaum osing (dari bahasa Blambangan, artinya 'tidak').
"Sangat menarik ceritamu. Aku senang kau menemaniku malam ini. Tapi di mana kami dapat membeli kuda yang bagus? Kami akan berkeliling Blambangan untuk menawarkan dagangan kami. Itu sebabnya diperlukan kuda yang kuat dan bagus."
"Di sudut jalan sebelah timur ada pasar hewan. Tuan bisa mencari di sana-."
"Terima kasih." Harya memberikan sekeping perak. "Sungguh Tuan ingin ditemani nanti malam?"
"Tentu. Tapi tunggu apakah temanku tidak ingin menjelajah dulu wilayah Blambangan yang elok ini. Dia pelaut baru." Harya tersenyum. Wanita itu berkikik.
"Hati-hati, Tuan, jika berkeliling Blambangan jangan sampai melukai hati orang osing. Mereka suka membunuh. Mereka orang-orang keras. Karena itu kami dikirim ke sini, yang mula- mula adalah orang-orang terhukum. Dan kami adalah yah, yang di Mataram pun nasib kami adalah..* seperti ini. Hidup dari belas kasian lelaki yang kesepian. Dan membutuhkan hiburan."
"Jadi... umumnya kalian sudah berpengalaman di tempat asal kalian?"
"Ah, tidak... cuma terpaksa. Baru kok, Tuan. Baru tiga..." "Tiga apa?" '
"Tiga tahun. Ya, terpaksa." Wanita itu menunduk. Harya Lindu Segara menyebut dalam hati. Baru tiga tahun?
Dengan kata lain sebelum di Blambangan pun ia sudah melakukan penjualan diri demi makannya.
"Apakah semua temanmu juga demikian?"
"Ya, Tuan. Semua wanita yang didatangkan dari daerah Mataram bernasib sama dengan hamba, Tuan "
"Baiklah, kautemani aku nanti malam, ya." "Baik, Tuan. Yang satu lagi?"
"Dia lebih suka mencari sendiri. Pergilah dulu. Aku akan mencari kuda."
Wanita muda itu menghormat sambil mengerling lalu pergi. Sementara itu Lindu Segara sendiri segera keluar diikuti Mas Sratdadi. Mereka menuju tempat penjualan kuda. Agak mahal memang. Itu, kebiasaan pedagang. Begitu melihat orang asing dan tampaknya beruang, maka harga langsung dinaikkan.
Siapa yang tak ingin untung banyak? Tapi Mas Sratdadi dan Lindu Segara tidak menggubris soal harga. Berapapun asal kudanya baik.
"Kuda ini benar-benar dari Sumba, Tuan." "Kami butuh dua."
"Ah, dua? apakah Tuan juga ingin naik kuda Sumba?" Penjual kuda itu memandang Mas Sratdadi agak heran. Karena tubuh Mas Sratdadi yang lebih ramping dibanding Lindu Segara. Tertawa juga Mas Sratdadi melihat perlakuan orang itu. Tapi ia senang. Dengan kata lain penyamarannya berhasil.
"Kami sungguh-sungguh." Ia menegaskan tanpa mempedulikan lecehan penjual kuda. Dan makin terlonggok- longgoklah blantik (makelar (penjual) hewan) kuda itu ketika Sratdadi memilih kuda tinggi besar yang berwarna hitam- pekat. Sedang Lindu Segara mendapatkan yang berwarna coklat, dengan belang putih dekat kukunya serta ada segitiga putih dikepalanya. Setelah memasang pelana dengan terlebih dahulu mengelus kepala kuda itu. Rupanya itu memang bekas milik pejalan jauh yang agak lama tidak ditunggangi setelah dijual. Maka tidak heran mereka amat senang begitu menerima belaian kedua orang itu. Tanda persahabatan dari manusia. Sebagai balasannya kedua kuda itu menyapa mereka dengan ringkikan panjang, mirip tertawa karena gembira.
Kegelapan pun turun. Lampu-lampu dipasang di pinggir- pinggir jalan. Terutama sekali sepanjang jalan raya utama. Beberapa bentar kemudian kedua orang itu telah menyusuri jalan-jalan kota Sumberwangi dan menuju ke barat. Gardu- gardu penjagaan tidak pernah mencurigai orang asing.
Demikian halnya kedua orang itu. Dengan amat mudah lolos dari pemeriksaan penjaga kota karena mereka tidak berbahasa Blambangan. Menggunakan Melayu dengan amat baiknya.
Di atas punggung kuda Sratdadi merasa segar kembali.
Seolah keperkasaannya masa lampau muncul kembali. Apalagi kudanya seolah rindu melintas padang luas. Berlari seperti anak panah lepas dari busurnya.
"Betapa lama kita tidak merasakan kehahagiaan seperti ini, Harya. Sayang saat ini malam. Dan tidak ada tempat aman untuk kita."
"Kita akan mencoba di Lateng, Yang Mulia. Kita coba mencari penginapan. Kuda ini sudah lama tidak dilarikan dalam jarak yang jauh. Ia harus kita beri makan dan jika perlu dibelikan jamu terlebih dahulu.",
Betul juga, pikir Sratdadi. Ia menurut. Untuk mencapai Lateng mereka perlu istirahat dua kali di tengah hutan.
Mentari pagi menyambut kehadiran mereka di kota Lateng. Kabut enggan berlalu. Rapat menutup jalan-jalan. Rumput dan ilalang saling berlomba. Demikian juga tumbuhan perdu lainnya, berusaha menutup semua jalan. Sratdadi geleng kepala. Lateng, yang dulu menjadi pusat kerajaan, kini telah menjadi kota mati. Tidak ada lagi kesibukan di pagi hari. Di mana bekas pasar dulu? Mas Sratdadi memperlambat lari kudanya. Celananya basah oleh embun yang menempel di rerumputan. Demikian pula bunga-bunga rum-put-pahitan tak ubahnya serbuk halus putih kekuning-kuningan. Tapi kedua orang itu tetap tidak menghentikan langkah kaki kudanya.
Rumah-rumah yang dulu berjajar di kiri-kanan jalan masuk kota itu, kini sebagian besar porak-poranda. Halaman- halamannya tak terawat. Merana tanpa tangan yang menyentuhnya. Kedua orang itu menyebut dalam hati. Daun pisang dan kelapa bergoyang ditiup angin pagi. Seolah memberikan penghormatan pada keduanya.
"Otak macam apa yang tinggal di kepala manusia perusak hidup dan kehidupan seperti ini?" Sratdadi berdesis. Teman seperjalanannya diam.
"Atau barangkali hati mereka tidak terbuat dari darah dan kumparan otot-otot halus dan lembut!
Sehingga tak sepercik pun rasa kemanusiaan dalam kepalanya. Hemh..." Sratdadi mengerutkan giginya. Tinjunya mengepal. Perasaan menyesal menelusuri tiap relung hatinya. Namun sebagai satria sekaligus brahmana ia segera menyadari bahwa penyesalan itu tidak berarti. Sekilas ia teringat wajah ayahnya yang menasihatinya. "Keadaan yang akan kaulihat di negerimu itu, jangan kauanggap sebagai kepahitan. Tapi justru harus diterima dengan ucapan syukur. Karena sebenarnyalah keadaan itu memberimu kesempatan untuk menjadi orang besar di antara wangsa Tawang Alun.
Jika kau mampu membangun kembali negerimu dari kehancurannya, maka kau adalah orang besar. Bangunlah negeri itu dengan tanganmu sendiri! Dengan kepalamu sendiri! Bukan seperti Mas Ngalit sekarang. Ia membangun ibukota dengan utang pada kekuatan asing. Utang yang sebenarnya adalah penjualan kedaulatan negeri! Ingat, Nak! Bukan kebenaran yang membuat kemenangan! Tapi kemenangan yang akan membuat kebenaran!
Sratdadi menggeragap seperti terbangun dari mimpi. Harya Lindu Segara jadi terkejut.
"Ada apa, Yang Mulia?" Harya Lindu Segara bertanya sambil terus memperhatikan wajah Sratdadi yang berkeringat. Keringat dingin. Ah, kini . ia mengusap mukanya dengan telapak tangan. Kemudian menggeleng-gelengkan kepala.
Berulang-ulang. Entah sampai pada kali yang kebera-pa ia baru berhenti.
"Tidak apa-apa, Lindu. Aku jadi terbakar melihat kenyataan ini. Kita terlambat. Andai saja kita dapat mengusahakan bahan makanan jian senjata yang cukup dan baik, tentunya keadaan akan berbeda sekarang."
"Bukan salah kita, Yang Mulia. Pelayaran kita sangat ditentukan oleh angin. Apa boleh buat?"
Sratdadi kembali menghela'napas panjang. Juga Lindu Segara. Kemudian keduanya sama-sama menghentikan kuda mereka. Tercenung buat sesaat.
"Kita menuju tempat penjual rumput dan makanan kuda!" Sratdadi le_bih dulu tersadar. "Setelah itu kita mencari tempat istirahat."
Keduanya meneruskan perjalanan. Melingkar untuk menghindari loji-loji milik Kompeni ataupun para saudagar Cina, Arab, dan India. Tentu di kawasan itu tak ada penjual rumput dan katul. Sebab bau tai kuda akan mengganggu mereka.
"Kekalahan ini sudah kita ketahui kala di Surabaya dulu.
Tidakkah Yang Mulia ingat kala di pinggir Kali Mas para tawanan dari Blambangan digiring untuk kerja paksa mengeruk kali?" "Ya, laki-perempuan dengan tangan diborgol. Kau ingat berapa jumlah mereka waktu itu?"
"Hamba tidak ingat secara tepat, Yang Mulia. Hamba rasa ada seribu tujuh ratus dua puluh tiga orang. Sebagian kecil saja lelaki dalam rombongan tawanan itu. Yang lebih banyak adalah wanita dan anak-anak."
"Bukankah waktu itu tanggal dua puluh dua, Kartika?" (tanggal 7 November 1772)
"Ah, ternyata ingatan Yang Mulia tidak pernah dapat dihapus sekalipun oleh tingginya gelombang." Lindu Segara berusaha menghibur pemimpinnya.
"Peristiwa sepenting itu seharusnya tidak boleh kita lupakan. Kaulihat nasib mereka? Cobalah -ingat! Jika tidak ada pedagang budak belian datang, tentulah nasib mengeruk Kali Mas dengan tangan dan kaki dirantai begitu tidak akan berhenti. Celakanya lagi, kita tidak bisa menolong. Karena yang boleh membeli budak belian hanya kulit putih dan kuning. Juga yang memperdagangkannya."
"Semuanya telah berlalu, Yang Mulia. Mari kita memikirkan yang akan datang. Kita bisa berunding dengan Mas Ayu Tunjung sebagai calon pendamping Yang Mulia."
Keduanya sampai di tempat yang mereka cari. Setelah menitipkan kuda sambil berpesan agar diberi makanan serta jamu, mereka bergesa mencari penginapan. Mereka ingin melihat-lihat tiap kota besar Blambangan terlebih dahulu sebelum masuk Songgon. Walau untuk itu Mas Sratdadi harus menahan rindu yang telah menggunung.
***
Udara dingin merambat ke setiap penjuru. Namun pilar- pilar pendapa kadipaten di Sumberwangi tidak nampak terpengaruh. Malam juga merangkak kian larut. Semua orang sudah mene-lusup di bawah selimut masing-masing. Terlena oleh buaian mimpi. Mas Ngalit masih saja duduk , sendiri di ruang tengah kadipaten yang baru saja selesai dipugar. Bukan karena menikmati indahnya ukir-ukiran yang mengelilingi ruangan itu. Bukan juga memandangi pilar-pilar kayu jati coklat yang juga bagus itu. Bukan! Pandangannya menatap tempat kosong.
Berkali ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mondar-mandir. Gadis-gadis pelayan tidak diperkenankannya mendekat. Kendati biasanya malam-malam begitu ia suka mendekap mereka. Pertemuannya dengan Mas Ayu Tunjung benar-benar mengguncangkan jiwanya. Rambutnya, alisnya, matanya, hidungnya, bibir dan janggutnya... aduh, belum pernah ia melihat perawan semanis itu. Alangkah bahagia jika ia bisa memandang wanita itu sepanjang hari. Melihat gontainya, dan... aduhai lenggangnya...
Ah, mengapa semua jadi tak terlupakan. Aduh-susunya, hemh, pusarmu... Tangan Mas Ngalit bergerak-gerak seolah meraba-raba perut Ayu Tunjung. Dan entah bagaimana seolah Mas Ayu Tunjung sudah ada di depannya.
"Ya, Tuhan... Allah kauberikan ia padaku?"
Dan gadis itu tersenyum. Bibir tipis seperti kulit buah manggis yang merekah.
"Mas Ayu? Kau datang? Kau mau jadi istriku?" Cuma senyuman yang menjawab.
Mas Ngalit seolah tak percaya. Untuk sesaat ia terdiam.
Namun kemudian berkata,
"Jika kau mau jadi istriku, minta apa saja aku turuti asal tidak minta turunnya bintang dan rembulan... ha... ha... ha."
Wajah Mas Ayu masih menyungging senyum.
"Kau nanti juga jadi orang Islam seperti aku. Jangan pakai nama Mas Ayu Tunjung. Aku akan panggil kau Sri Tanjung... Sri artinya Nur Ilahi. Sebab istri Bathara Wisnu juga bernama Dewi Sri. Aku akan sama dengan Bathara Wisnu. Sri Tanjung... Mari..." Mas Ngalit berdiri. Mas Ayu Tunjung tidak menjawab. Tampak mundur sedikit. Mas Ngalit berjalan mendekat. Perlahan-lahan. Mas Ayu Tunjung melambaikan tangan. Menjauh setapak. Mas Ngalit berusaha menangkapnya.
"Mari, Bathara Wisnu..." Tampak Tunjung tersenyum menggemaskan. Tapi tiap kali ditangkap, menghindar.
Hilanglah sabar Mas Ngalit. Keinginannya membopong gadis itu ke pembaringan sudah tak tertahan. Maka secepat kilat dia bergerak, menubruk si gadis. Tapi apa yang terjadi kemudian tidaklah dia sadari. Tubuh si gadis ternyata keras. Muka dan kepalanya seolah dipukul martil berat. Berkati-kati. Dan Mas Ngalit baru sadar menjelang pagi kala seorang pelayan akan menyapu ruangan itu. Bahwa semalam ia cuma menubruk pilar.
Kepalanya berat. Ternyata bengkak. "Ampun, Yang Mulia. Apa yang terjadi?"
"Ah, entah ya? Barangkali aku terlalu lelah, semalam aku menubruk tiang. Ah, kalian memasang lampu kurang terang. Besok tambah penerangan di sini!" Mas Ngalit berbohong kemudian berjalan masuk kamarnya.
"Eh, jangan beritahu siapa-siapa!" katanya sebelum menutup pintu.
Betapa terkejut Mas Ngalit kala melihat wajahnya di cermin. Bengkak. Ah, malu... Mengapa kaupermalukan aku semacam ini, Sri Tanjung? Ya, kau Sri Tanjung. Darah Tawang Alun berjodoh dengan darah Tawang Alun. Tentu aku akan jadi raja besar dan jaya. Ah, aku jadi sultan!
Ah, sebaiknya aku suruh Kanda Arinten untuk melamarnya.
Ya, siapa orang yang tepat? Tapi ah, bagaimana caranya. Mudah saja, ia suruh seorang pengawal pergi ke Pakis untuk memanggil Mas Ayu Arinten.
"Beritahu kakakku itu bahwa aku sedang sakit, jadi tidak dapat datang sendiri."
"Hamba, Yang Mulia."
Perjalanan dari Pakis ke Sumberwangi bukanlah menempuh jarak yang dekat. Apalagi bagi wanita yang tidak terlatih.
Melewati rimba raya yang lebat. Jurang-jurang. Maka memakan waktu yang cukup lama. Dan dalam penantian akan kedatangan kakaknya, Mas Ngalit tidak mampu mengebas bayang-bayang Mas Ayu Tunjung. Mengapa kau masih menyebut dirimu sebagai
Mas Ayu Tunjung? Bukankah aku telah memberimu nama Sri Tanjung? tanyanya suatu malam. Tentu para wanita muda yang biasa menghiburnya jadi heran karena Mas Ngalit tidak memperhatikan mereka lagi. Bahkan tampaknya sang adipati itu lebih senang duduk sendiri.
Demikian juga halnya malam itu. Untuk kese-kian kali Mas Ngalit melambaikan tangan, memberi isyarat agar mereka menjauh.
"Tentu terkena guna-guna perawan Blambangan," bisik salah seorang selir itu.
"Jangan curiga! Barangkali terlalu lelah. Bayangkan, membangun kota semacam ini."
"Tapi dulu-dulu tidak seperti itu!"
Kusak-kusuk berjalan terus. Tapi Mas Ngalit malam itu benar-benar tak ingin ditemani. Ia masuk kamar sendirian. Kala ia membuka pintu hampir saja ia berteriak. Ia melihat Ayu Tunjung tidur miring dengan kepala disangga oleh telapak tangan dan tersenyum menyambut kehadirannya. Ngalit terpatri. Terdengar olehnya Mas Ayu Tunjung menyapa dengan suara merdu, "Mari, Suaminda, aku sejak tadi menunggu "
Mas Ngalit berdebar. Kini tampak wanita itu terlentang.
Kaki selonjor sebelah, sedang sebelah kaki ditekyk ke atas. Ah, paha yang begitu mulus.
"Kenapa ragu, Suaminda? Mari "
Mas Ngalit melangkah maju. Tangannya gemetar. Pelan- pelan ia buka bajunya. Demikian pula kainnya. Pelan-pelan ia naik ke pembaringan. Tangannya terulur meraba paha Mas Ayu Tunjung. Tak bergeming. Jengkel. Ia tangkap pinggang Tunjung dan ditariknya untuk duduk di pangkuannya. Tapi...
cuma sebuah guling. Mas Ngalit penasaran.
***
Sebagaimana biasa, pada hari Radite Mas Ayu Tunjung meneruskan kebiasaan Rsi Ropo saat sebelum perang, ia mengajar murid-muridnya. Tidak sebanyak murid Rsi Ropo tentunya. Karena memang jumlah pribumi Blambangan saat itu cuma tinggal sekitar tiga ribu orang saja. Semua punah dilanda perang. Siapa yang berani menentang VOC akan dipunahkan. Inilah modal. Kekuasaan dari kaum bermodal. Siapa saja! Ya, siapa pun yang berani coba-coba mengusik kekuasaan modal, pasti akan dibinasakan! Baik secara kejam dipunahkan sama sekali seperti pribumi Banda oleh Yan Pieter Zoen Coen, yang menyewa kaum samurai Jepang, atau dengan cara yang santun. Seperti yang dilakukan oleh Bong Swi Hoo yang kelak bergelar Sunan Ngampel. Orang ini telah berhasil memudarkan kekuatan Majapahit secara damai.
Mas Ayu Tunjung sama sekali tak menduga bahwa akhirnya orang-orang Songgon bersedia mendengar semua tuturnya.
Mereka dengan patuh duduk ngelesot diTantai pendapa balai pracabaan. Pilar-pilar masih sekokoh saat Rsi Ropo mengajar. Pengunjung tidak meluber sampai ke halaman. Umumnya orang-orang Songgon sendiri. Cuma sedikit saja pendatang dari luar Songgon yang ikut dalam perhimpunan itu. Petang itu pun demikian halnya. Tapi semua yang duduk mendengar dengan penuh khidmat. Kadang mereka tertawa. Bersama- sama. Kadang mereka bertepuk tangan. Juga bersama-sama. Kadang mereka berdecak kagum. Hampir semua terayun-ayun dalam perasaannya, sesuai dengan yang sedang dibicarakan oleh Mas Ayu Tunjung.
"Jatidiri yang kokoh akan memberikan pada kita makna diri," kata Mas Ayu dalam mengajar sambil duduk bersila di potongan kayu besar dan bulat. Tak ubahnya patung Ken Dedes. Ia pandang semua yang hadir. "Orang yang saat ini akan menenggelamkan kita, berusaha menenggelamkan jatidiri kita terlebih dahulu." Diam lagi sebentar. Menarik napas. Susunya tampak naik-turun. Seirama dengan tarikan napasnya. "Karena itu berhati-hatilah! Dalam merampas jatidiri kita, mereka tidak lagi dengan paksa! Tidak juga dengan perang. Mereka menggunakan cara yang amat sukar untuk dapat kita lihat. Begitu sukarnya, seolah kita sedang mencari jarum yang berjalan dalam air. Mereka menggunakan wanita, minuman, harta benda, dan banyak lagi. Sekali lagi berhati-hatilah terhadap masiya, manuya, madya, dan mutral (ikan, daging, arak, dan wanita)
"Bagaimana dengan Mas Ngalit yang sekarang sedang membangun ibukota baru bagi Blambangan itu? Apakah mungkin dia akan menjadi Ken-Arok bagi Blambangan?" (Arok
= pembangun. Ken Arok = ksatria pembangunan)
'"Inilah yang setiap orang seharusnya tahu. Apa yang sedang dikerjakan Mas Ngalit sekarang?" , Kembali ia diam beberapa bentar. Setelah tidak-seorang pun yang menjawab ia berkata lagi, "Mas Ngalit adalah seorang yang dendam pada kekuasaan Agung Wilis karena tidak mendapat kesempatan ikut berkuasa. Lebih lagi karena ada beberapa kerabat dekatnya yang digantung. Sekarang setelah ia mendapat kesempatan, sekali lagi setelah mendapat kesempatan, segera menjelma menjadi manusia rakus. Ia telah menjual tanah kita, pohon kita, hewan kita. Pendek kata apa saja yang bisa dikeruk dan dijual untuk kekayaan pribadinya. Demikian halnya dengan para pung.-gawa lainnya. Sepeninggal Wong Agung Wilis Blambangan telah jatuh miskin akibat perampok Bali, yang tiada henti menggerayang kekayaan kita.
Sekarang... yah, begitu berkesempatan muncul menjadi sang penguasa, besar atau kecil, segera menjelma menjadi bandit!"
"Tapi mereka berjasa membangun kota-kota "
'"Tampaknya memang begitu. Loji-loji yang dulu tidak pernah ada kini berbaris sepanjang jalan-jalan raya utama. Mesjid-mesjid yang dulu tidak ada kini tampak menghiasi kota. Nah, kita bisa melihat sekarang, sebagian besar bukan kebutuhan kawula Blambangan. Tapi lihat! biaya pembangunan itu siapa yang harus menanggung? Kita! Kita!
Memang biaya itu datang dari VOC sekarang ini. Tapi marilah kita menghitung, Mas Ngalit harus membayar upeti sebanyak enam puluh ribu ringgit. Enam puluh Yah, coba kalikan
dengan uangmu sendiri. Satu ringgit sama dengan dua setengah gulden uang Belanda. Sedangkan satu gulden uang mereka dihargai tiga-ribu picis uang kita. Nah, kalian bisa menghitung sendiri berapa? Dari mana Mas Ngalit akan membayar pada VOC sebegitu besar? Bukankah dari hasil keringat kita? Keringat kita! Sedang saat ini seluruh pribumi Blambangan jumlahnya tinggal tiga ribu orang. Dari jumlah delapan puluh lima ribu sebelum perang kini tinggal tiga ribu! Sisanya dibantai! Jadi tiap orang harus menanggung dua puluh ringgit per tahun. Bayangkan! Tak pernah mimpi, bahwa kita sekarang harus punya utang dua puluh ringgit. Bukankah itu sama dengan seratus lima puluh ribu uang kalian?" Mas Ayu diam sebentar. Mengambil sirih di sampingnya dan mulai berkinang. Giginya yang berbaris rapi seperti deretan bulu kumbang itu menggerus dedaunan yang kemudian menampakkan warna merah. "Anak-anak pun punya utang.
Yang dalam kandungan pun punya utang. Jika tidak mau punya utang maka ia harus tidak menjadi warga Blambangan. Minggat ke Bali misalnya. Karena jika tidak punya utang ia bukan warga Blambangan." Ayu Tunjung memperdengarkan suara tawanya. Ramah. Semua pendengar ikut tertawa. "Mas Ngalit yang membuatnya begitu. Si Arok Blambangan!" Makin riuh. Beberapa lama setelah itu Mas Ayu menutup ajarannya dengan, "Jangan melawan dengan kekuatan senjatamu!
Karena Mas Ngalit tidak pernah segan menumpahkan bangsanya sendiri!"
Semua orang kagum. Enggan rasanya mereka berdiri. Ingin lebih lama lagi mendengar suara merdu itu.
"Jumlah kita makin sedikit. Mempertahankan hidup saat ini sudah merupakan perjuangan tersendiri bagi suatu bangsa yang dengan sengaja hendak ditumpas! Apalagi mempertahankan keberadaan peradabannya."
Setelah berulang Mas Ayu meminta mereka semua istirahat, barulah mereka beranjak. Satu demi satu menyembah dan bangkit. Berat hati mereka. Semalam suntuk pun mereka akan betah berbincang dengan sang gadis. Hati Mas Ayu terharu melihatnya. Mereka rindu mendengar kata- kata surga. Hiburan yang dapat menjelaskan arti kebenaran yang sesungguhnya. Selama ini Mas Ngalit selalu menekankan pada kawula Blambangan, supaya tidak usah belajar berpendapat, ridak usah mengerti siasat kekuasaan! Yang perlu kerja! Kerja tidak banyak" omong! Membangun Blambangan!
Suara jangkrik di malam hari mengiringkan langkah mereka meninggalkan pertapaan. Juga sorot pandang Mas Ayu serta lima orang penga-^ walnya. Para cantrik pun belum beranjak. Namun Mas Ayu segera menjadi terkejut kala akan turun dari tempatnya. Dua orang muda masih saja terpatri di tempat duduknya. Sekalipun semua orang sudah pergi. Keduanya tertunduk dalam-dalam di bawah temaram samar sinar pelita. Mukanya tertutup bayang-bayang sehingga menyulitkan Ayu Tunjung mengenalinya. Diiringi pandang semua cantrik dan pengawalnya, ia turun dan mendekati. Perlahan-lahan seolah berjalan di tepian jurang. Sampai beberapa jarak kemudian ia bertanya,
"Mengapa kalian tidak segera pulang? Ada sesuatu yang ingin kalian utarakan?"
Keduanya diam untuk sesaat. Saling melirik. Lalu sama- sama menyembah. Dan Harya Lindu Segara membuka percakapan sambil menunduk.
"Ampunkan kami berdua, Yang Mulia, kami datang dari jauh. Dan kami ingin bermalam di sini. Adakah tempat?"
"Hyang Dewa Ratu!" Mas Ayu menajamkan mata. Tapi masih saja belum mampu melihat wajah mereka yang tertunduk dan tertutup oleh bayang-bayang. "Tentu semua orang bisa berma.-lam di sini. Asal tidak membuat keonaran." Kemudian ia berbalik menghadap Janaluka. Cantrik Janaluka. "Siapkan kamar untuk mereka."
Cantrik Janaluka segera pergi setelah menyembah. "Kami mengagumi pengetahuan Yang Mulia.
Sungguh, kami tidak bisa mengerti bagaimana Yang Mulia bisa menghitung dengan pasti angka-angka tadi."
Mas Ayu Tunjung tersenyum. Tapi curiga. Sejak tadi mereka tetap tertunduk. Jangan-jangan telik dari Sumberwangi.
"Kita memang sejak lama dijauhkan dari angka-angka. Kebanyakan kita malas menghitung. Itu sebabnya sebagian bangsa Nusantara menjadi miskin. Barangsiapa tidak tahu menghitung, sebenarnya telah menjadi bingung. Karena ia tidak pernah tahu untung dan rugi. Kaum pemilik modal senang kawula tidak tahu angka-angka. Demikian pun Belanda. Karena demikian untuk selamanya kawula tidak akan dapat menghitung, berapa jumlah kekayaan yang seharusnya menjadi hak mereka." Senyumnya makin lebar. "Bayangkan, menghitung haknya sendiri saja tidak bisa! Adakah makhluk yang lebih mengibakan dari mereka? Karena ketidaktahuan akan hak sendiri itulah maka apa yang seharusnya milik mereka, menjadi milik orang lain. Hak mereka menjadi semacam titipan yang bernama utang! Utang yang tak pernah mereka sadari. Karena memang mereka tak pernah melakukannya."
"Jagat Dewa!" kedua tamu itu menyebut kagum. Sratdadi tak mampu lagi menahan hatinya. Suaranya telah membuat Ayu Tunjung terkejut. Dengan mendadak jantungnya berdebar keras. Kembali ia menajamkan matanya. Berganti-ganti ia pandangi kedua pemuda di hadapannya itu. Sratdadi yang merasa salah itu bertanya lagi. Kepalang basah, pikirnya.
"Kenapa Yang Mulia tidak memimpin mereka untuk berperang saja? Supaya dapat dihancurkan semua kelaliman?"
"Hyang Dewa Ratu!" Ayu Tunjung makin gemetar. Senang dan kaget menyatu. "Mengapa aku harus menghadapi penguji secara..."
Ia maju lagi. Selangkah. Dan lagi, selangkah. Makin jelas dan makin jelas. Terkuaklah ingatannya. Maka segera ia menjatuhkan diri... "Hyang Dewa Ratu! Kanda...!"