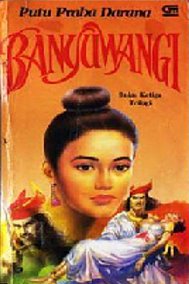Bab 2 : Sarang Camar Pun Punah
Arinten tidak bisa menyambut kehadiran adiknya di Pangpang saat pemuda itu tiba dari Surabaya sesudah dilantik menjadi adipati Blambangan. Sebuah kerajaan yang telah diturunkan derajatnya menjadi kadipaten. Tentu ia tidak berkuasa lagi atas Probolinggo, atau daerah sekitarnya.
Bahkan Lumajang yang pernah menjadi ibukota Blambangan pun tidak. Hujan sehari-hari menandai awal pemerintahan Mas Ngalit pada tahun seribu tujuh ratus tujuh puluh tiga itu. Ingin ia pergi ke Lo Pangpang. Tapi bukan cuma hujan yang menghalanginya. Sebab yang pokok ialah sakitnya.
Kenikmatan dan kepuasan yang ia terima dalam pelukan Juru Kunci semalam kala orang itu menyampaikan berita pengangkatan Mas Ngalit dulu, harus dibayarnya dengan perdarahan. Ia sadar bahwa benih Schophoff punah karena kehebatan Juru Kunci di tempat tidurnya. Ia mengakui bahwa selama ia kenal dengan lelaki, tidak ada yang sehebat Juru Kunci. Benar-benar kuda jantan di malam hari. Sudah lebih lima belas hari, belum juga pulih kekuatannya. Jamu kunyit campur lempuyang serta telur ayam tidak pernah terlambat tiap hari.
"Salah sendiri," bisik seorang dayang pada lainnya. "Apa belum pernah dengar bahwa- Yang Mulia Juru Kunci itu tidak bisa punya anak. Habis nafsunya besar.:.."
"Kau..." Yang lain tersenyum mendengar itu.
"Benar! Ah, Mas Ayu seperti tidak ada puasnya. Sudah punya Tuan Besar kan lumayan. Sekarang mana ada orang lebih berkuasa dari Tuan Besar Residen itu."
"Janda yang kesepian. Maklum saja," yang lebih tua ikut berceloteh. "Dingin-dingin lagi...." Suara kikik mereka tertahan-tahan. Takut kedengaran Mas Ayu Arinten. Bisa kehilangan pekerjaan. Lumayan menjadi dayang daripada petani yang terus terbakar terik mentari. Jika ada untung menjadi dayang bisa berkenalan dengan para pengawal. Lebih-lebih jika ada bangsawan yang menginginkannya. Bisa- bisa menjadi selir bangsawan tersebut.
Beruntung bagi Arinten, jamu-jamu itu ternyata menolongnya. Berangsur-angsur membaik kendati masih belum mampu berjalan jauh. Itu sebabnya ia cuma mengirim surat pada adiknya melalui Juru Kunci.
"Kenapa Kanda Dewi tidak bisa hadir? Apa sakitnya?" Mas Ngalit heran.
"Hamba sama sekali tidak tahu, Yang Mulia. Surat ini hamba terima dari seorang dayang," Juru Kunci gugup. Ia sendiri tidak tahu persis. Memang ia tidak mengerti bahwa sepeninggalnya Arinten keguguran.
"Jika demikian aku sendiri akan menghadap Kanda," katanya sambil menghadap Residen.
Schophoff menerima penghadapan mereka dengan senang.
Kali ini ia akan menjelaskan perintah Gubernur untuk dilaksanakan di Blambangan. Mas Ngalit belum terbiasa memasuki gedung itu. Maka ia perhatikan dengan sungguh- sungguh semua pilar, dinding, dan semua hiasan. Di samping kanan agak ke belakang meja Schophoff berdiri bendera merah-putih-biru. Tepat di dinding atas di belakang kepala Residen terdapat gambar yang tidak ia mengerti maknanya. Lambang kerajaan Belanda. Di samping kiri terdapat beberapa bendera yang juga tak diketahuinya bendera mana. Tapi jauh dalam lubuk hatinya timbul dugaan bahwa itu adalah bendera Kompeni dan VOC. Tidak ada lambang Sonangkara (lambang negara Blambangan; gambar kepala anjing hitam) atau
umbul-umbul Jingga milik kerajaan Blambangan. Ia tahu Belanda sedang menghapus kerajaan Blambangan. Sama dengan kerajaan Nusantara lainnya. Semua harus bersimpuh di bawah telapak kaki si bule. Tapi Mas Ngalit tidak merasa perlu memikirkan itu.
Kegagalan Mas Rempek cukup membuatnya ketakutan. Untuk berpikir seperti Rempek itu pun takut.
"Ah, selamat pagi, Yang Mulia," Schophoff memulai. "Selamat pagi, Tuan," kedua orang itu membalas sambil
menghormat. Sekilas Mas Ngalit melirik dua gadis yang berdiri
di samping kiri-kanan Schophoff sambil mengipasinya. Kendati musim penghujan, Schophoff memerlukan pengipas. Tentu bukan untuk mengusir kegerahan. Tapi untuk memamerkan kebesarannya*
"Tentu Yang Mulia kaget melihat keadaan Blambangan saat ini. Tapi ini dilakukan demi kita semua. Dan ini sudah menjadi perintah Gubernur untuk mengisi kekosongan Blambangan dengan penghuni baru. Supaya mereka dapat memanfaatkan ladang-ladang dan sawah-sawah yang ditinggal oleh pemiliknya. Kewajiban Yang Mulia adalah menjaga agar tidak ada pembangkangan lagi. Sebab pembangkangan akan menyebabkan berkurangnya pendapatan negara. Pendapatan kita semua."
"Jadi mereka diterima menjadi kawula Blambangan?" "Ya! Dengan syarat mereka tidak boleh melakukan apa
yang pernah mereka kerjakan di daerah asal mereka. Dan mereka sanggup dipekerjakan sesuai mau kita."
"Jadi siapakah mereka itu? Dari mana?" Juru Kunci terkejut. Schophoff tertawa. Tubuhnya berguncang-guncang.
"Orang-orang dari wilayah Mataram yang sudah diserahkan pada VOC. Jangan resah, Yang Mulia. Di daerah asal mereka binal, tapi di Blambangan itu tidak boleh terjadi. Kita harus menjinakkan mereka."
"Ya Allah, Hamba belum mengerti, Tuan." Mas Ngalit masih bingung. Apakah lelaki dan perempuan yang datang itu sama- sama binal? Celakalah mereka jika harus memimpin kawanan binal. Satu orang binal mampu meributkan orang satu pedesaan. Apalagi satu kawanan? Ah, bukan cuma sekawanan. Tapi pada kenyataannya mereka telah datang gelombang demi gelombang dengan tanpa persetujuan kawula sebagai pemilik tanah Blambangan. VOC memang tidak pernah memerlukan persetujuan. Tapi semua-mua harus tunduk pada kemauan VOC. Siapa yang mampu membendung? VOC bermodalkan segala. Uang, pasukan, dan kepandaian. Pribumi?
"Yang Mulia akan mengerti nanti. Tapi yang penting sekarang adalah pengaturan mereka. Yang Mulia berdua harus mengatur mereka. Percayalah, kesibukan kerja yang kita berikan akan membuat mereka tidak sempat berpikir tentang kebinalan. Apalagi jika kita mampu menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga jika di antara mereka meluangkan waktu untuk melakukan kebinalannya kembali, mereka akan lapar. Karena itu Yang Mulia harus memberi keterangan pada mereka."
"Baik hamba akan beranjangkarya untuk bersua dengan mereka, kelompok demi kelompok. Dan berbicara dengan mereka, pedesaan demi pedesaan," Mas Ngalit berjanji.
"Akan kami siapkan pengawalan, Yang Mulia." Schophoff girang. "Lalu apa rencana Yang Mulia selanjutnya? Ada usul- usul?"
"Ada. Hamba tidak ingin menempati rumah bekas milik Yang Mulia Jaksanegara. Hamba akan pulang ke Pakis terlebih dahulu. Dan sesegera mungkin hamba ingin membangunkan ibukota baru bagi Blambangan. Bukan lagi di Lateng atau Pangpang. Tapi hamba memilih Bandar Sumber-wangi sebagai ibukota."
"Ya Tuhan!" Schophoff terkejut mendengar usul itu. "Apa alasan Yang Mulia tidak suka tinggal di Pangpang?" "Setelah perang yang amat menyedihkan itu hamba ingin memerintah Blambangan dengan suasana baru. Kota yang baru. Tentu akan lebih baik dari dahulu. Nah, di Sumberwangi kita akan mendirikan istana baru. yang berhadapan dengan Mesjid Agung. Hamba ingin ada Mesjid Agung di ibukota seperti halnya di Bangkalan, atau layaknya ibukota daerah- daerah lain."
"Apakah tidak bisa itu kita bangun di Lateng dan Pangpang atau Wijenan?"
"Di Sumberwangi yang bandar itu kawula lebih banyak bergaul dengan segala bangsa. Pikiran mereka akan lebih terbuka. Karena persinggungan antara darat dan laut membawa arti tersendiri dalam kehidupan. Tiap persinggungan akan mampu mengubah nilai dalam kehidupan. Sebaliknya mereka yang tinggal di pedalaman dengan tanpa persinggungan, maka mereka lebih cenderung berkokoh dalam ajaran moyangnya."
Sekali lagi Schophoff tertawa. Juru Kunci kagum. Dari mana Mas Ngalit yang dulu terkenal sebagai seorang pendiam dan penakut itu belajar berpendapat? Bahkan mengeluarkan pendapatnya seperti itu? Ah, ia tidak salah pilih. Beberapa bulan di Madura rupanya membawa berkah untuk anak muda ini.
"Itu pendapat yang amat bagus. Hamba akan memerintahkan Tuan Pieter Luzac ke Surabaya untuk melaporkan rencana ini pada Gubernur. Sementara itu pembangunan segera akan kita mulai. Yang Mulia harus memerintahkan pada para bekel supaya mengerahkan sebagian penduduk laki-lakinya ke Sumberwangi."
"Besok hamba mulai bergerak. Harini hamba akan pulang ke Pakis. Hamba mohon besok Yang Mulia Juru Kunci bergerak ke utara, sedang hamba ke selatan sambil seterusnya mengawasi pembangunan di Sumberwangi." "Untuk sementara Yang Mulia bisa tinggal di rumah bekas kediaman Yang Mulia Suratru-na. Rumah itu sudah jadi milik VOC dan jika tidak dipergunakan akan kami lelang pada para saudagar. Banyak yang mau. Terutama saudagar Cina."
"Jika demikian, kita tak perlu membangun istana baru. Sebaiknya itu saja diperbaiki. Diperluas dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan seorang adipati."
"Usul yang amat bagus karena dapat mengurangi biaya."
Juru Kunci segera menceritakan pada istrinya kala sampai di rumah. Dan mereka amat gembira karena ternyata Mas Ngalit tidak menghendaki rumah Jaksanegara yang mereka tempati itu. Tidak salah Juru Kunci memilih Mas Ngalit.
Sewajarnya Mas Ngalit berbuat seperti itu, untuk membalas budi Juru Kunci sehingga ia bisa kembali ke Blambangan.
Sementara kakaknya; Nawangsurya tidak mendapat perkenan dari Panembahan Rasamala. Orang tua itu takut kehilangan wanita cantik dari Blambangan yang menjadi lambang bahwa ia pernah mengalahkan Blambangan. Sedih hati Nawangsurya tidak bisa mengikuti perjalanan pulang adiknya.
Sementara itu Mas Ngalit serta beberapa orang pengawalnya memacu kudanya ke Pakis. Ia benar-benar kaget. Orang-orang tidak lagi menjatuhkan diri untuk menyembah pada pembesar negeri yang lewat. Tidak seperti di Madura. Atau daerah lain yang pernah dilihatnya. Perasaan tidak senang membelit hatinya melihat ini. Ia ingin agar semua orang di Blambangan menghormatinya. Perubahan watak yang tak pernah disadarinya. Dulu ia tak berani menuntut itu. Namun kini hatinya menuntut. Siapakah aku maka orang bersikap tidak ramah padaku?
Mas Ngalit tidak pernah menyadari bahwa kawula tidak mengenalnya lagi sekarang. Dahulu ia tak pernah mengenakan pakaian seperti itu. Tidak pernah mengenakan blangkon seperti laiknya pembesar Mataram. Tidak pernah mengenakan baju hitam berenda-renda emas di dadanya. Ia dulu telanjang dada dan berdestar di kepalanya. Kini ia tidak lagi mengenakan pending emas di pinggangnya sebagai tanda bahwa ia adalah seorang pangeran Blambangan. Cuma orang-orang yang baru datang dari daerah Jawa lainnya yang menyembahnya di batas kota Pangpang.
Keheranannya makin dalam kala masuk ke wilayah Pakis. Bukan cuma huma yang tampak merana serta rumah yang kosong. Tapi juga tidak berkeliarannya kawula di sawah tempat mereka mendapatkan makanan. Ke mana mereka itu? Juga tidak nampak si Tole atau si Enduk berlarian di halaman- halaman rumah. Mengapa pasar juga sepi? Tidak lagi nampak berjubel seperti kala Mas Rempek masih hidup. Apakah mereka punah bersama Mas Rempek? Dan kala matanya mencoba menembus ke dalam kedai-kedai itu, kebanyakan pemiliknya kini berkulit kuning dan bermata sipit. Ke mana para pedagang pribumi yang dulu itu?
Apakah seluruh Blambangan menjadi demikian adanya?
Jika demikian berapa jumlah kawula Blambangan yang punah? Sungguh di Pakis ini Mas Ngalit mencoba menghitung berapa yang masih tinggal. Tidak ada sepersepuluh dari jumlah sebelum perang. Sungguh mengagumkan kekuatan pasukan Kompeni yang bergabung dengan Madura, Surabaya* Sidayu, dan Pasuruan. Betapa konyolnya melawan pengaruh asing yang sedang naik daun ini, pikir Mas Ngalit sambil berjanji pada diri sendiri tidak akan mengulangi kesalahan Rempek ataupun Sutanega-ra dan Wangsengsari.
Istana Pakis tampak lengang. Pasukan pengawal juga Kompeni. Apakah kakaknya dikenakan penahanan rumah maka tidak menyambutnya di Pangpang? Apa arti pengawalan oleh Kompeni ini di seputar istana? Pasukan pengawal itu berdiri dalam jajar yang rapi untuk memberi penghormatan. Hatinya agak lega. Apalagi setelah Arinten nampak berjalan lambat-lambat di pendapa untuk menyambutnya. Perlahan sekali seolah takut bumi yang dipijaknya itu akan amblas. Ngalit sama sekali tidak mengerti bahwa perasaan nyeri masih mengganggu di perut bagian bawah kakaknya.
"Assalamuallaikum " Arinten sedikit terkejut mendengar
adiknya memberikan kata pembukaan seperti itu. Namun ia segera sadar, bahwa Madura telah mengubah adiknya. Maka ia pun memberi salam seperti yang pernah diajarkan guru ngaji Jaksanegara dulu.
"Masuklah, Adikku " Ia tidak berani mendekat untuk
memeluk atau mencium adiknya itu. Tatanan baru yang mulai diberlakukan sejak zaman Jaksanegara dan Wangsengsari melarangnya untuk melepas rasa rindu dengan cara itu dengan orang berlainan jenis kecuali suaminya sendiri.
Mas Ngalit menyembah sambil tetap berdiri dari beberapa jarak. Sekalipun rasa rindu mengentak dalam dadanya. Ia gembira melihat kakaknya mengenakan kemben. Juga tidak lagi menyelipkan cundrik di depan perutnya.
"Ke mana semua binti perwara?"
"Jangan lagi mengingat mereka! Cuma ditemani lima orang dayang. Semua orang telah meninggalkan kita. Semua ingin menempuh jalannya sendiri-sendiri."
"Ah, Kanda, mereka tidak mengerti bahwa apa yang kita alami adalah takdir. Itulah celakanya jika tidak mengenal Tuhan. Sekalipun berusaha setengah mati, jika sudah takdir mana mungkin bisa mengalahkan Belanda? Apalagi jika semua adipati di Jawa ini membantu mereka, maka kita tidak ubahnya ketimun!! Ya! Ketimun melawan durian. Ah, kita harus tinggalkan jalan pikiran lama. Hidup dalam tatanan baru dalam jalan pikiran baru pula. Hamba akan mencoba menyadarkan kawula Blambangan. Dan hamba akan membangunkan ibukota baru bagi Blambangan." "Adinda adalah tumpuan harapan Tawang Alun saat ini. Karenanya aku akan membantu sepenuh daya untuk tiap langkahmu."
"Alhamdulillah! Syukur-syukur."
Keduanya masuk ke ruang tengah. Para pengawal telah diperintahkan istirahat. Arinten melihat ada banyak perubahan dalam diri adiknya. Bukan cuma cara berpakaian. Cara bicara dan cara berjalan pun tampak berubah. Tampaknya semua sudah diatur seperti meniru cara Gubernur Van de Burgh berjalan dan bicara. Juga mendengarkan -pembicaraan orang lain yang disertai mengangguk-angguk. Arinten sedikit berdesir. Jangan-jangan hati adiknya itu juga berangsur- angsur berubah seperti Belanda. Ah, jika demikian maka orang Blambangan akan semakin menjauhkan diri. Apakah mungkin mereka menjadi satria Blambangan yang tidak dihormati oleh kawulanya sendiri?
Beberapa bentar kemudian keduanya terlibat dalam pembicaraan yang panjang dan melingkar-lingkar. Saling menceritakan pengalaman. Tapi tentu saja Arinten tidak menceritakan pengalamannya dengan Schophoff yang membuatnya mengandung dan kemudian keguguran karena ulah Juru Kunci. . "Kasihan Kanda Nawangsurya." Arinten mengingat kakaknya yang jelita itu. "Mengapa ia bersusah menjadi seorang istri adipati yang begitu perkasa dan punya nama adiluhung (terhormat dan terkenal)
"Beliau selalu ingat Rempek. Nampaknya beliau sangat dendam pada suaminya sendiri. Kini Panembahan Rasamala sedang sakit. Ketuaan menggerogoti keperkasaannya. Kanda Nawangsurya tidak pernah menghadap jika tidak dipanggil. Padahal sang Panembahan benar-benar mencintainya." Mas Ngalit diam sebentar sambil menebarkan pandangnya ke sekeliling ruangan. Tiba-tiba hatinya berdebar. Ia melihat pet merah berlapis emas pada tepinya. Tentu milik pembesar Kompeni. Arinten tahu adiknya merenungi pet itu. "Milik Tuan Residen." Arinten tersenyum menutup malu. Memang singkat jawabannya. Namun cukup membuat Mas Ngalit membawa nalarnya untuk menelusuri suatu kisah yang panjang. Tentu ia dapat meraba sambungan kata-kata kakaknya. Kendati tidak diucapkan oleh Arinten. Janda kembang dengan wajah menawan. Ah... barangkali sudah takdir bahwa ia harus mengatasi hidupnya dengan jalan begitu. Lagi ia kembali pada ajaran guru mengajinya kala di Madura. Maka ia tidak melanjutkan penyelidikannya dengan pertanyaan. Cuma dalam hati saja. Betulkah orang Blambangan tidak ada yang suka mengawini kakaknya. Atau memang semua satria sudah punah? Sehingga yang tersisa ini cuma sudra saja?
"Mengapa termenung?" Muka Arinten jadi merah kala adiknya itu diam saja.
"Ah, tidak apa-apa, Kanda," Ngalit gugup. "Cuma berpikir tentang rencana esok. Dari mana hamba harus memulai perjalanan. Apa terus ke Lateng? Atau melingkar dulu. Tentu harus ke Pangpang lagi untuk bertemu muka dengan pendatang dari daerah Mataram."
"Pendatang? Dari Mataram?"
"Ya. Untuk mengisi sawah dan rumah yang kosong." "Mereka akan menempati tanah dan rumah yang bukan
haknya? Apakah tidak menimbulkan kemarahan kawula kita, Adinda?"
"Kawula kita selalu membantah mempersembahkan upeti. Karena merasa hidup di atas tanah sendiri. Itu sebabnya kami mendatangkan mereka agar mengelola tanah milik kita dan memper- ? sembahkan upetinya. Barangkali mereka bisa ditekan bahwa upeti itu cuma sebagai sewa tanah."
"Berhati-hatilah, Adikku! Siapa tahu masih i banyak satria yang setia pada Wilis bersembunyi di antara para kawula." "Hamba akan perhatikan nasihat ini, Kanda. Dan hamba sadar bahwa kebahagiaan yang kita cita-citakan tak mungkin dapat digapai dengan mudah. Tapi percayalah pada takdir.
Jika memang Tuhan menghendaki maka manusia tidak pernah menyangka apa bakal terjadi atas dirinya." Kemudian Mas Alit memberi contoh pengangkatannya jadi adipati Blambangan itu. Dia sama sekali tak tahu bahwa untuk pengangkatannya itu ada orang lain yang memperjuangkan. Ada orang lain yang mengatur. Bahkan ada orang lain yang berkorban. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kakaknya sendiri harus mengorbankan kehormatannya di atas tempat tidur dengan banyak orang.
Tapi Arinten tidak ingin mengecewakannya. Justru ia ingin mendorong adiknya agar tidak kalah dengan Wilis 9 atau Rempek.
"Membangun ibukota baru membutuhkan tenaga dan biaya banyak. Dari mana kau akan mendapatkannya, Adinda?"
"Gubernur akan menyediakan biayanya. Bahkan akan membantu mengirimkan tenaga dari Jawa dan Madura. Sebagai imbalannya hamba harus menyerahkan pajak tahunan enam puluh ribu ringgit (1 ringgit = f 2,50) dalam mata uang Belanda. Karena itu sejak sekarang di Blambangan hanya berlaku mata uang Belanda."
"Begitu besar?" Arinten terkejut. Ia sudah tahu nilai uang Belanda karena sering menerima dari Schophoff.
"Kita harus membayar banyak untuk membangun negeri ini, Kanda. Padahal kita tidak punya modal. Sebaliknya VOC bermodal. Kita perlu menjadikan diri kita bermodal lebih dulu, kaya dulu, baru bisa membawa kawula ke arah kebahagiaan. Bagaimana bisa menjadikan negeri ini makmur jika diri sendiri belum makmur? Jika hamba mampu memasukkan enam puluh ribu ringgit tiap tahun maka hamba akan mendapat upah seperlimanya. Belum gaji yang hamba akan terima sebagai punggawa yang mengakui kedaulatan VOC," Mas Ngalit menyatakan kegembiraannya. "Jika Blambangan dapat mendirikan ibukota baru seperti itu tentu kau jadi amat kaya, Adikku. Luar biasa kau ini," Arinten pun memuji.
"Buat apa kita bersusah-susah melawan VOC yang mampu membayar Kompeni begitu banyak. Bahkan membayar bupati- bupati di hampir seluruh Nusantara ini. Hamba melihat sendiri ketika ikut Panembahan Rasamala ke Surabaya, para tawanan perang, yang pernah bertempur disini. Orang-orang Bali. Ah, lelaki dan perempuan digiring untuk dihitung jumlahnya sebelum dijual ke Batavia sebagai budak. Jika hamba tidak salah ingat jumlah mereka sekitar dua ribu lima ratus lima orang. Sebagian besar perempuan.(Kejadian yang dilihat Mas Ngalit itu tertanggal 7 November 1772 sesudah Bayu kalah tanggal 11 Oktober 1772) Nah, apakah bukan cari penyakit seperti itu? Mana tanggung-jawab Wilis? Mana itu para pemimpinnya yang membakar-bakar semangat mereka agar melawan Belanda? Mana?" Mas Ngalit kini berjalan mondar- mandir. Sementara kakaknya cuma memandang semua tingkahnya.
"Mulai besok hamba mengerahkan orang ke Sumberwangi. Bandar kecil itu akan hamba jadikan ramai. Lebih ramai dari zaman Wong Agung Wilis."
"Jika kawula Blambangan tidak mendengarmu?"
"Harus diciptakan suatu cara agar mereka mau mendengar.
Atau akan hamba suruh orang lain yang membangunnya. Besok hamba akan mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri bahwa ibukota dipindahkan ke Sumberwangi. Dan semua "orang harus ikut membangun kota itu agar layak menjadi sebuah ibukota."
"Apakah para bekel mau mendengar perintahmu?" "Kenapa tidak? Kita akan angkat bekel-bekel baru.
Punggawa baru. Mulai dari hamba sendiri sebagai adipati,
dibantu oleh Yang Mulia Juru Kunci sebagai patih, kemudian akan diangkat wedana-wedana yang akan berkuasa di luar ibukota. Misalnya di Lateng, Panarukan, Wije-nan, Pakis, dan lain-lain kota yang ditunjuk VOC. Nah, untuk membantu para wedana itu akan diangkat para kliwon dan mantri dalam. Bekel sekarang tidak boleh berkuasa seperti dahulu. Kini mereka akan dibantu oleh beberapa petinggi. Setiap desa akan ada modin sebagai pembina dalam urusan kita dengan Tuhan dan perkawinan. Kemudian dibantu oleh para kuwu, sebagai kepala-kepala dari para pengayak yang menyampaikan perintah dari atasan."
"Lalu apa jaminan yang kauberikan agar mereka mau menjadi pembantumu."
"Mereka akan mendapat bengkok. Misalnya para bekel akan mendapat bagian tujuh setengah bau (satu bau = 500'Ru. 1 Ru = ± 4x3 meter) sebagai ganjaran. Juga para petinggi, mendapat bagian yang sama dengan bekel. Sedang para modin mendapat satu tiga perempat bau. Sedang kuwu atau pengayah satu setengah bau
lebih sedikit. Lalu mengapa mereka menolak ganjaran sebanyak itu?"
"Aku senang kau punya pendapat seperti itu. Aku dukung." Arinten gembira. Adiknya begitu menguasai ketatanegaraan. "Aku berdoa agar kau berhasil memulihkan cakrawarti wangsa Tawang Alun."
* * *
Mas Ngalit tidak pernah menduga bahwa menjadi seorang adipati berarti juga harus menghadapi berbagai macam masalah. Bukan sekadar duduk di singgasana yang empuk. Karena di beberapa tempat banyak ganjalan-ganjalan. Walau ia sudah menempatkan paman-pamannya, yaitu Pangeran Wirodo, adik ayahnya untuk menjadi . wedana di Lateng dan Pangeran Wiroyudo sebagai wedana di Wijenan. Dan gelar pangeran Blambangan tidak diperkenankan, atau tidak dipergunakan lagi.
Sebagai syahbandar ia mengangkat Tan Eng Gwan, karena orang ini berani mempersembahkan dua ratus ringgit setiap tahun. Bukankah ,dengan begitu mampu menyumbang banyak bagi pembayaran utang Blambangan terhadap VOC. Dia memang mendengar desas-desus yang berkembang di antara para bupati utara, bahwa Gubernur Jenderal di Batavia telah memutuskan agar Blambangan untuk sementara tidak diwajibkan mempersembahkan pajak. Tapi mereka diharuskan mengganti rugi biaya peperangan melawan Bayu, serta membayar utang tepat pada waktunya. Dari mana Mas Ngalit mendapatkan dana jika tidak dari perpajakan? Padahal sekarang ini masih banyak sawah kosong. Karena itu daerah- daerah yang kosong itu perlu diisi. Bukankah jumlah sawah di daerah Sumberwangi yang ada sekarang ini seluas delapan ribu enam belas bau? Baru dua ratus dua puluh dua bau yang dihadiahkan sebagai bumi ganjaran bagi para pejabat.
Termasuk Tan Eng Gwan mendapat bumi ganjaran, karena ia sudah dianggap pejabat. Walau ia kerja di bawah perjanjian kontrak. Seratus sembilan puluh satu bau dibagikan pada orang-orang yang bekerja pada punggawa-punggawa. Jadi mereka tidak berhak untuk menuntut upah. Sisa tanah seluas itu sebagian besar masih kosong, walau sebagian kecil digarap oleh pribumi Blambangan. Namun mereka tidak bersedia diikat oleh peraturan yang diberlakukan oleh patih Blambangan.
Itu merupakan salah satu kendala dalam menghambat masuknya dana bagi pembangunan Blambangan. Tapi Mas Ngalit masih menyabarkan diri. Ia menyadari bahwa ia harus mengambil hati kawula Blambangan yang terus-menerus masih memimpikan hadirnya Wong Agung Wilis. Mereka semua berharap bahwa sang raja adil, yaitu Wong Agung Wilis, akan memerintah kembali di Blambangan. Demikian pula halnya sore hari itu. Juru Kunci menghadap bersama Tan Eng Gwan, Han Tian Boo, dan Baba Song.
Tamu-tamu yang biasanya selalu datang dengan membawa persembahan. Termasuk salah satu dari persembahan istimewa, seorang gadis yang masih sangat muda dan cantik, Su Lie Hwa. Maka ia menyambut mereka dengan amat ramahnya. Pada pelayan ia memerintahkan agar dikeluarkan arak wangi untuk tamu-tamu tersebut. Dan mereka diperkenankan masuk ke beranda di samping halaman tengah. Sehingga a akan bicara dengan santai di taman yang tersedia. Udara segar merupakan suguhan tersendiri, selain kembang- kembang yang berhamburan di seputar tempat duduk mereka. Pohon mahoni meneduhi tempat itu bersama dengan sepasang pohon naga-sari. Tempolong-tempolong besar yang terbuat dari kuningan sengaja disediakan di dekat tiap tempat duduk. Barangkali untuk meludahkan dubang jika para tamu itu menginang. Tapi kecuali Juru Kunci, para tamu itu tidak menginang. Meskipun demikian tempolong-tempolong itu tetap ada gunanya. Sebab mereka sering berdahak.
"Tentu ada masalah yang perlu kubantu maka Tuan-tuan datang sore-sore begini." Mas Ngalit tersenyum ramah. Setiap kali ia berhadapan dengan mereka, setiap kali ingatannya melambai pada Su Lie Hwa.
"Ya. Di beberapa tempat, pembabatan kayu ulin tidak dapat terlaksana. Terutama di daerah yang telah kita sewakan pada Tuan Han Tian Boo," Juru Kunci lebih dulu menjelaskan.
"Apa sebab?"
"Wilayah yang kita sewakan pada Tuan Tian Boo melingkupi daerah Songgon. Ini yang jadi persoalan."
"Kenapa dengan daerah Songgon?" Mas Ngalit menoleh pada Han Tian Boo. Yang bersangkutan buru-buru menunduk dan tangannya segera menyatu. Kemudian diletakkannya di antara kedua pahanya. Di hadapan seorang pejabat pribumi seperti itu ia mengharuskan dirinya sendiri bersopan-sopan. "Ampun, Yang Mulia, kami mendapat tantangan dari orang- orang Songgon. Mereka menghalang-halangi orang-orang kami. Bahkan jika kami melanjutkan pembabatan hutan di seputar Songgon, mereka akan membunuh kami satu per satu. Dan... yang amat menggelisahkan adalah begitu banyaknya jebakan di sana."
"Jebakan?"
"Ya, Yang Mulia. Sudah empat puluh delapan pekerja kami yang tewas masuk ke dalam jebakan. Tidak nampak memang. Seperti tanah biasa. Tapi waktu diinjak oleh beberapa orang, ternyata tanahnya amblas ke bawah, dan di dalam lubang itu sudah tersedia puluhan bambu runcing yang siap menyate tubuh setiap orang yang jatuh ke dalamnya."
"Ya, Allah!"
"Sungguh gawat, Yang Mulia. Maka kami mohon kebijakan Yang Mulia, agar kita tidak rugi. Belum lagi yang terluka oleh tombak bambu yang terpasang dalam semak belukar.
Sungguh mengerikan. Karena pengalaman menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diobati. Mereka semua akan mati pelan-pelan dengan tubuh membiru."
"Racun?" Mas Ngalit tersenyum.
"Hutan seluruh Blambangan penuh racun. Baik yang terpasang dalam songga maupun dalam bambu runcing di jebakan-jebakan itu," Juru Kunci yang menerangkan kini. "Terutama hutan-hutan yang dulu dikuasai laskar Bayu."
"Iblis!" Mas Ngalit mengutuk.
"Orang Songgon bukan cuma berani menghentikan budak- budak pembabat hutan, tapi juga mereka tidak menjual hasil buminya pada Baba Song. Juga tidak ada yang mau membeli dagangan kami," lapor Han Tian Boo lebih lanjut.
"Kita tak dapat memaksa," Juru Kunci menu-Kas. "Persoalan bukan karena kita paksa atau tidak. Masalahnya mereka punya hubungan langsung dengan pedagang- pedagang Portugis dan Bali. Mereka menembus langsung ke Bandar Sumberwangi."
"Astaghfirullaahal'azhiim!" Mas Ngalit kembali menyebut. "Mereka bebas naik ke geladak jung-jung Portugis maupun
Bali. Ini sangat memprihatinkan.",
"Apakah Tuan tidak bisa mencegah orang-orang Portugis atau orang-orang Bali agar tak membeli langsung dari orang Songgon itu?"
"Kami takut mengurangi hasil cukai bandar, Yang Mulia.
Sebab andaikata kita lakukan pengetatan pengawasan, bandar, mereka menjadikan Grajagan, atau mengadakan penyelundupan lewat pantai lainnya."
"Siapa yang memimpin Songgon sekarang?" Mas Ngalit tidak sabar. Ia pandang semua-mua sambil mengernyitkan dahi.
"Seorang gadis. Mas Ayu Tunjung."
"Tidak mungkin seorang wanita mampu berbuat seperti itu." Mas Ngalit tidak percaya. "Tidak boleh seorang wanita memimpin suatu daerah. Harus ada penertiban. Songgon harus tunduk pada kita. Tak boleh mengambil kebijakan sendiri."
"Apakah kita akan melindas mereka dengan perang baru?" Juru Kunci bertanya. Kini semua orang memandang Mas Ngalit. Kini Mas Ngalit terdiam. Sambil menarik napas panjang ia menyandarkan diri pada sandaran kursinya. Sementara suasana menjadi hening.
"Tidak!" tegas Mas Ngalit. "Kita harus hindarkan Blambangan dari perang baru. Sebab pembiayaan perang akan kita pikul, kendati kita akan menang. Dan masih banyak lagi kerusakan yang harus kita tanggung." "Lalu?"
"Kita akan mencoba mendekati mereka. Jika perlu aku sendiri akan turun ke tempat-tempat mereka. Baiklah, sementara kita tarik orang-orang yang membabat hutan di seputar Songgon."
"Lalu?"
"Kita alihkan ke hutan lain. Atau daerah lain. Masih luas daerah kita yang belum terbuka."
"Masalahnya bukan cuma itu. Tapi macam kayu yarrg dapat kita jual untuk galangan-galangan kapal lebih mudah didapat di seputar Songgon."
"Tidak! Di Purwa, Sentolo, dan lain-lainnya masih banyak." "Masalah penjualan madu, sarang burung, kayu manis,
serta beras orang-orang Songgon itu bagaimana?"
"Kita akan cegah. Aku sendiri akan ke sana. Jika tak bisa dicegah, maka mereka harus membayar cukai tinggi."
***
Bulan-bulan pertama pembabatan hutan di seputar Sumberwangi berjalan amat lamban. Kenyataan ini membuat gusar Mas Ngalit yang sudah menempati rumah bekas milik Suratruna. Padahal ia ingin segera selesai. Maka ia segera mengambil langkah yang tak pernah diduga oleh semua orang sebelumnya. Ia tidak peduli apakah langkahnya itu disetujui oleh para pembantunya atau tidak. Yang penting baginya adalah menjadikan Blambangan negeri yang indah dan tertib. Untuk itu ia panggil Juru Kunci.
"Kita harus meminta tambahan tenaga dari Jawa pada Tuan Residen. Kita tidak akan bisa memenuhi ketentuan besarnya pajak jika tahun ini pembangunan ibukota belum selesai. Kita akan membayar utang kita dari pungutan atau pajak bandar. Karenanya pembangunan harus segera selesai." "Bagaimana dengan orang Blambangan sendiri? Apakah mereka tidak bisa kita gerakkan?" Juru Kunci mencoba bertanya.
"Hamba akan bertemu langsung dengan para bekel dan kepala daerah. Di samping itu hamba juga mendengar adanya desa baru di selatan kota Lateng. Adakah kaudengar itu, Yang Mulia?"
"Ampun, Yang Mulia. Tidak pernah."
"Aku akan datang ke sana. Seorang pemimpin laskar pemberontak dari Mataram yang telah menyusup kemari kini membangun sebuah desa menjadi kota yang agak luas. Demi pengikutnya. Tidak "apa. Kita akan tampung mereka dengan syarat mau bekerjasama dengan kita. Artinya mau membayar pajak dan mengirimkan orang-orangnya demi pembangunan ibukota Blambangan yang baru."
"Yang Mulia akan pergi sendiri?"
"Sementara Yang Mulia menghadap Tuan Schophoff atau Pieter Luzac, hamba akan menemui mereka. Barangkali laporan ini benar dan... siapa tahu bisa menguntungkan kita?"
"Hamba akan kerjakan!"
"Tapi sebelum berangkat, hem... tolong umumkan pada para saudagar Cina atau bangsa apa saja yang mau membeli tanah dan rumah-
.rumah kosong di Sumberwangi ini," Mas Ngalit mengelus- elus jenggotnya sambil memandang Juru Kunci.
"Yang Mulia akan menjual tanah dan rumah-rumah itu?" "Daripada oleh VOC diberikan pada orang-orang Mataram
dengan tanpa imbalan apa-apa? Apa salahnya jika kita dapat menjualnya dengan harga mahal. Bukankah memperingan beban pembayaran utang pada VOC?" "Tentu, Yang Mulia. Hamba sangat setuju." Juru Kunci tampak bersemangat. Sekilas ia ingat tamu-tamu istrinya yang sering memberinya hadiah. Tentunya mereka adalah orang- orang kaya. Istrinya akan senang mendengar itu. Maka ia akan segera menyampaikan berita itu pada istrinya.
"Jika Yang Mulia setuju, maka sebaiknya segera kita umumkan."
"Tidak perlu pengumuman itu, Yang Mulia." "Tidak perlu?"
"Ya! Tidak perlu. Karena jika hal ini di dengar Tuan Residen, maka ia akan mencegahnya."
"Mengapa?"
"Seperti halnya Probolinggo dan Pasuruan, VOC menjual tanah-tanah itu pada Cina dan uangnya masuk ke VOC tanpa memberi bagian pada kita. Nah, apa yang dapat kita perbuat? Jangan risau soal pembeli. Hamba akan membawa kemari sepekan mendatang." Juru Kunci mempe-rendah suaranya sambil mendekatkan mulutnya ke telinga Mas Ngalit, Sebentar kemudian menoleh ke belakang serta kiri-kanan. Seolah takut sesuatu. Mas Ngalit tertawa mendengar usul Juru Kunci itu.
Ah, cerdik orang ini. Pantas menjadi pembantunya sebagai patih Blambangan.
Setelah Juru Kunci pergi ia segera memanggil kepala pengawal dan memerintahkan agar bersiap untuk melakukan perjalanan keliling kembali. Di depan pasukan berkuda yang mengiringi Mas Ngalit itu terdapat seorang berkuda yang bertugas membawa bendera merah-putih-biru. Dan seorang lagi membawa umbul-umbul kuning, dan seorang lagi putih. Mendung masih mengiringi perjalanan mereka. Namun tiada hujan. Pohon-pohon nampak hijau menyedapkan mata. Nyiur melambai-lambai, seolah mengundang siapa pun saja agar memungut buahnya yang telah berjatuhan karena tiada lagi pemiliknya. Hamparan sawah luas terbengkalai menumbuhkan ilalang dan rumput pahitan. Kijang berdatangan dari hutan dengan tanpa susah sedikit pun menemani rumput muda di sawah yang tanpa padi itu lagi. Burung manyar, kutilang, cucakrawa atau gelatik, dan burung-burung pipit, beria-ria. Ayam hutan dan maleo juga tidak kalah ramai mengisi hutan baru di bekas huma yang merana. Monyet-monyet berebut pisang, duku, durian atau rambutan, dan buah-buahan lain. Jalan-jalan mulai ditumbuhi rumput. Tentu tidak lagi berdebu. Tapi jika dibiarkan, orang tidak akan melihat jika sedang ada ular yang bercengkerama di tengah-tengahnya. Ah, mengapa mereka meninggalkan semua ini? Mereka belum pernah pergi ke Madura yang kerontang dengan bukit-bukit kapurnya? Ah, andai saja mereka tahu, mereka akan sayang meninggalkan tanah garapan yang demikian hijau.
Masih ada beberapa perkampungan yang berpenghuni.
Tapi orang-orang tidak menyambut- I nya. Tidak memasang umbul-umbul seperti dulu kala mereka menyambut kedatangan Agung Wilis. Sekalipun ia berusaha meramahi mereka dengan senyumnya. Bahkan lambaian tangannya» cuma dibalas dengan tatapan mata yang hampa tanpa kesan. Memandang pasukan Kompeni yang mengawalnya itu, mereka nampak jijik. Sungguh orang Blambangan telah menjadi sekelompok orang yang tidak ramah dan tertutup pada siapapun. Atau karena aku berpakaian semacam pembesar Jawa mereka bersikap seperti itu? Karena aku telah menjadi Islam? Ah, bukankah waktu zaman Wong Agung Wilis juga sudah ada orang Islam bermukim di Blambangan? Mereka tak bersikap seperti itu? Bahkan kalau ia tidak salah dengar dulu Blambangan pernah membantu Adipati Sawunggaling yang Islam itu?
Yang lebih membuatnya heran adalah sikap para bekel. Hampir semua menyambutnya dengan dagu yang tertarik kaku. Tanpa senyum. Padahal bukankah beberapa bulan lalu mereka telah menerima perintah dari Pieter Luzac bahwa mereka harus meninggalkan Igama lama mereka yang kafir itu dan memilih Islam sebagai gantinya? Dan jika melihat cara mereka berpakaian sekarang tentunya mereka telah menjadi Islam. Lalu mengapa mereka bersikap seperti itu padaku?
Mereka memandangku dengan mata ketakutan. Seperti laiknya anjing melihat harimau. Mengapa? Mas Ngalit sibuk menebak-nebak. Tapi ia tetap tak peduli. Setiap memasuki pedesaan yang masih berpenghuni dan bertemu dengan para bekel, ia menekankan agar mereka mengirim tenaga untuk pembangunan ibukota Sumberwangi.
Tentu itu merupakan kesedihan baru bagi para bekel. Tiap kerja paksa yang demikian selalu menciptakan bencana baru. Mengapa orang mengatakan itu kerja paksa? Bukankah itu gotong-royong demi pengabdian pada negara? Mengapa harus dirasakan sebagai kerja paksa? Mas Ngalit bertanya waktu memberikan perintah. Semua yang dikerjakan demi kepentingan umum dan negara jangan dianggap kerja paksa. Bukankah setiap kemajuan memerlukan pengorbanan? Para bekel tidak bertanya dan membantah. Mereka tahu di belakang Mas Ngalit berdiri pasukan Kompeni yang telah membunuh lebih dari dua pertiga penduduk Blambangan. .
Namun sepeninggal Mas Ngalit barulah mereka, mengumpat dalam hati. Sambar geledek! Dia tidak kehilangan apa-apa. Tapi kami? Tanah kami, anak kami, semua tumpas karena pemimpin macam kamu! Pembangunan kota? Tentu bukan untuk kami! Bukan! Ah, kami tidak menikmati apa-apa dari pembangunan ibukota itu! Kamu dan orang-orang dekatmu! Juga orang-orang yang mampu membayar harga tanah yang dirampas dari tangan saudara-saudara kami. Kini kau jual atas nama negara dan kemajuan, kemakmuran, masa depan, tapi demi dirimu sendiri! Nah, sekarang telah kau rampas tanah dan rumah Yang Mulia Suratruna demi keenakan diri sendiri. Lain kali rumah dan tanah yang lain demi kekayaan pribadi atas nama negara. Sekarang semua kepentingan pasti diatasnamakan kepentingan negara. Setelah memakan empat hari perjalanan, melewati berbagai perkampungan dan hutan maka sampailah ia pada tujuan yang sesungguhnya. Sebuah perkampungan baru.
Jalan-jalan juga baru. Sawah dan ladang juga baru. Namun padi sudah mulai nampak berjajar rapi dan lurus-lurus seperti laiknya sawah orang-orang Blambangan. Tapi mereka bukan orang Blambangan. Yang bekerja di sawah nampak gelisah melihat kehadiran Mas Ngalit. Sungguh tidak satu orang pun menduga sebelumnya. Apalagi setelah Mas Ngalit berhenti dan memanggil seorang pemuda tanggung yang sedang mencari belut di pinggir sawah.
"Siapa namamu, anak muda?" Mas Ngalit bertanya dalam Jawa. Karena ia tahu persis bahwa pemuda itu bukan orang Blambangan. Anak muda itu menyembah.
"Sidin."
"Hemh... Sidin sudah lama tentunya kau pindah ke sini?" Mas Ngalit menyelidik sambil melirik ke semua arah. Dan pemuda itu tiba-tiba tampak resah. Orang-orang meninggalkan sawah satu per satu. Ada yang tampak tergesa- gesa. Sampai-sampai cangkulnya ketinggalan. Mas Ngalit melihat gelagat yang kurang bersahabat itu segera memerintahkan kepala pengawal agar menghentikan langkah orang yang tersisa. Tentu tidak susah buat kepala pengawal itu. Dengan sekali gertak, orang-orang yang tersisa itu meng- keret seperti siput. Dan terpatri di tempatnya.
"Aku memerlukan keteranganmu. Sidin. Jawablah dengan baik dan jujur. Jika tidak, kau akan mendapat celaka. Juga ayah-ibu serta semua saudara-saudaramu."
"Ba... baik... hamba memang sudah agak lama." Anak muda itu mulai takut.
"Berapa lama?" "Lupa..." "Lupa? Atau memang tidak mau mengaku?" "Ampun, Yang Mulia," anak itu menyembah. "Hamba
memang tidak ingat."
"Lupa. Tidak ingat! Rupanya kau sudah dilatih menjawab seperti itu. Baik! Kaulihat para pengawal yang menghentikan langkah orang-orang itu? Mereka juga sanggup menghentikan mulutmu berkata tidak ingat dan lupa. Ingin kau, aku memerintahkan mereka berbuat seperti itu? Aku bertanya baik-baik. Ketahuilah aku datang hanya untuk berkenalan dengan kalian. Ingin menolong kesulitan kalian. Ingin berdamai."
Pemuda cilik itu nampak ragu. Namun pandangan matanya masih menunjukkan kecurigaan.
Ah, masih lebih baik dari pribumi yang tidak menjawab sepatah pun jika ditanya, pikir Mas Ngalit.
"Jika demikian..." Kembali anak itu berhenti oleh keraguan.
Mas Ngalit membujuk terus dengan ramah dan memberi harapan-harapan.
"Ya. Jika demikian sebaiknya Yang Mulia menjumpai pemimpin kami."
"Pemimpin kamu? Siapa itu, Sidin?" "Raden Singa Manjuruh."
"Raden Singa Manjuruh?" Mas Ngalit mengulang. Sejenak ia tercenung. Orang itu memasang gelar "Raden" di depan namanya. Tentu orang Mataram. Dan pasti bukan orang sembarangan. Semua orang Mataram yang dikirim ke sini umumnya dari golongan sudra dan orang terpidana karena tindak kejahatan. Sedang yang perempuan umumnya adalah orang-orang yang dijauhi oleh orang sejenisnya karena digolongkan binal. Kini seorang raden ada di Blambangan dan membangun sebuah perdesaan yang cukup besar. Berapa pengir kutnya? Melihat caranya mengatur kehidupan desa itu, tentu orang ini mengerti ketatanegaraan. Ah, jika aku tidak salah, Singa Manjuruh tentu seorang pemberontak yang menyembunyikan diri.
"Di mana dia tinggal?"
"Di tengah desa ini. Di sebuah rumah besar yang halamannya berpagar batu merah."
Mas Ngalit menyebut dalam hati. Mereka mampu membuat batu merah? Dengan kata lain mereka ingin menetap untuk selamanya.
"Pergilah ke sana, Sidin! Katakan pada Raden Singa Manjuruh, bahwa aku, penguasa Blambangan, ingin berjumpa dengannya."
Sidin segera berbalik memunggungi Mas Ngalit, untuk kemudian berlari sambil membawa serenteng belut di tangan kanannya. Betapa senangnya anak itu, seperti terlepas dari sarang macan. Sementara itu kuda Mas Ngalit mengikutinya dari belakang. Mas Ngalit memang" enggan turun. Karena tanah becek. Kaki kuda puri terbungkus lumpur. Belum ada kelapa tumbuh tinggi di desa ini. Tapi banyak buah-buahan lain. Durian, nangka, sisa pohon-pohon hutan yang sengaja tidak ditebang.
. Dan kala Mas Ngalit sampai di dekat rumah yang dimaksud, menjadi amat terkejut. Beratus-ratus orang berkumpul di halaman rumah dan jalanan. Pada umumnya mereka adalah petani. Seolah mereka berbaris membentengi rumah sang pemimpin.
"Berilah kami jalan, agar kami dapat bersua dengan Raden Singa Manjuruh!" Mas Ngalit berkata dengan suara agak keras. Namun mereka tidak sudi menyibak apalagi menyimpang. Beratus-ratus orang itu telah bertekad melindungi pemimpin yang telah membawa mereka menemukan daerah subur itu. Mereka telah berikrar mati bersama demi mempertahankan tanah yang menjanjikan harapan baru dan cerah bagi masa mendatang.
"Tak kalian lihat kami datang bersama Kompeni? Sungguh, aku ingin bicara baik-baik dengan pemimpin kalian," Mas Ngalit berteriak kembali. Namun tetap saja tak membuat mereka bergeming. Malah mereka membuat barisan dengan bergandengan tangan satu dan lainnya. Makin lama makin banyak orang yang merelakan diri menjadi benteng hidup mengitari rumah Raden Singa Manjuruh. Baik di jalan, maupun di halaman rumah. Ngalit terkejut melihat kenyataan ini. Singa Manjuruh begitu dicinta oleh pengikutnya. Mengapa kawula Blambangan tidak mencintaiku seperti ini?
Kepala pengawal mulai tidak sabar. Ia mulai memerintahkan anak buahnya mengokang dan mengocok bedilnya. Sebentar lagi pembunuhan akan terjadi.
Pembunuhan? Mas Ngalit tersentak. Bau bangkai belum lagi habis. Kini pengawalnya akan menambah jumlah bangkai yang belum bersih di hutan-hutan Blambangan itu? Tidak!
Barangkali hal ini yang akan makin menjauhkan aku dari kawula Blambangan. Tapi orang-orang ini memang menjengkelkan. Tanah ini adalah wilayah Blambangan. Mereka membabat dengan tanpa izin dari penguasanya. Ah, aku harus bicara baik-baik dengan Singa Manjuruh, kata Mas Ngalit dalam hati. Jika aku mengambil jalan kekerasan, mungkin mereka melawan. Dan aku serta para pengawal ini akan punah sekalipun mereka juga akan membayar dengan nyawa beberapa yang tertembak. Maka kini Mas Ngalit
Tersenyum.
"Sungguh! Aku akan bicara baik-baik. Atau sebaliknya? Aku mengalah sekarang dan akan kembali dengan membawa pasukan? Pikirkanlah itu!"
Beberapa jenak suasana menjadi hening. Burung-burung pipit dan gelatik mengisi kesunyian dengan nyanyian mereka. Angin dingin berembus perlahan. Seolah embusan napas bidadari yang menyejukkan. Pandang mata beratus-ratus orang menajam. Para pengawal gelisah menunggu perintah. Keringat dingin membasahi tangan. Demikian juga kaki yang terbungkus sepatu itu. Namun tiba-tiba semua orang dikejutkan oleh suara dari rumah Singa Manjuruh. Seorang mengenakan baju lurik dan blangkon di kepalanya muncul. Tepat di tengah beranda. Masih muda.
"Mengapa Kompeni kemari? Apa salahku?"
Semua yang sedang berbaris dan bergandengan tangan menoleh padanya. Mas Ngalit tercengang. Untuk beberapa bentar ia tidak berkata-kata. Sampai Singa Manjuruh mengulangi pertanyaannya.
"Bukan Kompeni. Aku adalah penguasa bumi Blambangan. Mas Ngalit. Aku ingin bertemu dengan Raden Singa Manjuruh. Ingin bicara dengan baik-baik. Mengapa justru disambut dengan permusuhan?"
"Sebab Yang Mulia datang bersama rombongan pembunuh."
Hawa panas menampar muka Mas Ngalit seketika. Orang Jawa pun banyak yang tidak suka pada Kompeni? Jadi mereka membabat hutan di Blambangan ini untuk menyingkir dari kekuasaan VOC?
"Bukan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk keselamatanku. Juga untuk menyelamatkan Blambangan."
"Sepanjang pengalaman yang hamba lihat mereka bukan penyelamat! Tapi pembunuh dan perampok. Mereka merampasi tanah kami, jengkal demi jengkal. Baik dengan cara membunuh ataupun menipu."
Mas Ngalit masih duduk di punggung kudanya. Hatinya berdesir mendengar perkataan yang berapi-api itu.
"Hamba Singa Manjuruh itu. Yang membabat hutan ini atas perkenan putra terbaik Blambangan, Mas Ramad Surawijaya." "Siapa yang memberinya kuasa? Sehingga ia berani memberi perkenan?" Mas Ngalit teringat akan nama itu. Nama yang pernah ditakuti di seluruh bumi Blambangan. Pemuda putra patih Blambangan, Wong Agung Wilis, yang pernah bergelar Mas Puger.
"Siapa? Mengapa Yang Mulia bertanya demikian?
Pertanyaan yang seharusnya terpulang pada Yang Mulia sendiri." Kini Singa Manjuruh turun dari beranda. Ia maju dan menguak barisan demi barisan yang melindunginya.
Sementara itu seorang perempuan muda, berkulit hitam manis, bertubuh semampai menggantikannya di beranda. Tapi di tangannya terdapat sebuah bedil yang teracung ke dada Mas Ngalit. Terkesiap darah Mas Ngalit. Nyawanya dalam ancaman. Jika ia tidak hati-hati, akan musnah di tangan seorang perempuan. Orang asing di bumi Blambangan tapi berani menghinanya semacam itu. Dan setelah Singa Manjuruh berdiri di hadapannya dengan membelakangi barisan pelindungnya, ia baru mampu mengucapkan kata- kata. "Apa arti semua ini?"
"Bukankah itu pertanyaan hamba yang tadi? Apa arti kedatangan Yang Mulia ini?"
"Astaga! Sangat membingungkan. Bukankah sudah aku jelaskan? Aku datang untuk bicara baik-baik. Sebab aku merasa sebagai keturunan Tawang Alun yang sah. Dan aku berhak memerintah atas bumi Blambangan ini."
"Apa yang akan dibicarakan? Hamba sudah di sini."
"Tak dapatkah kita duduk dengan baik-baik dan tanpa laras senjata yang teracung?"
"Yang Mulia telah mulai dengan senjata teracung ke dada kami. Salahkah jika kami melakukannya untuk membela diri?"
"Ya Allah," Mas Ngalit menyebut. "Lagi pula kita bicara di sini lebih baik agar teman-temanku ini mengerti dan mendengar langsung hasil pembicaraan kita."
"Baiklah jika demikian," Mas Ngalit menyerah. "Seperti telah kukatakan, aku datang sebagai seorang penguasa di bumi Blambangan. Dan aku perlu menanyakan, siapa yang bertanggung jawab atas pembabatan hutan kami ini?"
"Semua yang berdiri di hadapan Yang Mulia penanggung jawabnya."
"Bagus, jika demikian apakah kalian akan menggunakan tempat ini untuk tinggal tanpa seizin kami? Artinya akan mengambilnya dengan paksa?"
"Sudahlah adil jika pertanyaan itu juga dilontarkan pada Belanda atau para pedagang asing. "
"Mereka membayar harga tanah yang mereka tempati itu.
Pedagang Cina yang kini banyak membeli tanah di Sumberwangi itu sebagai salah satu misal "
"Kami juga membayar, sekalipun dengan tanpa uang. Kami telah menumpahkan darah dan keringat. Apakah itu kurang?"
"Pembabatan ini tidak berguna bagi Blambangan. Tapi sekadar perampasan kasar demi perut kalian sendiri."
Singa Manjuruh hampir tidak sabar. Ingin ia melompat menerkam pemuda yang duduk di atas kuda itu. Namun ia sadar, itu akan mengundang bala tentara Kompeni waktu berikutnya. Ia mengerutkan giginya. Beberapa bentar kemudian ia mengembuskan napas panjang. Ia memutuskan untuk menghadapi dengan kepala dingin.
"Mengapa jika kami yang melakukannya selalu saja salah?" Singa Manjuruh merendah. "Mengapa pedagang-pedagang Cina yang saat ini juga melakukan pembabatan di dekat Sumberwangi tidak terkena tuduhan? Apakah karena mereka akan menggunakannya sebagai kebun tebu itu? Demikian halnya orang-orang Belanda di hampir seluruh bagian Blambangan. Melakukannya untuk mendirikan loji-loji. Tapi Yang Mulia tidak mengusir mereka."
"Aku juga tidak mengusir kalian seperti aku tidak akan mengusir mereka semua. Tidak! Aku datang justru ingin bekerjasama dengan kalian. Dan menjadikan kalian bagian dari Blambangan. Jangan tinggal di sini sebagai orang asing."
"Tidak salahkah pendengaranku ini?" Singa Manjuruh tak percaya. Ia tajamkan pandangannya pada Mas Ngalit. Juga semua pengikutnya. Saling pandang satu dengan lainnya.
"Demi Allah aku akan perlakukan kalian sama dengan mereka asal kalian mengakui kekuasaan dan pemerintahanku atas negeri ini. Aku percaya bukan waktunya lagi kita saling berperang. Dan seharusnya kita yang tinggal di Blambangan ini, pribumi atau bukan, tapi hidup di sini, bersatu untuk membangun negeri ini dari reruntuhan karena perang."
"Alhamdulillah... kami menerima tawaran ini dengan senang hati."
"Inilah yang kami kehendaki. Dan, apa nama desa ini?" "Belum kami beri nama, Yang Mulia."
"Baiklah... Jika demikian aku yang akan memberi nama.
Setuju?"
"Setuju, Yang Mulia."
"Karena yang memimpin pembangunan desa ini adalah Singa Manjuruh, maka desa ini aku beri nama Singa Juruh."
Semua pengikut Singa Manjuruh berteriak girang mendengar itu. Mereka kini telah mendapatkan tempat tinggal baru. Daerah yang subur melebihi daerah yang mereka tinggalkan di Mataram atau Madura. Sudah jenuh rasanya mereka diburu oleh kekerasan dan kesulitan hidup. Kini Mas Ngalit menjanjikan perlindungan. Menawarkan kerjasama. Apa beratnya mengakui kekuasaannya? Memang sejak dulu mereka bukan penguasa. Singa Manjuruh tidak pernah berkeinginan menjadi seorang penguasa. Ia mengerti benar, seluruh pengikutnya memang mengharap-harap agar mereka mendapatkan kedamaian. Dibuktikan oleh sorak-sorai mereka begitu mendengar pernyataan Mas Ngalit.
Namun senyum mereka itu tidak lama bertengger di bibir mereka. Karena sebentar kemudian Mas Ngalit berkata lagi.
"Semua kalian adalah bahagian dari Blambangan. Karenanya tidak pantas jika kalian tinggal diam saat Blambangan sedang membangun ibukotanya. Sanggupkah kalian membantu pemerintah?"
"Sanggup," Singa Manjuruh menjawab dengan suara berat. "Pembangunan membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan
tenaga dan uang. Dan itu dituntut dari kalian. Juga dari semua orang Blambangan.
Itu sebabnya kami menuntut sepertiga hasil panen kalian diserahkan pada pemerintah dan sedikitnya dua puluh orang tiap harinya dikirim ke Sumberwangi untuk pembangunan ibukota Blambangan."
Semua orang ternganga. Juga Singa Manjuruh. Inikah imbalan yang harus mereka berikan atas desa yang kini bernama Singa Juruh ini? Dua puluh orang tiap hari? Kerja paksa? Kerja tanpa gaji? Tapi mereka tidak bisa menolak lagi. Sampai Mas Ngalit meninggalkan tempat itu, mereka-masih belum beranjak dari tempat mereka berdiri." Perjuangan begitu panjang untuk menghindarkan diri dari perbudakan oleh bangsa asing ternyata cuma menghasilkan...
Namun Singa Manjuruh merasa bahwa" jika menolak cuma melahirkan perlawanan yang sia-sia. Sedang tampaknya anak buahnya telah kehilangan semangat untuk itu. Maka dalam keputus-asaan ia menunduk. Pandangan matanya menghunjam tanah. Seolah ingin mewawancarai bumi, mengapa kau memberiku nasib yang sedemikian buruk? Langit, mengapa kau tak menjatuhkan, berkat?...
Sementara itu gelegar demi gelegar sayup terdengar dari jarak yang amat jauh. Hutan seputar Sumberwangi telah dibabat oleh kuli-kuli yang bekerja untuk para saudagar, baik bangsa kulit putih maupun kuning. Namun yang lebih banyak adalah kulit kuning. Juru Kunci, melalui istrinya, telah memasarkan tanah Sumberwangi pada mereka.
Mendatangkan banyak uang bagi Mas Ngalit dan Juru Kunci sendiri. Walau sebagian dibayarkan pada VOC sebagai cicilan utang Blambangan.
Tampaknya saja para saudagar itu memang bersusah- susah. Tapi Mas Ngalit tidak melihat bahwa mereka cukup membayar harga tanah itu dengan penjualan kayu-kayu raksasa ke galangan kapal Gresik, gedang yang lebih kecil mereka kirim gelombang demi gelombang ke Jepara seoagai bahan untuk membuat ukir-ukiran. Sebenarnyalah Mas Ngalit tidak pernah memikirkan bahwa ia telah mengambil langkah yang jauh bertolak belakang dari pemerintah para pendahulunya di Blambangan. Yang ia pentingkan ialah bagaimana mendatangkan uang untuk menunjukkan pada kawula Blambangan dan seluruh dunia bahwa dialah pembangun. Ia adalah Arok-nya Blambangan. Apa itu pemerintahan Wong Agung Wilis? Cuma mengundang pertentangan dan perang! Sekarang ini yang diperlukan adalah kerjasa-ma antar bangsa. Bukan melawan, atau menentang bangsa-bangsa lain yang ingin berniaga dan ingin mengambil peruntungan di Blambangan. Jika itu akan mendesak dan mengalahkan kawula, ya... salah sendiri, kenapa kawula malas bekerja keras. Malas bersaing dengan mereka. Malas membantu atau terlibat dalam pembangunan negeri.
Lihat itu Baba Song dengan teman-temannya! Lihat!
Mereka begitu giat membabat hutan. Mereka begitu murah mengeluarkan uangnya demi Blambangan. Juga bagiku sendiri. Mereka begitu baik. Dan memang para pedagang Cina itu sangat baik pada Mas Ngalit. Hampir setiap hari mereka berkunjung ke istana. Demi kepentingan pembangunan istana mereka mempersembahkan bahan-bahan bangunan, baik yang berupa kayu, batu merah, gamping, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengirim bahan makanan, baik untuk para pekerja maupun persediaan makanan bagi istana sendiri.
Semua datang sebagai ucapan terima kasih atas izin tinggal dan pengelolaan tanah serta kekayaannya.
Mas Ngalit tidak peduli atas semua kerusakan hutan bumi semenanjung Blambangan. Tidak peduli kayu-kayu yang bergaris tengah dua depa itu,.yang tidak pernah tumbuh di Negeri Belanda ataupun Cina, dan sepanjang lebih dari seratus depa, tumbang satu per satu, dan dilayarkan ke negeri-negeri utara. Apalagi jika yang melakukannya Baba Song. Bukan cuma kayu yang mereka rampok. Tapi juga harimau, kijang yang bertanduk aneh itu, bahkan buaya serta biawak, sampai- sampai ular dan kera putih. Belum lagi burung merak, burung bayan, dan ayam hutan. Pendek kata semua yang dapat mempertebal kantong para saudagar, mereka keruk baik secara sah maupun tidak, tahap demi tahap. Mas Ngalit tambah lama semakin tidak sempat memperhatikan semuanya. Pekerjaannya menjadi bupati kian banyak. Untuk itu ia membutuhkan banyak pembantu. Mana yang harus mengurus keamanan, keuangan, pertanian, perniagaan, pajak dari bandar, urusan dengan manca negara, juga urusan dengan VOC.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama Tan Eng Gwan telah juga mempersembahkan para gadis cantik, dan ada beberapa di antaranya yang berkulit kuning dan bermata sipit. Mereka bertugas sebagai; penunggu taman, gadis pengipas, pembersihan, atau apa saja. Pendek kata jika seorang berkunjung ke istana, maka mereka akan melihat di mana- mana ada wanita muda cantik. Kecuali pengawal, semua pekerjaan di istana itu dikerjakan oleh wanita. Dan hampir semua itu dikirim oleh Juru Kunci dan Tan Eng Gwan. Dengan demikian Mas Ngalit tidak lagi sempat pulang ke Pakis,
Tentu saja itu menyenangkan Schophoff. Tiap kali ia bersua adipati muda itu ia memuji,
"Aha, ternyata Yang Mulia pintar. Sekalipun masih muda, tapi Yang Mulia tidak kalah dari pada adipati yang lebih tua. Sepatutnya Gubernur Jenderal di Batavia menganugerahkan bintang jasa bagi kemampuan Yang Mulia membangun negeri ini. Seharusnya Yang Mulia menjadi adipati teladan. Karena kami menilai masa depan Blambangan akan menjadi yang termakmur di seluruh negeri yang bergabung dengan pemerintahan agung Batavia."
"Tuan terlalu mengada-ada," Mas Ngalit menjawab sambil tersenyum kala ia mengantar tamunya memeriksa pembangunan ibukota baru itu.
"Tidak, Yang Mulia. Gubernur sendiri puas menerima laporan kami. Ia katakan seluruh adipati hendaknya mencontoh Yang Mulia dalam mengatur kadipatennya."
"Ah..." Jauh dalam lubuk hatinya melambung. Juru Kunci ikut bangga mendengar pujian itu. Ia merasa telah berjasa memilihkan seorang yang cakap buat VOC.
"Namun masih ada sedikit ganjalan. Yang Mulia masih teringat pada Rsi Ropo dari Songgon itu?"
"Rsi Ropo?" Mas Ngalit dan Juru Kunci sama-sama terkejut. "Apakah dia tidak mampus bersama Jagapati?" Mas Ngalit menyambung dengan penuh keheranan.
"Baik. Kita percaya bahwa dia mati. Tapi kenapa Songgon sampai sekarang tidak tunduk pada kita. Bahkan kita lihat seluruh kawula Blambangan tidak bersedia membayar pajak. Semua ini tidak mungkin berjalan dengan sendirinya." "Jadi menurut Tuan ada yang mengatur? Atau dengan kata lain diatur oleh Songgon."
"Pieter Luzac mencurigai Songgon. Tapi VOC tidak mungkin bertindak tanpa perkenan Yang Mulia," Schophoff memancing.
"Hamba akan mencoba melihat ke sana. Peperangan tak cuma menimbulkan korban atau kerusakan. Tapi yang lebih penting adalah penghamburan pembiayaan yang cukup besar. Karenanya jika bisa ditempuh jalan damai, sebaiknyalah kita melakukannya."
"Ha... ha... ha... ha..." Schophoff bergelak. Cukup cerdas adipati yang satu ini. Bangunan mesjid di depan alun-alun masih belum selesai. Dermaga juga diperlebar. Rumah-rumah besar juga didirikan sebagai tempat menimbun barang-barang yang belum sempat dikirim ke tempat tujuan. Atau barang yang menunggu kapal-kapal dagang. Ada empat rumah besar. Salah satu di antaranya adalah milik Han Tian Boo. Dengan kata lain orang itu tak pernah menyewa milik kadipaten bagi kepentingan perniagaannya. Ia bahkan menempatkan pekerja untuk menjaganya. Meski begitu sang Adipati tidak merasa dirugikan. Sebenarnyalah Mas Ngalit tidak pernah rugi dengan segala tingkah semua orang asing di negerinya. Karena yang rugi adalah negara dan kawula Blambangan. Malah secara pribadi Mas Ngalit mendapatkan banyak keuntungan.
Dan Mas Ngalit membuktikan kata-katanya pada Schophoff.
Ia segera bertandang ke Songgon yang memang luput dari pengamatannya selama ini. Apa yang harus aku lakukan terhadap pribumi sebangsaku ini? Mengapa mereka tak mau beker-jasama dengan bangsa asing yang baik hati menyediakan modal bagi kemajuan negara? Sekali lagi aku harus menyadarkan mereka! Harus! Atau Kompeni kembali menumpahkan darah mereka? Pergumulan terus terjadi di dadanya yang bidang d dan berbulu itu. Kendati masih muda kumis tebal telah menghiasi wajahnya. Rapi tertata di bawah hidung mancung. Cambangnya juga tumbuh dengan manis sampai ke pangkal rahangnya. Semua itu membuat iri kaum lelaki. Dan memang harus mereka akui, tentulah banyak wanita akan bersimpuh di kaki Mas Ngalit.
Perjalanan amat sukar. Mas Ngalit tidak sanggup menempuhnya dalam waktu satu hari. Musim penghujan membuat belukar menutup jalan-jalan setapak dalam hutan. Penjalin yang menjalar panjang-panjang itu menyodorkan duri-duri tajam. Kuda Mas Ngalit tidak terbiasa mengatasi kesulitan semacam itu. Seperti itu pula halnya Mas Ngalit.
Tidak terlatih melintasi daerah sulit. Kendati ia adalah saudara seayah dengan Jagapati yang gagah perkasa itu. Karena itu ia mengajak para pengawal bermalam di Lo Pangpang, kemudian besoknya bermalam di Pakis. Baru hari ketiga ia dan pengawalnya sampai di Songgon. Buat sesaat Mas Ngalit menghentikan langkah kudanya. Demikian pula para pengawal. Sebelum mereka memasuki batas desa Songgon, mereka sudah melihat hamparan sawah hijau yang begitu luas. Pematang-pematang tertata rapi dan bersih. Kendati mereka tak melihat seorang pun yang dapat dimintai keterangan. Namun Mas Ngalit menduga, tentunya daerah ini tak terusik oleh perang. Beberapa ekor anjing tampak
mondar-mandir di pematang seolah mencari sesuatu. Mencium-cium tanah. Tentunya mencari tikus.
Namun kalau kuda Mas Ngalit dan rombongan mulai melangkah, mendadak anjing-anjing menggonggong. Bahkan melolong seperti serigala yang kelaparan. Kuda Mas Ngalit seperti ketakutan. Apalagi setelah kelompok demi kelompok anjing-anjing mendekati. Mas Ngalit penasaran. Ia sentuhkan tumit ke perut kuda sebagai perintah agar si kuda mempercepat larinya. Namun rombongan anjing itu terus mengejar seperti hantu.
Para pengawal hampir kehabisan akal. Mereka mempersiapkan bedil untuk mengusir gerombolan anjing. Tapi Mas Ngalit segera mencegah. Ia tahu itu akan semakin menyakitkan hati kawula. Mau tak mau mereka harus berteriak-teriak saja memaki dan mengusir hewan peliharaan orang Songgon itu. Masuk batas desa mereka berhenti lagi. Para pengawal memberanikan diri melompat turun dan mengambil batu serta kerikil yang berhamburan di tepi jalan. Kemudian melempari gerombolan anjing yang menyambut dan mengantar mereka ke tapal batas itu. Kini terpaksa mereka menjauh dan menghindar sambil mengumpat tanpa makna.
Mas Ngalit bernapas lega. Anjing-anjing itu menjauh. Tapi kini keheranan merambati hatinya. Deretan rumah di kiri- kanan jalan sepi tanpa penghuni. Ke mana mereka? Di sawah sunyi, di pedesaan pun senyap. Padahal jika melihat bunga- bunga, pohon-pohon semua terawat rapi. Tanpa bersaing dengan rumput dan ilalang. Pelan-pelan kuda mereka melangkah lagi. Hampir tak ada serumpun pun rumput tumbuh di jalan yang dipadatkan oleh pasir dan batu itu. Dua kali kecil mengapit jalan itu. Gemercik suara air membawa kedamaian di hati. Rumah-rumah pun berjajar rapi memberikan sapaan tersendiri. Demikian pun nyiur, kenari, atau kenanga yang meneduhi sepanjang jalan. Terus saja mereka masuk. Semakin tercengang. Di tengah-tengah desa itu ada sebuah rumah besar. Bangunan kuno. Berpagar batu- batu kali. Pelatarannya amat luas. Pendapa juga lebar. Tentu ini rumah Rsi itu, pikir Mas Ngalit. Maka ia membelokkan kudanya ke halaman.
Tiba-tiba langkah kuda Mas Ngalit terhenti.
Karena Mas Ngalit terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Seorang perempuan muda dengan telanjang dada berdiri di titian pendapa. Ia gosok matanya. Perempuan muda itu tersenyum sambil menelangkupkan kedua telapak tangannya di antara kedua susu yang montok dan berkulit mulus. Lepas tanpa kutang dan apa pun sebagai penutup.
Sebagai penutupvkaki wanita itu mengenakan kain putih yang melingkar sampai ke bawah pusarnya. Pending emas berkilau ditimpa mentari yang menerobos di sela mendung. Gelang dan binggal menghias dua pergelangan kaki dan tangan menandakan bahwa wanita muda itu bukan sudra. Untaian mutiara melingkar di leher jenjang yang menyangga wajah bulat telur dengan hidung mancung. Mata berbentuk sebungkul bawang dihias oleh bulu lentik dan diteduhi oleh alis seolah garis seperempat lingkaran. Gigi berwarna hitam mengkilat seperti bulu kumbang berbaris rapi di sela bibir tipis berwarna merah bercampur ungu seolah warna kulit manggis yang sedang merekah, menandakan bahwa seharusnya wanita muda ini tinggal di puri istana Blambangan, zaman Wong Agung Wilis. Tapi usianya masih sangat muda. Tentu bukan salah seorang selir atau istri Mangkuningrat. Lalu siapa dia?
Hati Mas Ngalit berdebar. Darah mudanya bergelora. Tapi wanita itu tidak sendiri. Di belakangnya berdiri lima orang wanita yang berbusana seperti halnya yang terdepan. Semua wanita. Tak seorang pun lelaki. "Dirgahayu, Yang Mulia.
Silakan naik ke pendapa dan duduk." Kembali suara merdu seperti suara burung cucakrawa membangunkan lamunan Mas Ngalit.
."Eh... hamba ingin bersua de..." Mas Ngalit migup. Kulit wanita ini tidak kuning sepefti biasa wanita yang dipersembahkan oleh Han Tian Boo. Sawo matang. Bahkan agak sedikit hitam. Tapi manis. Rambutnya ikal tersanggul di atas kepala, dihiasi tusuk konde emas.
"Ingin bersua dengan Rsi Ropo?" Wanita itu memotong. "Ya, betul "
"Beliau sedang tak ada. Silakan naik. Barangkali hamba dapat menolong kepentingan Yang Mulia, atau...
"Tidak. Hamba cuma memerlukan dia." Mas Ngalit masih saja duduk di pelana. "Sayang." Mas Ayu Tunjung mendengus. "Bukan kebiasaan satria Blambangan tidak berlaku ramah seperti itu. Apalagi seorang adipati."
Merah wajah Mas Ngalit mendengar itu. Perempuan muda itu sudah tahu namaku? Kedudukanku?
"Bukankah Mas Ngalit seorang yang berdarah Tawang Alun? Ah, siapa yang tak pernah dengar nama Tawang Alun di bumi Semenanjung ini? Seorang satria sekaligus brahmana.
Mengapa keturunannya tidak lagi menghormati kekudusan pertapaan leluhurnya sendiri?"
"Laa ilaaha illal laahu Muhammadur Rasuulullaah," Mas Ngalit menyebut sambil mengembuskan napas panjang. Para pengawal memandangnya heran. Songgon bekas pertapaan leluhurku? Tawang Alun? Dan... kembali ia menghela napas panjang. Ingin membuat dadanya lega. Kemudian ia berdoa lagi dalam hati agar terbebas dari godaan syaithan. Namun ia belum juga turun.
"Siapa yang sedang berhadapan dengan aku ini? Dan bagaimana aku harus memanggil?"
"Tentu Yang Mulia tidak pernah rhengenal hamba. Memang bukan wanita ternama seperti halnya Mas Ayu Arinten. Tapi tidaklah salah jika hamba menjelaskan bahwa hamba adalah adik dari Pangeran Mas Sutajiwa, putra Ramanda Mangku- ningrat anumerta, putri bungsu yang lahir dari Paramesywari Mas Ayu Chandra anumerta.
Dan kemudian Ibunda bergelar Mas Ayu Na-wangsasi.
Hamba adalah Mas Ayu Tunjung."
"Ya Allah, Ya Rabbi..." Mas Ngalit terkejut. Dengan mulut ternganga ia pelan-pelan turun dari kudanya. "Ampunkan hamba..." Mas Ngalit kehilangan pegangan. Para pengawal makin tertegun. Namun mereka ikut turun dari kuda. "Waktu berlalu cepat sekali, zaman pun telah berubah, membuat hamba tidak ingat pada Yang Mulia. Zaman telah maju dengan pesatnya..." Mas Ngalit berusaha memulihkan wibawanya. Namun Ayu Tunjung segera memotong.
"Zaman boleh berubah, bahkan boleh saja sepesat anak panah, tapi peradaban tidak boleh dihancurkan," tegasnya.
"Justru kedatangan kami kemari untuk tujuan itu." Ngalit menemukan dirinya kembali. "Kami perlu membicarakan dengan Rsi Ropo yang selama ini dinilai oleh pihak Belanda sebagai penghambat berkembangnya peradaban di Blambangan."
"Jagat Dewa Pramudita! Ya, Hyang Dewa Ratu." Ayu Tunjung pura-pura terkejut. "Belanda memberi penilaian semacam itu? Sang Rsi penghambat berkembangnya peradaban? Sungguh hamba tidak mengerti."
"Baiklah. Hamba akan jelaskan. Tapi hamba mohon Yang Mulia menjawab kami dengan sejujurnya."
"Di Blambangan satria pantang berkata dusta."
"Baik. Siapakah yang menculik Yang Mulia dan membawa kemari? Bukankah Rsi Ropo yang keparat itu?"
"Yang biasa menculik bukan seorang Rsi. Brahmana tidak pernah bicara dengan paksaan seperti itu. Hamba datang sendiri dengan sukarela. Justru saat Rsi tidak ada di tempat. Sampai sekarang pun beliau belum pulang."
"Hai. Benarkah? Apakah hamba bisa percaya? Jika benar demikian, mengapa tak seorang pun di sawah maupun di rumah?"
"Jangan samakan brahmana dengan para kawula.
Lenyapnya kawula dikarenakan mereka takut." "Takut?"
"Ya! Yang Mulia datang bersama para pembunuh!
Kompeni!" "Mereka pengawal hamba dan penjaga keamanan di Blambangan dan seluruh Nusantara."
"Penjaga keamanan? Pada siapa mereka memberikan keamanan? Kawula tak pernah merasa aman dengan adanya mereka di negeri ini."
"Siapa bilang begitu?"
"Salahkah telinga hamba yang mendengar jerit tangis wanita-wanita dan anak-anak yang kehilangan suami atau ayah-ayah mereka? Ke mana mereka semua yang tidak merelakan tanahnya dirampas untuk dijual pada pemilik modal besar itu? Siapa yang harus bertanggung-jawab jika bukan Kompeni? Atau barangkali... barangsiapa tunduk dan taat pada penjahat, telah menjadi penjahat dengan tanpa sesadarnya."
"Astaga! Jika demikian semua orang harus melawan? Yang Mulia menganjurkan mereka melawan?"
"Merelakan diri dipaksa, merupakan kejahatan bagi dirinya sendiri. Melawan jauh lebih mulia dari pada bersekutu dengan penjahat."
Mas Ngalit terdiam lagi. Kehabisan akal. Berkali menoleh pada para pengawal yang mulai tidak-sabar. Tapi mereka tidak dapat menangkap makna pembicaraan kedua orang itu. Meski demikian dalam hati mereka timbul berbagai tanya. Mas Ngalit yang biasa menjadi pujaan para selir itu kini kuncup meriup. Seolah semua wibawanya punah ditelan keanggunan Ayu Tunjung. -
"Jika demikian, tolonglah hamba, Yang Mulia, beritahukanlah pada mereka agar mereka sudi mempersembahkan upeti demi kejayaan Blambangan. Dan kirimkan mereka bergotong-royong membangun ibukota baru bagi Blambangan yang kita cintai ini," Mas Ngalit mengiba. "Luar biasa manis kata-kata Yang Mulia ini. Tapi sayang!
Sungguh menyesal hamba tak dapat membantu. Karena orang Songgon cuma mau mendengar kata Rsi Ropo. Bukan hamba dan bukan Mas Ngalit. Lihat saja, tak seorang pun di Songgon menjatuhkan diri menyembah Yang Mulia. Semua berlari."
"Padahal hamba ingin membangunkan kembali kejayaan Blambangan. Cakrawarti..."
"Ampun, Yang Mulia. Jangan bicara itu di depan kawula.
Sebab mereka akan menjadi muak.
Kejayaan Blambangan tidak bisa dicapai dengan menjual anak-anaknya menjadi budak bangsa asing yang menguasai modal. Juga tak bisa dengan membiarkan bumi kita dijarah- rayah seperti sekarang ini. Ya, dijarah-rayah oleh pribumi yang ingin memperkaya dan merajakan diri sendiri. Di samping perampok-perampok asing yang datang rgelombang demi gelombang."
"Yang Mulia..."
"Bagaimana tidak harus kukatakan perampok? Mereka pasti tahu, seperti semua orang tahu, bahwa kekayaan yang terkandung dalam bumi ini jauh lebih mahal dari harga tanah yang mereka beli dari Yang Mulia."
"Tapi..."
"Lebih dari semua itu, kawula Blambangan tahu persis, bahwa sebenarnya masih ada yang lebih berhak memerintah negeri ini, dari Yang Mulia. Kendati ia seorang wanita."
"Tapi..."
"Hamba tak dapat melayani "
"Tunggu, Yang Mulia! Masih ada lagi yang wajib kita persoalkan. Songgon berhubungan dengan para pedagang asing secara langsung. Mereka meluputkan diri dari cukai. Juga selalu mengusir pedagang atau saudagar yang telah kami izinkan masuk untuk membeli dan menjual di seluruh wilayah Blambangan!
"Sekali lagi! Songgon tidak sudi terikat oleh peraturan yang dibuat oleh bandit-bandit! Mereka semua telah membayar pada Yang Mulia dan patih Blambangan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang memaksa semua orang harus berjual-beli dengan mereka. Apakah Yang Mulia tidak tahu bahwa mereka membeli barang kami dengan harga murah, sedang mereka menjual dagangan mereka dengan harga kelewat tinggi?"
"Itu..."
"Hamba tak dapat melayani Yang Mulia lebih banyak lagi." Ayu Tunjung kembali mengernyitkan dahinya. Pangkal alisnya terangkat. Suatu pemandangan yang mengundang pesona tersendiri.
"Camkanlah ini," kata wanita berbibir mungil itu. "Pikirkanlah! Kebiasaan memaksa adalah kebiasaan bandit!" Mas Ayu Tunjung segera memunggunginya. Kemudian meniti naik pendapa. Sementara Mas Ngalit tak mampu bergerak.
Mulutnya ternganga. Matanya tak berkedip.
Aduhai, mulusnya punggung yang telanjang itu. Dan, ah, ia perhatikan lenggangnya seperti blarak (daun pisang serta pelepahnya sudah kering, yang dengan sendirinya patah karena ketuaan namun tetap menempel pada dahannya) yang terkulai karena patah. Tangannya seolah busur yang terayun perlahan. Suara gemerincing binggal di kedua belah pergelangan kaki disertai suara kain ketat pembungkus kaki itu bergeser seolah undangan bagi Mas Ngalit untuk mengikutinya ke peraduan. Tapi Mas Ngalit tidak berani melakukannya. Sebab Ayu Tunjung tentulah akan mengusirnya seperti mengusir anjing kurap....